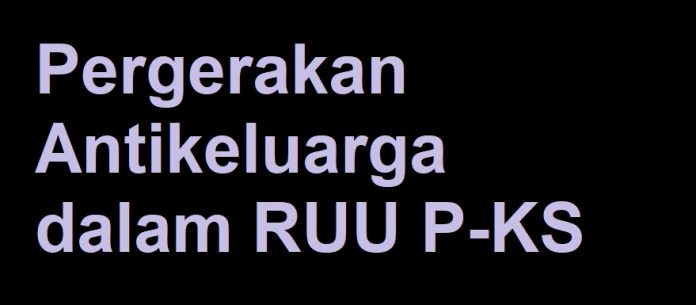Oleh: Sarah Mantovani*
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang sering diakronimkan dengan RUU P-KS telah memasuki episode baru. RUU kontroversial yang telah diusung oleh Komnas Perempuan dan draftnya dirumuskan serta disusun oleh berbagai organisasi Feminis maupun LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) sejak tahun 2012 ini diputuskan oleh DPR untuk ditarik pembahasannya dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas 2020.
Sebelumnya, DPR mengaku penarikan RUU ini atas usulan dari Komisi VIII. Penarikan ini tentu bukan tanpa alasan yang jelas. Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, sebagaimana dilansir nasional.kompas.com, menyebut pembahasan RUU ini agak sulit dari beberapa sisi.
Pertama, dari sisi lobby-lobby ke berbagai fraksi menemui jalan buntu. Kedua, selalu terjadi perbenturan saat membahas tentang judul dan definisi kekerasan seksual. Ketiga, masih terjadinya perdebatan mengenai pemidanaan terhadap pelaku. Lantas karena ketiga alasan ini, Komnas Perempuan menuduh DPR tidak punya kemauan politik yang kuat untuk memberikan keadilan pada korban.
Walau demikian, Rapat Paripurna yang digelar pada 16 Juli 2020 lalu menghasilkan keputusan bahwa RUU P-KS akan dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan alasan lain untuk mempercepat pengesahan RUU Penanggulangan Bencana yang lebih prioritas, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com.
Saat mendengar hal ini, banyak orang khususnya umat Islam mungkin belum menyadari, ada pergerakan antikeluarga dalam RUU ini. Antikeluarga yang dimaksud ialah para pengusung maupun pendukung RUU P-KS menolak relasi antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan fitrahnya.
Misalnya, laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ataupun laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga jika perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin atau pencari nafkah meski suaminya mampu maka dianggap sebagai bagian dari kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender.
Selain itu, mereka juga menolak larangan atas pornografi sebagai penyebab adanya kekerasan atau kejahatan seksual yang terjadi, mereka malah menyalahkan patriarki dan relasi kuasa yang konon dimiliki laki-laki sebagai biang keladi. Pun ketika ada orangtua ingin mengarahkan anaknya yang punya orientasi seksual berbeda agar kembali ke fitrahnya, maka oleh RUU ini termasuk ke dalam kekerasan seksual.
Komnas Perempuan dan berbagai organisasi feminis lainnya yang sangat memaksa DPR untuk segera mensahkan RUU P-KS mengingatkan kembali pada situasi sebelum Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi (Beijing Declaration and Platform for Action) disahkan pada tahun 1995.
Berbagai wakil Negara yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tanggal 4 sampai 15 September 1995 bertemu di Beijing dalam rangka Konferensi Dunia keempat tentang perempuan. Salah satu yang menjadi wakil dalam konferensi tersebut ialah Presiden organisasi Pro-Keluarga Family Watch International yang juga seorang ibu rumah tangga, Sharon Slater.
Sharon pada saat itu membantu delegasi PBB pro-keluarga untuk mendukung posisi mereka selama negosiasi yang berlangsung sangat panas. Tentu sangat panas karena ada bentrokan nilai, pandangan hidup maupun pemikiran yang terjadi antara pendukung pro-keluarga dan Antikeluarga.
Dalam buku saku yang ditulisnya, Stand for the Family: a Call to Responsible Citizens Everywhere, Sharon mengaku konferensi dunia tersebut adalah salah satu poin penting dalam hidupnya dan ia menjadi saksi hidup bagaimana Negara tercintanya, Amerika Serikat, menyetujui hasil konferensi tersebut yang memasukkan hak-hak seksual untuk kaum homoseksual dan lesbian.
Sebagian besar oposisi terhadap keluarga diprakarsai oleh feminis radikal dan kelompok pendukung lainnya yang hadir, mewakili organisasi non-pemerintah (LSM) dari berbagai negara.
Sharon menyebut feminis radikal ini sebagai kelompok wanita yang mendukung (feminisme) secara militan, (mengusung) ideologi anti-patriarki yang menindas semua pria dan wanita. Mereka juga bekerja untuk melegalkan aborsi dan mempromosikan hak-hak lesbian, transgender dan homoseksual.
Perwakilan LSM ini bekerja erat dengan mayoritas anggota negara-negara anggota PBB, tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang akan dinegosiasikan akan mempromosikan pandangan anti-keluarga yang mereka bawa. Tentu Sharon merasa terkejut dengan taktik mereka.
Semangat menihilkan agama yang dibawa dalam RUU P-KS telah dikampanyekan sejak lama oleh para feminis di Eropa dan Amerika. Bahkan, Feminis Elizabeth Cady Stanton menyebut jika Bibel dan Gereja merupakan batu sandungan terbesar pada emansipasi wanita. Maka tidak heran jika semangat ini mereka bawa kemana saja.
Kaum feminis radikal, ungkap Sharon, melihat agama — dan khususnya kelompok keagamaan (mereka pertimbangkan sebagai pelaku yang melanggengkan patriarki) — sebagai penghalang utama bagi “pemberdayaan” wanita.
Pada saat itu, Sharon mengaku tidak tahu bahwa “menghormati nilai-nilai agama dan budaya” adalah salah satu ungkapan paling kontroversial sewaktu negosiasi dalam konferensi dunia yang diadakan PBB ini.
Jelas saja, menurut Sharon, hal ini karena agenda feminis radikal yang sedang berjalan langsung bertentangan dengan semua agama-agama besar dunia. Jika negara-negara diharuskan menghormati nilai-nilai agama, maka (semestinya) para feminis tidak dapat memaksakan agenda mereka.
Pemaksaan agenda antikeluarga ini diperlihatkan secara terang-terangan oleh para feminis radikal saat ada wakil dari Vatikan tidak setuju dan membawa nilai-nilai agama dalam konferensi tersebut kemudian ditekan agar ia ikut menyetujui agenda antikeluarga yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tersebut, sebagaimana dikisahkan oleh Sharon,
“Dia berdiri melalui beberapa jam negosiasi yang melelahkan, dan dia tampak sangat lelah. Dia ditekan oleh semua wakil negara di dalam ruang untuk menyetujui ketentuan homoseksual. Dia telah dengan kuat mempertahankan posisinya hingga saat itu, tetapi karena negosiasi ini memerlukan konsensus, maka seluruh ruangan menekannya hingga ke dalam gua (merasa terpojok, red.).
Tekanan terhadapnya meningkat sampai, akhirnya, dia meninggalkan ruangan. Untuk menghubungi atasannya melalui ponselnya. Dia kemudian masuk kembali ke ruangan dan menghentikan proses. Dengan semua mata tertuju padanya, akhirnya dia mengumumkan bahwa “Vatikan menarik tentangannya terhadap ketentuan homoseksual”,. Saya tertegun. Saya bertanya-tanya bagaimana seorang perwakilan Vatikan bisa telah menyerah pada masalah yang begitu penting bagi iman Katolik.
Sulit dipercaya bagi saya bahwa tekanan teman sebaya dan intimidasi bisa memainkan peran penting dalam negosiasi PBB yang memengaruhi seluruh dunia.”
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Setelah RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender yang diusung pada tahun 2010 gagal, kini mereka membawa RUU baru dengan semangat yang tidak berbeda namun jauh lebih halus : keadilan untuk korban kekerasan seksual. Meski demikian, penguatan atau ketahanan keluarga pun tidak mereka jadikan sebagai solusi, mereka langgengkan zina dan pornografi atas nama hak asasi, bahkan nilai-nilai agama yang ada di Negara ini pun ingin mereka ganti. Mereka yang pro-keluarga dituduh melanggengkan patriarki dan menyetujui kekerasan seksual yang terjadi.
*Penulis merupakan Aktivis Yayasan Peduli Sahabat
Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Tabligh edisi Agustus 2020