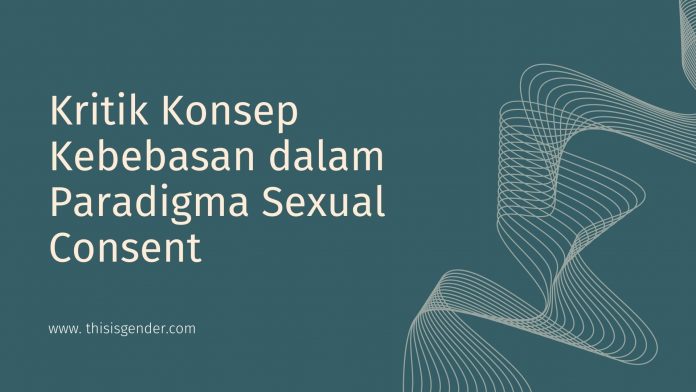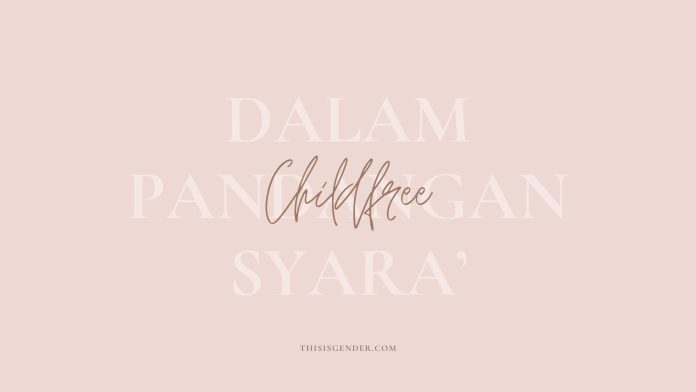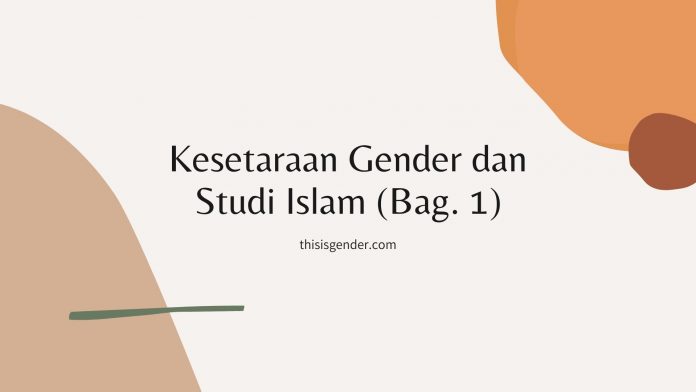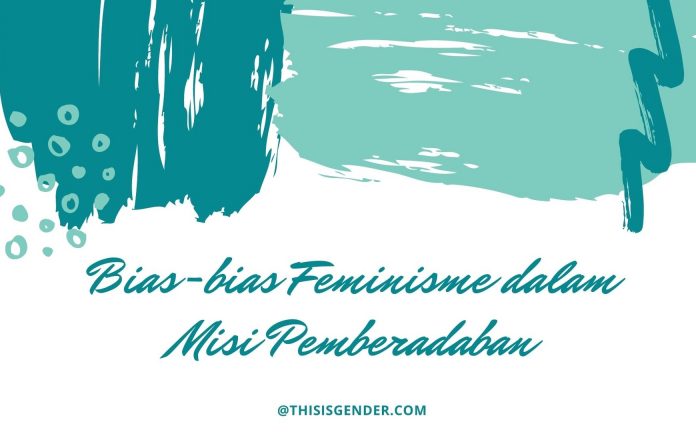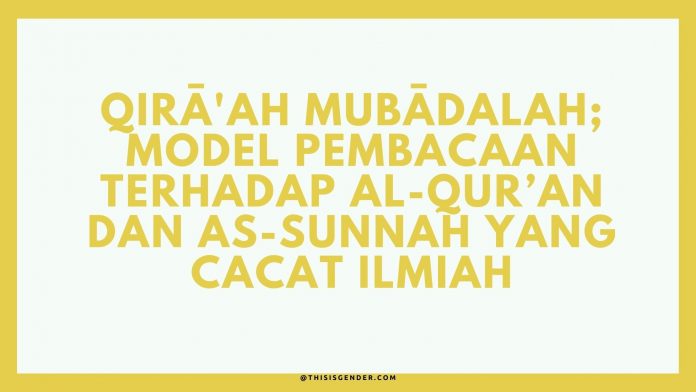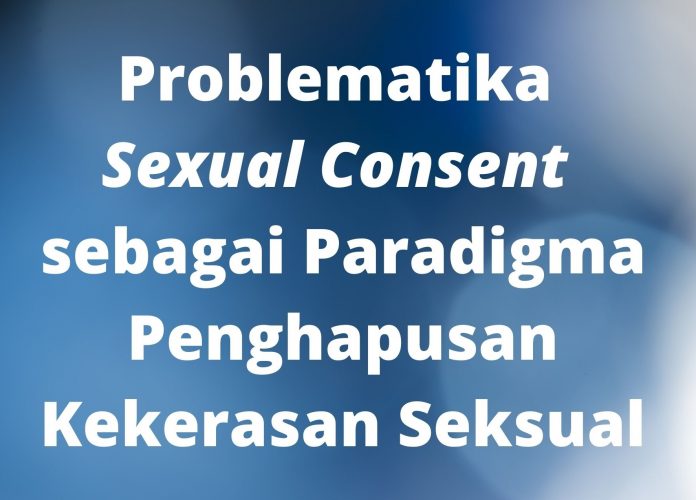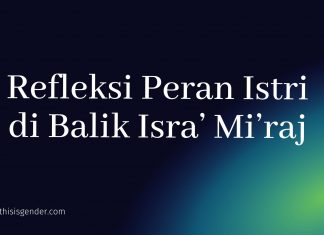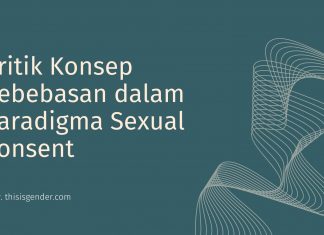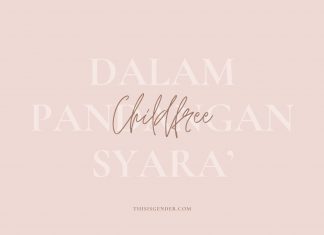Oleh: Cep Gilang Fikri S.Hum*
Qirā`ah Mubādalah dewasa ini sedang menjadi salah satu headline wacana para “feminis Muslim” Indonesia. Awal kemunculannya pada Februari 2019, ketika Faqihudin Abdul Kodir menerbitkan buku yang berjudul “Qira`ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.” Model pembacaan seperti ini oleh kaum feminis langsung ‘ditelan’ tanpa pengkajian kritis terlebih dahulu. Idealnya, sebuah model pembacaan atau metode baru itu perlu diuji kritis sebelum ‘ditelan’ sampai pada level akademik.
Di antaranya, di tingkat perguruan tinggi terdapat sebuah tesis master berjudul “Revitalisasi Pemahaman Hadits di Indonesia”. Tesis tersebut mengkaji hadits-hadits yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan menggunakan konsep mubadalah sebagai basis teorinya. Kesimpulan tesis tersebut mengasumsikan bahwa selama ini pembacaan hadits para ulama ahli hadis tentang relasi laki-laki dan perempuan masih tekstualis sehingga konon katanya melahirkan pemahaman yang menyudutkan perempuan.
Selain tesis, terdapat pula penelitian seorang dosen, yang ditulis dalam sebuah jurnal, menggunakan konsep ini sebagai landasan teorinya. Artikel jurnal tersebut berjudul “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, yang menghasilkan pandangan bahwa “konsep mubadalah merupakan salah satu konsep kesetaraan gender yang dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak di dalam kehidupan keluarga” [1].
Selain respon para akademisi, rupannya metode tersebut diterapkan juga ke berbagai ranah. Sepertinya ingin dipasarkan sebagai metode memahami sebuah hadis dan cara mendidik anak ala gender. Tentu saja respon dan praktik demikian termasuk ganjil.
Sebagaimana diketahui bahwa metode pembacaan nash-nash wahyu (al-Qur`an dan as-Sunnah) telah dikenal dan sudah digunakan secara mapan dalam dunia Islam berabad-abad lamanya. Berbagai diskursus keilmuan seperti Ushul Fiqh, Ulūm al-Qur`ān, Ulūm al-Hadīts dan lain-lain merupakan warisan ilmiah para Ulama yang secara esensi bersambung pada Nabi dan para sahabat dan diwariskan kepada tabi’in, hingga pada zaman setelahnya sampai sekarang.
Definisi Mubadalah
Buku berjudul “Qira`ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam” ini membahas dua permasalahan utama; yaitu mubadalah secara teoritis dan aplikatif. Secara teoritis, mubadalah dilihat dari segi konsep yang mendasarinya yaitu; konsep kesalingan yang kemudian dijadikan sebagai basis metode pembacaan nash. Sementara dari segi aplikatif, penulis buku menyebut kasus-kasus yang ada dalam relasi laki-laki dan perempuan, seperti isu eksistensi dan jati diri kemanusiaan, isu keluarga, pernikahan, dan isu-isu perempuan dalam kiprahnya di dunia publik. Kasus-kasus tersebut dibahas dengan menerapkan konsep dan metode mubadalah.
Dalam menjelaskan konsep, mula-mula penulis buku mendefinisikan terlebih dahulu istilah mubadalah. Mubadalah (مُبَادَلَةً) berakar kata “ba-da-la”, yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Ia merupakan bentuk kesalingan (mufā’alah) dan kerjasama antar dua pihak, yang saling mengganti, saling mengubah, atau timbal balik. Makna tersebut juga tidak jauh berbeda termaktub dalam kamus-kamus seperti lisān al-‘arab, al-mu’jam al-washīth. Padanannya dalam bahasa inggris yaitu reciprocity, reciprocation dan lain-lain. Sementara dalam bahasa Indonesia, penulis memilih diksi kesalingan untuk menunjukan padanan mubadalah. Dari penjelasannya tersebut, ia berusaha melihat mubadalah ini seakan-akan memiliki pijakannya dari turats para Ulama.
Hal itu terlihat ketika penulis mengambil makna kesalingan untuk diterapkan pada pola relasi laki-laki dan perempuan. Ia menyatakan bahwa pola relasi laki-laki dan perempuan mesti “mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal”. Dari konsep kesalingan tersebut, diupayakan agar pemahaman “teks Islam (bisa) mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama” [2]. Jika suatu ayat berbicara tentang laki-laki yang memiliki syahwat terhadap perempuan, maka dengan mubadalah ini berarti juga perempuan memiliki syahwat kepada laki-laki. Namun, penerapan teori mubadalah tersebut cenderung mengulang yang ada, dan bahkan menghindari rambu-rambu penafsiran, sebagaimana yang akan disampaikan di bawah. Artinya, mubadalah secara definitif dikembangkan dari makna etimologisnya menjadi sebuah pemahaman yang khusus dalam terminologi penulis buku, yaitu metodenya dalam menafsirakan nash-nash wahyu. Sebuah ‘loncatan liar’ yang sangat beresiko serius secara ilmiah.
Munculnya Mubadalah?
Mubadalah sebagai metode tafsir rupanya lahir dari adanya confuse (kebingungan) yang dirasakan oleh penulisnya. Pertama, penulis menilai bahwa tafsir keagamaan yang ada tidak objektif karena menggunakan cara pandang laki-laki sehingga hasil penafsiran lebih memihak kepada laki-laki dibanding perempuan [3]. Artinya, pengalaman; baik laki-laki maupun perempuan akan menentukan hasil penafsiran, dan dengan demikian cara pandang laki-laki dan perempuan tersebut, berdasarkan tulisan buku, perlu diakomodir dalam metode penafsiran nash-nash wahyu agar hasilnya berimbang/memperhatikan kedunya (laki-laki dan perempuan).
Kedua, latar belakang lainnya yang memunculkan mubadalah adalah perempuan selalu tidak diperhatikan dari hasil penafsiran karena kontruksi bahasa al-Qur`an banyak menggunakan bentuk tadzkīr/mudzakkar. Walaupun penulis mengakui terdapat sighat taghlib (yang disebutkan laki-laki namun maknanya mencakup laki-laki dan perempuan) namun ia tetap menyatakan bahwa makna dari ayat yang lahiriyahnya menggunakan dlamir mudzakkar selalu memposisikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan adalah objek atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali. Semestinya, “teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh bahwa perempuan juga menjadi subjek (Abdul Kodir:115).” Baik yang pertama dan yang kedua ini, sebetulnya sama yaitu beranggapan bahwa penafsiran yang ada ‘tidak ramah perempuan’.
Sementara itu, penulis menilai bahwa pesan-pesan al-Qur`an secara keseluruhan menunjukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pandangan seperti ‘tauhid merupakan basis kesetaraan laki-laki dan perempuan’, serta ayat-ayat yang memerintahkan untuk saling berbuat baik antara laki-laki dan perempuan menjadi landasan munculnya mubadalah (Walaupun lagi-lagi kasusnya sama seperti Amina Wadud, dengan gagasan hermenutika tauhidnya, mengharuskan adanya penafsiran al-Qur’an versi perempuan). Sehingga dari adanya permasalahan penafsiran yang dinilai lebih pro laki-laki lalu didorong dengan pesan-pesan agama yang mengarah pada kesetaraan laki-laki dan perempuan tersebut seakan menjadi angin segar untuk mengkampanyekan metode mubadalah.
Cara Kerja Metode Mubadalah
Sebelum penulis buku menjelaskan cara kerja mubadalah, ia menilai terlebih dahulu tafsir dan metodenya dengan kacamatanya sendiri. Penafsiran para ulama menurutnya adalah sebuah upaya mendekati (taqrīb) dan menduga (taghlib) maksud Allah dari ayat-ayat-Nya. Upaya penafsiran tersebut dilakukan dengan pengalaman Ulama sebagai hasil respon terhadap keadaan/konteks. penulis menyatakan, “karena (penafsiran) dikerjakan oleh manusia yang tidak terlepas dari dosa maka pastilah ia terkait dengan konteks di mana penafsir itu hidup dan bekerja. Kerja-kerja itu merupakan dinamika pertautan antara teks dan konteks dalam pengalaman Ulama masing-masing di setiap generasi” (Ibid:134). Atas hal itu, karena penafsiran hanya merupakan upaya mendekati dan dugaan maka penafsiran dinilai sebagai produk ulama belaka yang dipengaruhi oleh konteks di mana ia hidup dan hasilnya akan berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan ulama/penafsir.
Dengan demikian, qira’ah mudalah didahului oleh spekulasi yang kadarnya masih dzan (dugaan). Sayangnya, penulis buku itu tidak berhasil menjelaskan spekulasi dan dzan tersebut ke dalam tingkat pemahaman yaqin. Sebagaimana akan dijelaskan di sini, tetap saja metode ini diselimuti duga-dugaan, spekulasi, dan ‘fantasi-fantasi’ yang dibungkus dengan bahasa-bahasa ilmiah.
Secara metode, tafsir dinilai masih membuka cara kerja baru yang berbeda dengan metode sebelumnya. Dengan menamai metode yang telah ada sebagai metode ‘lama’, ia menilai metode tersebut tekstualis dan tidak memperhatikan kemaslahatan/tidak menghargai perempuan. Dengan mengutip pendapat Nasr Hamid Abu Zayd, seorang modernis mesir yang didakwa kafir oleh mahkamah karena karyanya, ia menulis bahwa “karakter utama dari peradaban Islam adalah orientasi pada teks” (h. 135). Semestinya, penafsiran mesti berorientasi konteks agar memperhatikan kemaslahatan. Bahkan ia mengatakan, “teks tidak dapat dikatakan hadir untuk menundukan realitas… keduanya perlu didialogkan untuk kemaslahatan” (h.144). Dengan kata lain, realitaslah (keinginan dan keadaan manusia) yang menjadi pegangan utama, bukan wahyu, dan dengan demikian wahyu mesti tunduk pada realitas. Dalam kaitannya dengan mubadalah, penulis menyebut bahwa metode inilah yang memperhatikan realitas perempuan sehingga tercipta penafsiran yang “berkesalingan” (Ibid). Dari sini terlihat, penilaian terhadap penafsiran dan metodenya adalah dalam rangka mencari tempat bagi diterimanya mubadalah sebagai metode tafsir baru.
Cara kerja metode tersebut jika dilihat bukan hanya memaknai cakupan ayat dengan pola kesalingan, melainkan menerapkan kesetaraan gender. Di antaranya dalam menafsirkan surah al-Nisa:11, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (bagian warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Sebagaimana cara kerja mubadalah, yaitu mula-mula mencari prinsip nilai al-Qur’an dan al-Hadits, menemukan gagasan utama dari teks, lalu menerapkan gagasan utama tersebut kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks (h. 200). Jika cara kerja tersebut digunakan dalam ayat ini, sesungguhnya ayat tersebut sudah mencakup laki-laki dan perempuan karena secara literal telah disebutkan. Namun, penafsiran diteruskan hingga sampai pada pandangan bahwa pembagian waris mesti disamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Ia menyatakan, “Ketika kenyataan sosial berubah maka penyesuaian bagian waris bisa dipertimbangkan….Ulama Indonesia telah mengenalkan konsep pembagian harta waris secara merata sebelum orang tua meninggal dunia” (h. 272-273). Dari sini terlihat bahwa penerapan mubadalah bukan hanya pada makna kesalingan, namun kesetaraan gender.
Kesetaraan gender tersebut semakin terlihat dalam penafsiran ayat yang lainnya. Dalam ayat poligami misalnya, pola pikir mubadalah menilai pernikahan poligami sebagai biang masalah. “Poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri, tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan,” dan bahkan merupakan bagian dari nusyuz (kemaksiatan) suami kepada istri”(h. 419, 422). Dari prinsip nilai dalam mubadalah, kesabaran dan kesetiaan merupakan sesuatu yang mesti dijaga dan hal itu tidak bisa terwujud kecuali dengan monogami (h. 421). Selain poligami, tafsir mubadalah juga memestikan adanya masa iddah bagi suami. Meski agak canggung, mubadalah dalam ayat ini bertujuan menerapkan iddah bagi suami. “Minimal secara moral keagamaan, untuk tidak melakukan pendekatan kepada perempuan lain dan tidak menikah sampai selesai 4 bulan 10 hari dari kematian sang istri” (hl. 428). Dalih-dalih seperti kesetiaan, keadilan, dan kemasalahatan itulah yang diterapkan dan tuntutan ayat/nash ditinggalkan, untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Konstruk Pandangan Hidup
Karakteristik mubadalah sebagaimana di atas tidak terlepas dari pandangan hidup penggagasnya, yaitu feminisme. Hal ini sebagaimana latar belakang kemunculannya yaitu menganggap penafsiran para ulama tidak ramah perempuan. Pandangan hidup feminis itu berarti segala hal dilandaskan kepada doktrin kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan harus disamakan dalam segala hal, termasuk dalam tafsir). Tidak aneh jika para Ulama yang mendasarkan penafsirannya kepada ilmu, bukan kepada kesetaraan gender, dinilai salah dan tidak ramah perempuan. Padahal, cara pandang kesetaraan gender tersebut problematis, mengingat karakter laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda sesuai dengan fitrah masing-masing, di samping terdapat kesamaan antara keduanya yaitu dalam derajat keduanya di hadapan Allah. Cara pandang tersebut mereka istilahkan dengan tafsir berbasis gender, bukan gender dilihat dari tafsir Islam.
Pandangan tersebut sebetulnya bukan hal yang baru. Ia telah ada sejak tahun 90-an ketika Amina Wadud, seorang feminis Amerika, menulis buku Qur’an and Women. Amina menyatakan “tidak ada metode penafsiran yang sepenuhnya objektif. Masing-masing penafsir membuat pilihan-pilihan yang subyektif.” Oleh karena itu, “para penafsir tradisional (bahasa Amina) telah dipengaruhi oleh pengalaman kelaki-lakiannya, seperti; cara pandang, tujuan, kecenderungan, dan kebutuhan mereka terhadap perempuan. Akhirnya, hasil penafsiran al-Qur’an tidak mengakomodir cara pandangan perempuan”[4]. Jika demikian halnya, mubadalah tafsir feminis merupakan pengulangan saja dari wacana-wacana sebelumnya.
Problematisnya cara pandang feminisme terhadap tafsir tersebut dapat dilihat dari dampaknya yaitu merelatifkan nilai. Seperti ulama dianggap menafsirkan menurut kacamata kelelakiannya, sehingga mesti ada tafsir berbasis cara pandang perempuan. Padahal, para ulama menafsirkan bukan dengan perspektif kelelakiannya, melainkan berpegang pada kaidah tafsir yang diajarkan Rasulullah S.A.W. dan para sahabatnya. Bahkan, salah satu syarat menafsirkan adalah memiliki akidah salīmah dan terlepas dari kepentingan politik, interes hawa nafsu. Artinya, para ulama menafsirkan berlandaskan nilai kebenaran, sebagaimana diajarkan Nabi.
Sebaliknya, tafsir berbasis pengalaman laki-laki/perempuan mendasarkan kebenaran pada kacamata penafsir saja. Pengalaman manusia akan berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Apa yang benar hari ini belum tentu benar kemudian. Seperti LGBT, yang kini dibenarkan oleh para penafsir Feminis. Jika demikian, permasalahannya bukan pada penafsiran ulama, mengingat para pewaris Nabi tersebut senantiasa terlepas dari kepentingan nafsu, melainkan permasalahannya adalah pada cara pandang feminisme yang problematis dalam menilai penafsiran para ulama.
Berkedok Maqashid Syari’ah
Mubadalah yang genealoginya adalah feminis berakibat pada liberalisasi metodologi tafsir. Cara kerjanya yang melihat prinsip atau nilai utama dari keseluruhan al-Qur’an, lalu menemukan gagasan utama dari ayat yang ingin ditafsirkan, dan menerapkannya kepada jenis kelamin yang tidak disebut oleh ayat, tidak memiliki acuan kaidah yang konsisten. Tidak aneh jika pembagian waris mesti disamaratakan, suami mesti memiliki masa iddah, poligami haram secara mutlak dan lain-lain. Itu semua karena cara kerja mubadalah dipayungi oleh doktrin kesetaraan gender dalam feminisme, sebagaimana telah dijelaskan. Cara kerja mubadalah ini, jika dalam bahasa sederhananya adalah meninggalkan tuntutan ayat dan menakwilkannya sesuai basis kesetaraan gender. Bahasa-bahasa kemaslahatan, dan keadilan sebagai tujuan dari mubadalah hanyalah sebagai pengecoh agar mubadalah bisa diterima, mengingat hasil penafsiran justru bertentangan dengan syari’at itu sendiri. Bukankah kemasalahatan dan keadilan datangnya dari agama dan syari’at Allah?. Lalu kemasalahatan dan keadilan seperti apa yang dimaksud jika agama dan syari’at Allah ditinggalakan.
Pola pikir tafsir berbasis kemasalahatan yang meninggalkan syari’at tersebut sesungguhnya adalah tren para pemikir modernis liberal. Terdapat sederet nama seperti Faraj Fawdah, Fazlurrahman, Nasr Hamid Abu Zayd, yang mendasarkan argumentasi penolakan syari’at dengan kedok kemaslahatan [5]. Bagi mereka yang penting adalah kemaslahatan, bukan konsistensi hukum dari al-Qur’an atau Hadits. Riba diharamkan untuk menjaga kepentingan golongan lemah. Hudud disyari’atkan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dari kriminal. Namun, lanjut mereka, kemaslahatan itu sendiri dapat berubah sesuai dengan peredaran waktu dan tempat. Apa yang dianggap maslahat hari ini belum tentu maslahat pada masa lalu dan pada waktu yang akan datang (Ibid).
Ini sama saja dengan narasi mubadalah tentang argumentasi tafsirnya. Seperti penentuan bagian waris 2:1 karena wanita pada waktu itu tidak mencari nafkah, dan karena sekarang perempuan telah banyak yang bekerja maka bagian waris mesti disetarakan (Mubadalah: 264). Poligami disyari’atkan karena syahwat orang Arab sangat besar, sehingga dikhawatirkan terjadi perzinahan jika tidak ada kebolehan poligami. Sementara ruang sosial Arab menurut mereka berbeda dengan yang lain, maka kebolehan poligami bisa berubah. Bahkan mereka menggeneralisir menjadi tidak boleh (Ibid: 418).
Yusuf Qardhawi menamakan golongan tersebut sebagai neo-Mu’attilah (orang yang mengabaikan nash al-Qur’an). Beliau menyatakan bahwa mereka telah menyalahgunakan prinsip maqashid syari’ah dengan menjadikannya sebagai dalih untuk lepas dari ikatan nash al-Qur’an (ta’thīl al-nushūsh bismi al-mashāliḥ wa al-maqāshid). Padahal Nash al-Qur’an tersebut terkategori valid secara transmisi dan maknanya (qat’iyyu al-wurūd wa qat’iyyu al-dilālah) [6]. Pantas saja jika Leonard Binder mengatakan, “for Islamic liberals the language of the qur`an is coordinate with the essence of revelation, but the content and meaning of revelation is not essentially verbal” [7]. Mestinya, kemaslahatan dilihat dari tuntunan ayat bukan tuntunan hawa nafsu, karena ayat tersebut merupakan firman Allah, dan tujuan diturunkan firman Allah adalah menciptakan kemasalahatan dunia dan akhirat.
Menggeser Kaidah Penafsiran
Dalam Mubadalah, laki-laki dan perempuan digeneralisir sama-sama menjadi subjek. Jika suatu ayat berbicara kepada laki-laki, maka perempuan dimasukan sebagai mitra tutur (mukhatab) dan posisinya disejajarkan dengan laki-laki. Begitu pun sebaliknya. Seperti masa iddah dimaknai kepada perempuan dan laki-laki, pembagian waris yang sama rata dan lain-lain. Prosedur seperti itu tidak memperhatikan konsep mukallaf sebagai yang diajak bicara oleh Allah. Artinya, khitab Allah ditujukan oleh-Nya kepada siapa yang dikehendaki, bukan disamaratakan menurut kehendak manusia. Seperti kewajiban shalat Jum’at kepada laki-laki saja, qawām bagi suami, tidak berlakunya shalat dan shaum bagi perempaun yang haidl, dan lain-lain. Memahami maksud ayat tersebut telah kokoh dalam kaidah-kaidah tafsir. Di dalamnya terdapat ulūm al-Qur’an, ulūm al-hadīts, ushūl fiqh, balaghah dan lain-lain. Artinya, jika kesalingan itu diterapkan begitu saja, maka ia telah berlawanan dengan kaidah-kaidah tafsir dan akan menghasilkan kekacauan penerapan syari’at.
Keluarnya mubadalah dari jalan lurus tersebut terlihat dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam mubadalah itu sendiri. Pertama, menilai penafsiran sebagai upaya yang relatif dan tidak akan menemukan kebenaran yang sebenarnya (Abdul Kodir:124). Kedua, dengan narasi dinamika teks dan realitas, penafsiran mesti mengacu kepada kondisi sosial masyarakat, dan meninggalkan nash (h. 135). Ketiga, ia memiliki pemahaman qat’iy-zhanniy sendiri. Ia memaknai hukum qat’iy tidak benar-benar permanen, melainkan masih menyisakan zhanniy (relatif) (h. 145). Keempat, memaknai prinsip nilai yang utama dalam prosedur penerapan mubadalah sebagai kesetaraan gender dalam perspektif feminis (h. 200). Artinya metode tafsir mubadalah dapat dikatakan berdasarkan tafsir bi al-ra`yi al-madzmūm.
Dalam menafsirkan al-Qur’an, muffassir memiliki kualifikasi tertentu, yang secara keseluruhan dijelaskan dalam literatur ‘Ulum al-Qur’an dan Ushul Fiqh. Untuk layak menafsirkan al-Qur’an, dijelaskan oleh Imam al-Suyuti dalam kitabnya Al-Taḥbīr fī ‘ilm al-Tafsīr, mesti menguasai bahasa arab dan literatur hadits secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dalam menafsirkan mesti sesuai dengan prosedurnya; yaitu menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, menafsirkan ayat dengan hadits, dan atau menafsirkan ayat dengan keterangan para mufassirin dari kalangan sahabat, tabi’in, dan para ulama salaf [8]. Sehingga, penafsiran tidak berdasarkan ra`yu semata, sebagaimana kecenderungan kesetaraan gender.
Penutup
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mubadalah adalah istilah baru yang esensinya tidak berbeda dengan istilah-istilah yang muncul dari para feminis. Mulai dari asumsi dasar kemunculannya yaitu mengggap tafsir para ulama bias gender. Ini sama seperti asuminya Amina Wadud yang melatarbelakangi tafsir versi perempuan (Qur`an and Women). Dari cara kerjanya, mubadalah beririsan dengan hermeneutika yang di dalamnya terdapat metode historisitas teks. Selain itu, konsep kesalingan dalam mubadalah tiada lain merupakan kesetaraan gender feminisme. Adanya kecenderungan menggunakan istilah baru ini adalah upaya pendekatan kepada publik atas ide-ide pembaruan yang sebenarnya tidak berbeda dengan ide-ide sebelumnya. Seperti dari Yogya, sempat dikeluarkan istilah maghza (bahasa arab: مغزى) yang esensinya adalah elan vital dalam hermeneutika. Contoh lain seperti istilah tauhidnya Amina Wadud yang isinya adalah pengalihan makna untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan lain-lain. Dengan kata lain, mubadalah dengan ide-ide feminis sebelumnya adalah hiya-hiya.
Dalam menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadits semestinya dilihat aspek aqidah, syari’at dan akhlak, sebagai bangunan Islam yang tidak bisa dipisahkan. Dalam aspek aqidah, interaksi dengan wahyu adalah dalam rangka menambah keimanan. Dari aspek syari’at, ketetapan ritual dan hukumnya mesti diikuti. Sementara dalam aspek akhlak, yaitu melihat nilai etika yang terdapat dalam ayat untuk diterapkan; seperti dalam ayat zuyyina linnās hubbusysyahawaāt mina al-nisā. Ayat tersebut sedang membicarakan perempuan sebagai yang dijadikan indah. Dalam tafsir Ibn Katsir, dapat dipahami bahwa wanita dengan ayat tersebut dididik agar menjadi al-mar`ah al-shālihah, agar tidak menjadi fitnah.
Dengan demikian, penekanan khusus kepada wanita dalam ayat di atas memiliki nilai akhlak yang mesti diamalkan oleh wanita, dan jika diterapkan makna kesalingan maka akan menghilangkan maksud penekanan makna tersebut. Cara pandang yang benar terhadap ayat mesti dikedepankan cara pandang yang menyeluruh, alias tidak sepotong-sepotong/parsial. Jika suatu ayat secara khusus berbicara mengenai perempuan, maka tidak bisa dipaksakan khitabnya diserikatkan dengan laki-laki. Karena khitab Allah kepada laki-laki berada dalam ayat atau hadits lain, dengan penekanan makna yang berbeda.
Daftar Pustaka
Abdul Kodir, Faqihuddin. 2019, Qirā`ah Mubādalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD.
al-Qardawi, Yusuf. 2008, Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī’ah, Kairo: Dar al-Syaruq.
Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. 1982, al-Taḥbīr fī ‘Ilm al-Tafsīr, Riyaḍ: Dār al-‘Ulūm.
Binder, Leonard. 1988, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies, Chicago & London: The University of Chicago Press.
Syafrin, Nirwan. vol. 1, no. 1. 2004, “Syari’at Islam: Antara Ketetapan Nas Dan Maqashid Syari’at”, Islamia. p. 89.
Wadud, Amina. 1999, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, New York: Oxford University Press.
Werdiningsih, Wilis. vol. 1, no. 1. 2020, “Ijougs”, Idougs. p. 1.
[1] Wilis Werdiningsih, “Ijougs”, Idougs, vol. 1, no. 1 (2020), p. 1.
[2] Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā`ah Mubādalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Dalam Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), pp. 59–60.
[3] Ibid., p. 104.
[4] Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 1–2.
[5] Nirwan Syafrin, “Syari’at Islam: Antara Ketetapan Nas Dan Maqashid Syari’at”, Islamia, vol. 1, no. 1 (2004), pp. 90–1.
[6] Yusuf al-Qardawi, Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī’ah (Kairo: Dar al-Syaruq, 2008), p. 83.
[7] Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1988), p. 4.
[8] Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, al-Taḥbīr fī ‘Ilm al-Tafsīr (Riyaḍ: Dār al-‘Ulūm, 1982), pp. 323–6.
*Penulis merupakan peneliti The Center for Gender Studies, saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor.