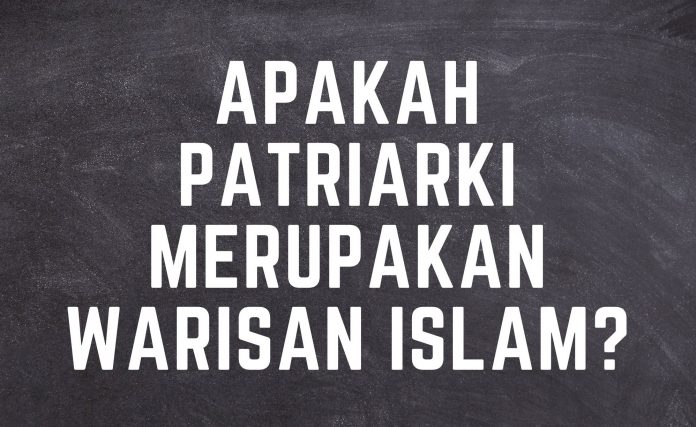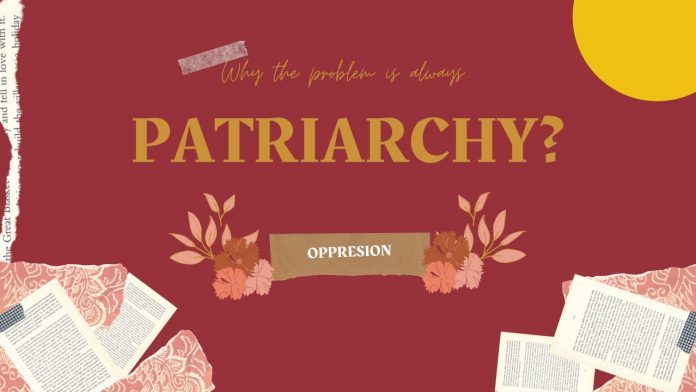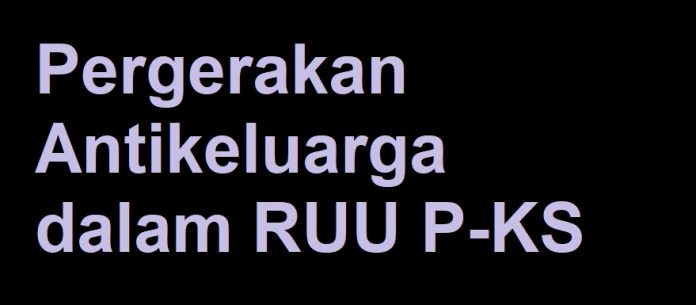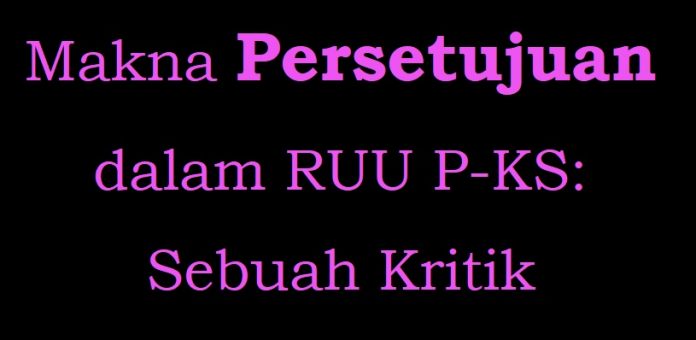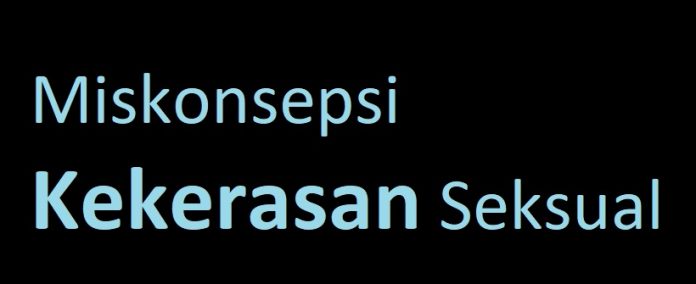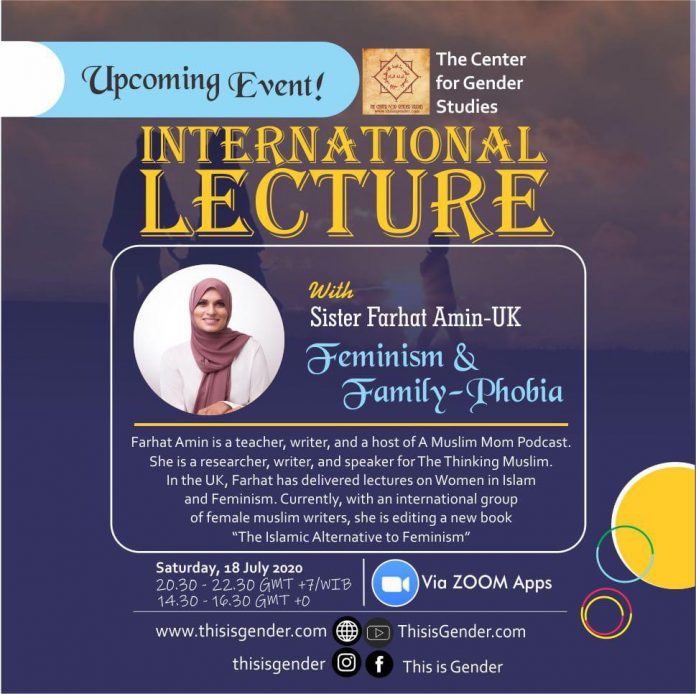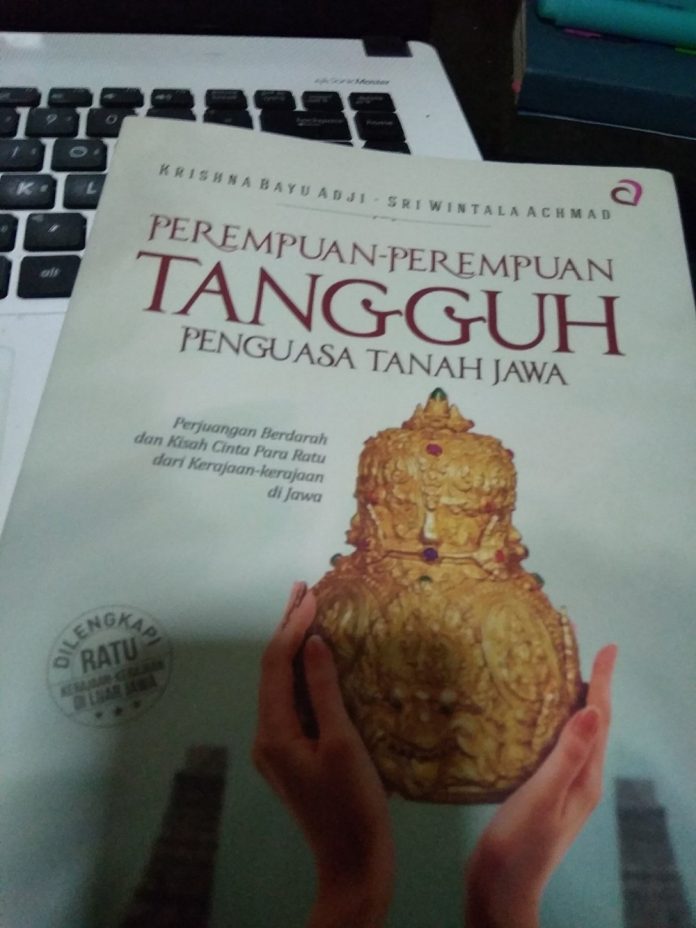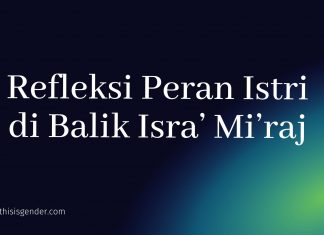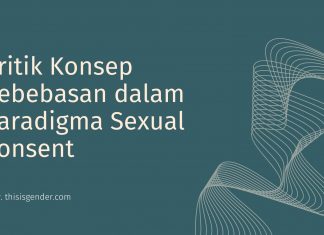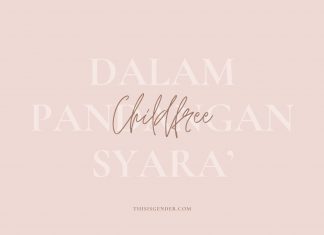Oleh: Putri Silaturrahmi, S.Sos., M.HSc.*
Patriarki merupakan kosakata yang disadur dari Bahasa Inggris yakni, Patriarchy. patriarki dapat diartikan laki-laki sebagai pemilik kuasa utama atau ia mendominasi segala peran dalam bermasyarakat. Elgenaidi (2019) mendefinisikan patriarki sebagai sistem sosial budaya dimana laki-laki dipandang secara kodratnya menjadi dominan atas perempuan. Kodrat ini melepaskan unsur kemampuannya dan ia masuk dalam posisi otoritas dan posisi kekuasaan kaum laki-laki. Sementara itu, perempuan dianggap sebagai anak-anak, ia perlu dilindungi atau dirawat, atau sebagai alat kekuasaan dalam melayani laki-laki, tidak pernah benar-benar utuh atau mandiri dari laki-laki, apalagi setara dengan mereka. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, patriarki itu sistem sosial yang problematik dan tidak adil.
Gagasan patriarki dalam sistem sosial di seluruh dunia memilki level eksistensi yang berbeda-beda. Patriarki eksis sejak zaman Yunani. Pada zaman itu konsep patriarki merupakan konsep bermasyarakat dimana kekuasaan dipegang dan diwariskan oleh kaum laki-laki dan dilegalkan oleh kaum gereja. Inilah awal dari tercetusnya konsep patriarki (Napikoski, 2019).
Sementara itu, patriarki pada zaman Romawi mendapatkan pertentangan dari kaum perempuan Romawi yang melakukan perlawanan. Mereka memprotes besar-besaran kebijakan Hukum Oppian, yang membatasi kepemilikan perempuan atas emas dan barang-barang lainnya. Bahkan saat itu konsul Romawi Marcus Porcius Cato melayangkan pendapat mengenai hukum tersebut bahwa “Begitu mereka mulai sederajat, mereka akan menjadi kaum yang superior!”(Olson, 2019). Menurut kaum feminis, eksistensi patriarki dibangun dalam agama. Ia ada melalui ayat-ayat suci, legitimasi negara dan ekstrimnya mereka berpendapat bahwa adalah kehendak Tuhan dalam membenarkan budaya patriarki ini. Ini sama saja kaum feminis menuding bahwa agama dan Tuhan turut menyumbang tumbuhnya sistem patriarki. Melihat konteks tersebut, tulisan ini berusaha membatasi spesifikasi penjelasan melalui kajian historis-filosofis bagaimana patriarki itu bisa terbentuk dalam sebuah sistem sosial.
Kaum feminis meyakini bahwa patriarki dipahami bukan hanya sebagai sistem sosial yang diwarisi oleh budaya klasik dari abad pertengahan melainkan juga diperkuat oleh perkembangan Renaissance. Tahun 1450-1500M merupakan awal baru di Eropa dengan ditandainya perluasan kapitalisme pra-industri dan reformasi Protestan. Feminisme lahir sebagai wujud protes kekecewaan kepada pihak gereja dan eksis mulai dari periode modern awal (Wiesner and Hanks, 2008).
Tiga puluh tahun lalu, patriarki digambarkan sebagai sesuatu yang “Maha” atau sebagai sistem kunci yang melatarbelakangi masyarakat dalam bersikap dan mengambil keputusan. Ia akan sangat mudah ditemui pada setiap hak istimewa yang diberikan kepada setiap laki-laki dikarenakan mereka merupakan kepala rumah tangga. Hak istimewa itu diberikan secara eksplisit dan implisit. Wujud dari pemberian hak istimewa ini lah yang menjadi cikal bakal lahirnya pergerakan kaum feminis pada masa awal Eropa Modern (Wiesner and Hanks 2018).
Dalam hal politik, kuasa turun temurun yang dimiliki laki-laki menjadikan mereka ahli dalam berpolitik baik secara teoretikal ataupun praktis. Peran mereka tumpang tindih serta mengikat satu dengan lainnya. Misalnya saja, raja dan pejabat kerajaaan tidak memiliki skat antara melaksanakan peran menjadi suami dan pemilik otoritas kerajaan yang penuh. Sistem sosial patriarki beranggapan bahwa Negara diibaratkan seperti rumah tangga. Perumpaan ini juga dinyatakan oleh Robert Filmer (1680) dalam karyanya Patriarcha ;
“Negara sama seperti halnya dalam sebuah rumah tangga yang suami atau bapaknya memiliki otoritas dan kekuasaan ilahi untuk semua angota keluarganya. Begitu pun pada sebuah negara, ia bagaikan seorang raja laki-laki yang harus selalu berkuasa. Saat itu anggota parlemen Inggris dan kaum revolusioner Prancis umumnya sepakat dengan kaum royalis bahwa kekuatan suami atas istri mereka adalah hal yang saleh dan ‘alami’, patriarki dianggap menciptakan apa yang dicap Christiane Faure ‘demokrasi tanpa perempuan’” (Gordon, 1975).
Kebanyakan gerakan feminis selalu menggunakan pendekatan ‘pembongkaran sistem patriarki’. Pendekatan ini merupakan misi umum kaum feminis untuk mempertahankan argumen mereka atas patriarki. Ternyata mereka juga sadar betul bahwa pendekatan ‘pembongkaran sistem patriarki’ ini merupakan medan yang rapuh. Seiring dengan perkembangan zaman, mereka menyusun gerakan baru yang menyentuh suatu definisi yang tepat yaitu “komunitas perempuan dan laki-laki”. Singkat kata mereka memperjuangkan perempuan sebagai mitra sejajar bagi kaum laki-laki. Akan tetapi, mitra sejajar ini tidak dapat menjadi tempat konflik yang dapat dihindari dikarenakan perbedaan kodrat. Faktor ini lah yang melahirkan sebuah ketidaksetaraan (Neuenfeldt, 2015).
Feminis juga sangat kental mengkritik bagaimana posisi perempuan dalam praktek Gereja. Mereka berpendapat bahwa struktur keagamaan dalam Gereja itu sangat hierarkis. Dalam tatanan hierarki yang sakral pada Gereja, laki-laki memiliki kuasa atas semua hal dan juga manusia. Skema hierarkis ini membutuhkan Tuhan yang memiliki kekuasaan atas segalanya dalam menentukan, membatasi, dan memaksakan keinginan, peraturan, dan perintah “-Nya”. Dalam tatanan masyarakat abad pertengahan hubungan laki-laki dan perempuan erat kaitannya dengan menghukum dan menyelamatkan. Laki-laki dianggap dapat menyelamatkan citra perempuan sebagai ‘Hawa’ sang penggoda menuju ‘Marry’ yang taat dengan berbakti kepada suaminya. Sementara terdapat hukuman apabila perempuan tidak mampu mengangkat martabat laki-laki. Hal ini digambarkan dalam konsep Saint Paul’s bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk penuh dosa karena ia mampu menggoda Adam sehingga turun ke Bumi. Selain itu istri harus menyerahkan diri kepada suaminya sendiri sebagaimana ia mengorbankan kehidupannya untuk Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sebagaimana Kristus adalah kepala gereja sehingga istri harus mematuhi dan menuruti suaminya. Keduanya (Kristus dan suami –red) menghukum dan menyelamatkan. Dari narasi ini dapat disimpulkan bahwa kritik mereka terhadap patriarki merupakan wujud kekecewaan kaum perempuan terhadap Gereja.
Dalam kajian teologi Feminisme, wacana iman dan agama juga memainkan peran utama dalam diskusi kesetaraan gender dengan bekerja sama secara positif menuju redefinisi peran dan struktur. Peran mereka sangat penting dikarenakan redefinisi menuntut perempuan sebagai mitra sejajar bagi laki-laki. Pada telaah kajian modern, feminis Gereja mengambil posisi penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan etika perlawanan terhadap ketidakadilan. Hal ini merupakan salah satu contoh peran aktif dan wewenang mereka.
Selain itu peran Gereja untuk kaum feminis modern ini sangat membantu mulai dari refleksi teologis yang digunakan untuk melakukan pendekatan kritis terhadap iman dan agama, hal ini dapat membantu membongkar hubungan yang berbahaya antara agama dan budaya sebagai penyebab perempuan terasing di ruang privat, ruang dimana kekerasan paling sering terjadi. Mengapa saat itu perempuan terasing pada ruang privatnya? karena keadaan perempuan di Abad Medieval diharuskan untuk mampu melayani suami. Hal ini dapat terlihat ketika suami gagal dalam melindungi istrinya dari marabahaya. Kencenderungan pertama dari kolektif sosial akan mempertanyakan sejauh mana sang istri patuh terhadap suaminya. Peran suami dalam kemampuan melindungi istrinya berbanding lurus dengan kemampuan istri dalam melayani suaminya. Sikap seperti ini terbukti dalam dokumen pengadilan Henry Cook dan istrinya (yang tidak ingin disebutkan namanya). Istrinya menyatakan bahwa suaminya memiliki pikiran jahat terhadapnya dan terlibat dalam hubungan zina dengan banyak perempuan. Ironinya, pengadilan memutuskan bahwa sang istri harus tetap bersama suaminya, rendah hati, tidak menghina suaminya, dan tidak bersikap kejam terhadap suaminya karena sang istri telah mengabaikan tugas domestiknya dan meninggalkannya (Halsall, 1996).
Organisasi Gereja pada masa modern mendukung penuh partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dengan menyangkal sikap yang melanggengkan ketidaksetaraan. Mereka merangkul perempuan untuk merumuskan resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian. Sementara itu kaum Gereja tetap gemar mengkampanyekan kesetaraan gender melalui kosakata teologis ‘Justice’ (Keadilan):
“Keadilan gender menyiratkan perlindungan dan promosi martabat perempuan dan laki-laki yang, diciptakan menurut gambar Allah, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling bertanggung jawab, laki-laki dan perempuan mampu menjadi mitra sejajar. Keadilan gender diungkapkan melalui kesetaraan dan hubungan kekuasaan yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dan penghapusan sistem kelembagaan dan budaya antar pribadi dan penindasan yang menopang diskriminasi” (Neuenfeldt, 2013 p.7).
Pada saat ini, kaum feminis mencoba mengkonsep keadilan gender dan menyamakan persepsi mereka dengan kaum Gereja. Mereka menggarisbawahi bahwa perlu ada kajian mendalam mengenai hubungan kuasa dan kekuasaan dalam sudut pandang teologis dan alkitabiah. Dalam upaya menyentuh ranah teologis mereka berharap penyalahgunaan kekuasaan yang dimanifestasikan melalui struktur hierarki dan androsentris gereja akan berganti menjadi istilah inklusif ‘mitra sejajar’. Selain itu mereka juga menginginkan hubungan yang lebih adil dan merata bagi kaum perempuan dan laki-laki. Saat ini gerak feminis menyadari bahwa proses, srategi dan kebijakan itu sangat penting dalam hal usaha mereka untuk meredefinisi makna gender.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa feminisme ini lahir dikarenakan kuasa patriarki yang sangat mendominasi. Ia merupakan produk dari sistem sosial budaya Eropa saat itu yang ingin melepaskan diri dari ikatan doktrin agama serta perempuan yang dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Mereka dianggap kaum rendah dan tidak dapat diandalkan. Menempatkan posisi perempuan sebagai peran sekunder. Konsepsi yang merendahkan derajat kaum perempuan menimbulkan sikap protes yang diskriminatif dan tidak adil bagi perempuan sehingga feminisme lahir menjadi sebuah gerakan. Ia menjadi teori sosial yang lahir dari realitas sosio-kultural masyarakat Barat. Pada masa sekarang kaum Feminis berafiliasi dengan kaum gereja untuk merumuskan kembali makna ‘Justice’ atau keadilan bagi kaum perempuan. Dari perumusan teologis ini lahir lah kesetaraan gender.
Pandangan Islam tentang Relasi Perempuan dan Laki-Laki
Islam lahir sebagai sistem kehidupan yang sempurna. Secara kekeluargaan, kondisi sosial-politik, hak ekonomi bagi perempuan, dan relasi gender di dalam Islam tidak dapat sepenuhnya dipahami dan dihargai kecuali Islam dilihat sebagai sebuah sistem yang lengkap dan sempurna bagi kaum laki-laki dan perempuan (Al-Mawdudi, 1992). Islam yang bermakna penyerahan diri kepada Allah Swt, mengamanatkan kepada seluruh ummat dimana di dalamnya termasuk perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak. Islam sebagai sistem menyajikan aspek kehidupan universal sepanjang masa. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya “Islam laki-laki” atau “Islam perempuan”. Penyerahdirian kepada Allah Swt. yang sempurna justru akan menjawab berbagai permasalahan dalam pandangan manusia termasuk permasalahan diskriminasi laki-laki dan perempuan.
Islam adalah sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, ia terintegrasi secara holistik berlandaskan ilmu Tauhid, Ke-Esaan Allah Swt, dan kesatuan dalam mencapai tujuan dalam penciptaan. Pesan Tauhid dalam Islam “tidak ada Tuhan selain Allah Swt” merupakan amanah bagi seluruh makhluk hidup yang tunduk dan patuh terhadap Allah Swt sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai wahyu dari-Nya dan As-Sunnah pengajaran dan praktek dari Rasullulah Saw. Pesan Tauhid ini adalah berkah untuk setiap insan di muka bumi baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Berdasarkan pesan tauhid tentang Ke-Esaan Allah Swt dan misi universal kekhalifahan Allah Swt di bumi, Islam menyajikan rancangan yang komprehensif untuk mengembangkan potensi manusia. Rancangan program pengembangannya tidak didasarkan pada keterpusatan laki-laki (berkonsentrasi pada pengembangan laki-laki saja dengan tidak mengacuhkan aspek keterbelakangan perempuan), ataupun sebaliknya yaitu tidak pada keterpusatan perempuan (hanya memfokuskan pengembangan perempuan dengan tidak mengacuhkan keterbelakangan laki-laki). Singkatnya Islam tidak lahir atas kuasa patriarki sehingga kaum perempuan menjadi masyarakat kelas dua.
Allah Swt adalah Pembuat Sistem terbaik dan Pemiliki Pengetahuan Absolut mengenai pengembangan semua makhluk hidup. Dia Subhanahu wa Ta’ala telah mempresentasikan rancangan pembangunan terpadu yang diperuntukkan bagi setiap laki-laki dan perempuan. Islam tidak memandang laki-laki dan perempuan secara bertentangan, oleh demikian sudah tentu Islam juga tidak pernah mengajarkan kaum laki-laki dan perempuan untuk saling membakar kebencian dan berjuang untuk memberdayakan satu sama lain, sementara yang lainnya terlalu unggul dan terlalu terbelakang. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam pengembangan keluarga dan masyarakat.
Islam tidak mengajarkan untuk meniupkan isu-isu antipati baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kekuasaan Islam hanya milik Allah Swt sementara laki-laki dan perempuan hanya lah agen Allah di bumi, menjadi wakil khalifah-Nya, seluruh makhluk hidup tidak perlu mengklaim kekuasaan dan otoritas untuk pemuliaan dan peningkatan diri mereka sendiri. Kinerja kita sebagai hamba-Nya ialah untuk menjadi khalifah Allah Swt. Hal ini sendiri menyiratkan bahwa kita sedang menjalankan otoritas penuh sebagaimana yang diamanatkan Allah Swt, demikian juga halnya dalam menjalin hubungan laki-laki dan perempuan pada semua bidang kehidupan. Dengan cara ini laki-laki dan perempuan hanya memiliki kekuasaan dan otoritas yang didelegasikan, yang ditugaskan kepada mereka oleh Allah Swt.
Istilah feminisme sebagai bentuk gerakan perlawanan terhadap kaum laki-laki, hadir sebagai mimbar atas kekecewaan kaum perempuan karena direndahkannya harkat, martabat, dan derajat perempuan. Dimana hal ini sangat kontradiktif dengan filosofi ke-Islaman mengenai kuasa dan otoritas. Konsep mengenai hak, kuasa dan otoritas ini perlu dikembalikan kepada pandangan Islam (Islamic Worldview). Ada dua hal yang harus dedifinisikan kembali dari sudut pandang ke-Islaman. Pertama, sebagaimana telah didiskusikan di atas bahwa dalam Islam semua kuasa dan otoritas hanya milik Allah Swt. Hal ini dikarenakan Allah Swt adalah Sang Pencipta, Maha Pemelihara, Penopang, dan Allah Swt adalah Tuan yang menetapkan hukum bagi seluruh ciptaan-Nya. Manusia diperintahkan untuk membangun sistem yang diwahyukan kepadanya dan amanah ketika menjadi khalifah di muka bumi ini. Dikarenakan kapasitasnya sebagai pemimpin di dunia ini diharapkan ia dapat membuat ijtihad yang berlandaskan kepada sumber ilmu dan hukum Islam. Kadar otoritas yang diberikan Allah pada manusia tidak boleh menjadikan manusia berlaku sewenang-wenang terhadap manusia lainnya. Dalam merancang sebuah peradaban yang sehat dan mengacu kepada Firman-Nya, setiap insan baik laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang besar menjadi Khalifah yang mampu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Kedua, Islam mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menikmati haknya yang diberikan oleh Allah Swt. Mengacu kepada Islam, bahwa setiap insan tidak memiliki kuasa untuk diberikan atau untuk mengambil hak dari insan lainnya. Ini merupakan karunia yang Allah Swt berikan dan ini merupakan tugas yang sesuai kepada seluruh ummat. Tidak satupun dari penciptaannya yang boleh mencabut hak-hak yang dapat dinikmati oleh insan lainnya karena hak-hak itu pada hakikatnya adalah dari Allah Swt. Ini dapat dicontohkan untuk perempuan dan laki-laki bahwa mereka tidak boleh melampui batas, sehingga dua jenis kelamin ini tidak bertengkar untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sebetulnya sudah diatur oleh Allah Swt. Perempuan tidak boleh mengemis untuk mendapatkan hak nya; karena sejatinya mereka juga memiliki hak sebagai khalifah di muka bumi ini.
Berbicara mengenai hak maka akan selalu terkait dengan hakekat Islam dalam memandang ilmu. Ilmu dinilai sebagai sarana yang penting untuk mengenal dan mengetahui Al-Haqq. Hak yang berasal dari kata haqq dalam pandangan Islam merupakan hakekat sekaligus kebenaran dalam dua wilayah penilaian atau hukum. Ia menunjuk kepada sebuah realitas yang mengacu kepada tatanan eksistensi ontologis dan logis (Al-Attas, 1995). Hak bukan saja suatu sifat dasar dan juga posisi alamiah (fitrah), ia juga berarti ‘tugas’ atau ‘kewajiban’ yang mengikat sesuai dengan realitas yang dikenali itu (Al-Attas, 1984). Dalam kaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat kecenderungan alami yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, karena itu kedua belah pihak dituntut untuk saling mengenali dan memenuhi tuntutan fitrah masing-masing. Jika dua jenis kelamin ini dapat memahami hak dan berusaha memenuhinya maka dengan sendirinya keadilan itu akan tercapai. Sebab dengan memenuhi tuntutan haqq ini, berarti juga seseorang telah melakukan kebenaran.
Akan tetapi, hegemoni kolonialisme barat membuat masyarakat Islam hampir berpaling dari konsep Islam terhadap ilmu yang Tauhidi. Barat telah mampu membuat ummat cenderung lebih memilih untuk mengadopsi konsep ilmu pengetahuan yang sekuler yang dianggap lebih maju, open minded, dan ‘dewasa’. Hegemoni Barat ini terus menerus berlangsung hingga berdampak kepada kepada pendangkalan pemahaman masyarakat Islam terhadap hakekat ilmu. Ummat tidak lagi mampu membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Pada akhirnya ummat perlahan akan kehilangan identitas Ke-Islam-annya. Seperti yang sekarang ini terjadi menggabungkan paham-paham isme dengan Islam. Termasuk juga di dalamnya paham Feminimse. Kemudian berusaha menggabungan feminisme dengan Islam. Padahal isme-isme ini sangat kontradiktif dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.
Cara Ummat dalam meraih ilmu juga akan berdampak pada pendidikan yang akan diraihnya. Hakekat pendidikan yang merdeka adalah manusia yang beradab, Insan Kamil yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt sebagai Sang Pencipta. Manusia beradab ini dicirikan dengan kehidupannya yang seimbang baik dari dimensi kepribadiannya dan juga dimensi yang membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosialnya. Manusia seimbang akan menghasilkan masyarakat seimbang yang tidak dapat memilah milih jenis kelamin mana yang lebih baik. Masyarakat seimbang ini akan terdapat pada jiwa-jiwa manusia yang memiliki kualitas dalam berpikir, zikir dan amalnya. Jika ibadahnya baik maka kehidupan sosialnya juga akan baik.
Dengan kata lain, ada hal-hal yang menjadi landasan penting dalam ber-Islam bahwa agama ini merupakan sistem kehidupan terbaik bagi laki-laki dan perempuan. Berbicara mengenai gender pada sudut pandang ke-Islaman tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja melainkan dari sebuah sistem yang penuh. Tujuan hidup dalam ber-Islam yaitu menjadi khalifah adalah sebuah amanah untuk laki-laki dan perempuan dalam meregulasi seluruh aktivitasnya mengacu kepada cara hidup yang Islami untuk memenuhi amanah tersebut. Terakhir, Allah Swt telah menempatkan setiap hak-hak penciptaannya yang sifatnya adalah mutlak. Sehingga hamba-Nya mampu menikmati setiap karunia yang Allah Swt berikan. Ketika insan satu dengan yang lainnya mampu menjalankan perannya masing-masing, keadilan dapat tewujud.
Singkat kata Islam tidak memisahkan laki-laki dan perempuan secara dikotomis. Keberadaan mereka tidak bisa dialamatkan sebagai permasalahan sosial, tidak juga sebagai sebuah konflik gender. Islam juga tidak menghendaki konflik antara keduanya dalam hal memperjuangkan hak-hak nya karena kuasa sepenuhnya hanya milik Allah Swt. Meskipun Islam menyajikan prinsip-prinsip khusus bagi setiap peran manusia, pada dasarnya sifat prinsip tersebut adalah wajib karena prinsip tersebut yang mengatur setiap manusia untuk menjadi utuh. Mengacu kepada landasan filosofi ke-Islaman di atas dapat disimpulkan bahwa patriarki bukan warisan Islam dan kesetaraan gender merupakan sebuah distopia.
Jakarta, 28 September 2019
*Penulis merupakan Alumni KOFI (Kuliah Online Feminisme & Islam) dan anggota komunitas Calami Veritatis—The Center for Gender Studies.
Ed: Sakinah/CGS
BAHAN BACAAN:
Elgenaidi, Maha (2019). The Case Against Patriarchy in Islam: Fitra, Vicegerency, and Universal Principal Akses pada laman https://ing.org/case-patriarchy-islam/
Gordon Schochet, Patriarchalism in Political Thought: The Authoritarian Family and Political Speculation and Attitudes especially in Seventeenth Century England (New York: Basic Books, 1975).
Gender Justice Policy, ed. Elaine Neuenfeldt (Lutheran World Federation, 2013), 7, at https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf
Halsall, 1996. Gratian: On Marriage (dictum post C.32.2.2),” in Medieval Sourcebook, edited by Paul Halsall, Jan 1996. http://www.fordham.edu/Halsall/source/gratian1.asp.
Neuenfeldt, Elaine (2015). Identifying and Dismantling Patriarchy and Other Systems of Oppression of Women Gender Analysis, Feminist Theology, and the Church in Mission. International Review of Mission: World Council of Churches pp 18-25.
Napikoski, Linda (2019). Patriarchal Society According to Feminism; Feminist Theories of Patriarchy akses pada laman https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978
Olson, John (2019). Feminism. Akses laman https://www.history.com/topics/womens-history/feminism-womens-history
Syed Abdul Ala Mawdudi (1992). Islamic Was of Life. Lahore: Islamic Publications.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Islam dan Filsafat Sains. Bandung: Mizan (1995).
Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Konsep Pendidikan dalam Islam. Bandung: Mizan (1984).
Merry E. WiesnerHanks, ‘Do Women Need the Renaissance?’, Gender & History 20 (2008), pp. 539–57; and Martha Howell,‘The Gender of Europe’s Commercial Economy, 1200–1700’, Gender & History 20 (2008), pp. 519–38.
Wiesner, Merry and Hanks (2018). Forum Introduction: Reconsidering Patriarchy in Early Modern Europe and the Middle East. Gender and History, Vol 30 No 2 July 2018, pp 320-330.