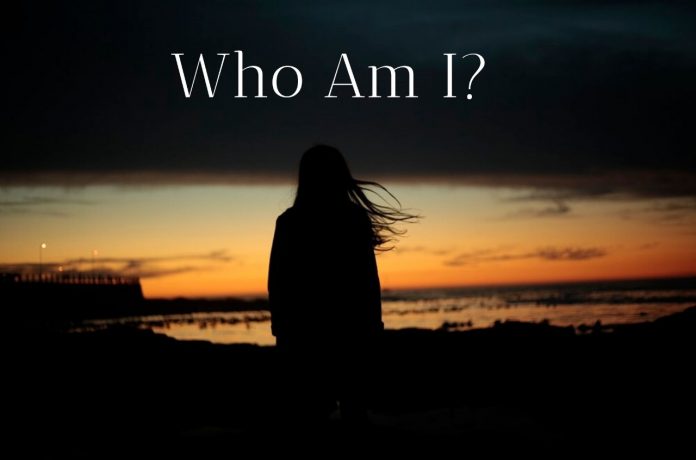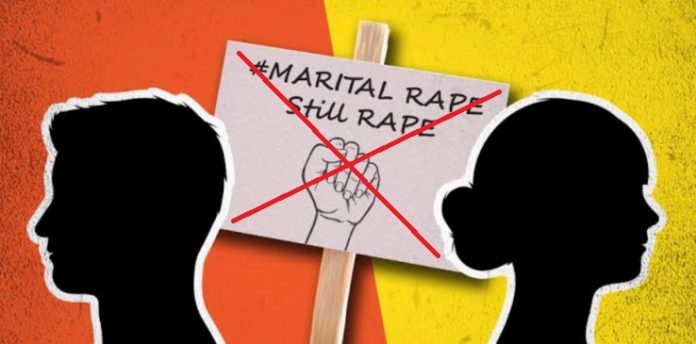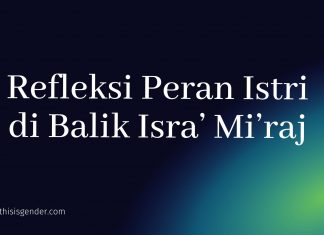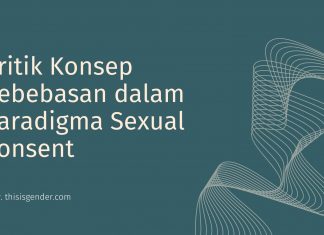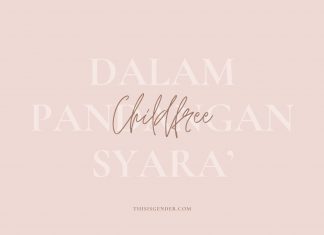Oleh: Dr. Dinar Dewi Kania[1]
Perempuan muslim di zaman ini tanpa sadar telah terjebak dalam krisis yang sama dengan perempuan Barat, menyangka bahwa paham kebebasanlah yang dapat membahagiakan perempuan. Padahal problem utama perempuan muslim saat ini adalah krisis ilmu. Syeikh Hamza Yusuf ketika berbicara pada konferensi Reviving Islamic Spirit di Malaysia pada tahun 2017 lalu, berulang-ulang mengafirmasi pendapat Prof S.M. Naquib al-Attas, bahwa krisis ilmu di dunia muslim yang pertama kali harus diselesaikan agar peradaban Islam kembali bersinar. Krisis ilmu terkait erat dengan krisis adab dan krisis kepemimpinan. Apabila perempuan muslim tidak merespon terhadap akar permasalahan tersebut dan hanya bersifat reaktif terhadap isu-isu yang kurang fundamental, maka krisis di dunia Islam tidak akan pernah berakhir.
Kaum perempuan muslim (muslimah) yang mengalami krisis ilmu akhirnya berpaling dari Islam dan mengadopsi cara pandang Feminisme dalam menilai problematika perempuan. Padahal hanya peradaban Islam, yang sejak dari kemunculannya, telah menghasilkan para intelektual dari kaum perempuan. Para intelektual muslimah memiliki kemampuan penalaran yang tinggi namun tetap menjaga fitrahnya sebagai perempuan. Mereka tidak pernah merasa inferior dilahirkan sebagai perempuan, tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh kaum lelaki, tidak pernah menganggap rendah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang dilakukan para aktivis feminis saat ini. Akram Nadwi dalam bukunya al-Muhaddithāt : the Woman Scholars in Islam,[2] mengatakan :
“I have worked through much material over decade to compile biographical accounts of 8.000 muhaddithāt. Not one of them is reported to have a considered the domain of family life inferior, or neglected duties therein, or considered being a woman undesirable inferior to being , a man, or considered that, given aptitude and opportunity, she had no duties to the wider society, outside the domain of family.”
Lebih lanjut ia mengatakan tentang para intelektual muslimah :
“I do owe to the women whose scholarly authority this book celebrates to say briefly what is necessary to distinguish their perspective. They were not feminists, neither consciously nor unconsciously. They were above all else, like the men scholars, believers, and they got and exercised the same authority by virtue of reasoning with the same methods from the same source as the men, and by having at the same time, just as the men did, a reputation for taqwā (wariness of God), righteousness and strong intellect.”[3]
Para intelektual muslimah bukanlah seorang feminis secara sadar maupun tidak sadar. Mereka di atas semua itu, karena mereka adalah orang-orang beriman sebagaimana kaum intelektual dari kalangan muslim. Mereka memiliki dan dilatih dengan penalaran menggunakan metode dan sumber yang sama dengan laki-laki. Mereka memiliki reputasi sebagai perempuan yang bertakwa dan memiliki intelek yang kuat. Hal tersebut dapat terjadi karena kedudukan ilmu dalam peradaban Islam sangatlah tinggi, bahkan periode munculnya struktur ilmu pada pandangan alam Islam (Islamic worldview) dimulai pertama-tama dengan penekanan pada konsep ilmu sebagai elemen yang fundamental.[4] Dalam pandangan alam Islam, ilmu selalu berkaitan dengan amal saleh. Orang yang berilmu haruslah orang yang juga mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan beribadah hanya kepada Allah SWT. Selain memiliki keterkaitan dengan amal, konsep ilmu dalam Islam selalu mengandung dimensi moralitas dan adab.[5] Hal inilah yang tidak disadari oleh para feminis yang menuduh agama Islam sebagai penyebab keterbelakangan dan penindasan terhadap perempuan.
Bagaimanakah tradisi keilmuan Islam yang tinggi dapat mengalami kemerosotan yang demikian hebat? Krisis ilmu yang menimpa umat muslim secara umum disebabkan oleh dua faktor; 1) faktor internal, yang berasal dari dalam diri seseorang, 2) faktor eksternal, bersumber dari lingkungan fisik dan sosial. Permasalahan atau krisis keilmuan di dunia perempuan, akan dibahas berdasarkan kedua faktor tersebut.
- Faktor Internal
Problematika keilmuan yang disebabkan oleh faktor internal, terkait dengan kondisi diri muslimah sebagai individu muslim. Krisis ini disebabkan karena kurangnya kontemplasi dan tradisi berpikir secara mendalam. Nilai-nilai ateistik di abad ke 20 menurut Jenkins[6] telah membentuk manusia-manusia bervisi mekanistis yang tidak memiliki makna atau tujuan hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita jumpai banyak perempuan yang menjalani kehidupannya seperti robot, tanpa pernah terbersit untuk berpikir tentang visi yang benar dalam kehidupan, siapa kita, mengapa kita hidup di dunia, hendak kemana kita setelah kematian, dan pertanyaan eksistensial lainnya. Ataupun jika ada yang telah memikirkannya, namun tidak sampai kepada jawaban-jawaban yang benar karena terpengaruh kepada cara pandang materialistik (materialistic worldview).
Manusia dikatakan sebagai “a language animal” karena kemampuan mengartikulasikan simbol-simbol linguistik menjadi bentuk yang bermakna yang merupakan daya dari realitas yang tidak terlihat, yaitu ‘aql.[7] ‘Aql menurut al-Attas adalah substansi kognisi spiritual yang sinonim dengan qalb, yang letaknya ada dalam hati (heart). Sifat dasar dari ‘aql adalah substansi spiritual di mana jiwa yang rasional (al-nafs al-naatiqah) mengenali dan membedakan kebenaran (truth) dari kepalsuan (falsehood). Oleh karena itu, al-Attas menyimpulkan bahwa realitas seorang manusia pada hakikatnya adalah makhluk spiritual, dan bukan semata-mata fisik atau aspek-aspek kehewaniannya saja (animal aspect). Kemampuan rasio pada manusia membuat ia mampu memahami kata-kata dan memformulasikan makna dalam rangka memperoleh ilmu.[8] Menurut Hamza Yusuf, disinilah pentingnya penguasaan terhadap ilmu-ilmu trivium, yaitu logika, tata bahasa (grammar) dan retorik, yang merupakan bagian dari tradisi pengajaran ulama-ulama Islam di zaman klasik.[9]
Minimnya kontemplasi dan berpikir mendalam untuk mengungkap makna, membuat para muslimah lemah dalam pengenalan terhadap sifat dan karakter diri. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah yang membedakan perempuan dengan laki-laki? tipe perempuan seperti apakah saya? apakah kekuatan dan kelemahan saya? hal-hal tersebut harus diketahui jawabannya oleh para muslimah. Muhammad Utsman al Huts menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan namun tidak menjadikan yang satu lebih mulia dari yang lainnya, melainkan keduanya setara dalam nilai, meskipun nilai masing-masing berasal dari jenis yang berbeda. Sunnatullah telah menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda secara natural penciptaannya dan fitrahnya. Hal tersebut dimaksudkan apabila keduanya bertemu, masing-masing akan berusaha keras untuk bersatu dengan lawan jenisnya, untuk saling melengkapi dan demi mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan percampuran tersebut.[10]
Perempuan meskipun secara umum memiliki kesamaan fisik dan psikologis, namun sebagai individu, tentunya terdapat perbedaan sifat dan karakter antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak menafikan temuan-temuan ilmu psikologi Barat tentang tipe-tipe keperibadian, gaya belajar, dan lain-lain. Pengenalan terhadap sifat, minat dan bakat akan membuat seorang perempuan lebih fokus dalam memilih bidang-bidang yang ingin dipelajarinya. Waktu hidup manusia sangat terbatas, sehingga perlu prioritas dalam menuntut ilmu yang paling bermanfaat untuk dipelajari. Namun demikian, tentunya diharapkan para psikolog Islam dapat menemukan teori-teori kepribadian yang sesuai dengan Islamic worldview.
Problem internal lainnya, banyak perempuan tidak mengetahui peran-peran apa yang cocok bagi dirinya, yang sesuai dengan fitrah perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Problem ini terkait dengan dua problem sebelumya, yaitu kurangnya kontemplasi dan berpikir untuk mengenali hakikat dan tujuan hidup, serta karakter dan sifat diri. Banyak perempuan terlibat dalam aktivitas publik, semata-mata untuk menunjukkan eksistensi diri atau terbawa cara pandang feminis yang mengatakan bahwa wanita harus berkontribusi secara ekonomi demi kemajuan sebuah bangsa. Ada juga yang sekedar ikut-ikutan, tidak tahu kemana dan dimana ia harus menyalurkan potensinya. Profesi ibu rumah tangga akhirnya ditinggalkan demi mengejar status sosial di masyarakat.
Kita temukan juga fenomena wanita yang memilih diam di rumah karena beranggapan Islam melarang perempuan untuk berperan dalam kegiatan publik, padahal sejarah peradaban Islam mencatat berbagai peran perempuan dalam aktivitas publik, terutama dalam bidang keilmuan. Sebagai contoh, Hafiz Ibn Najjaar, memiliki 400 guru perempuan, Hafiz Ibn ‘Asakir menarasikan hadits dari 80 perempuan, Hafiz Abu Thair al-Silafi mempelajari hadits dari 10 orang guru perempuan, dan Imam Ibn Taymiyah menerima hadits dari sejumlah ulama perempuan, dan masih banyak lagi.[11] Jadi kenyataan pada saat ini, ada perempuan yang berlebih-lebihan dan memaknai kebebasan secara kebablasan, namun ada juga yang terlalu ekstrim dan menutup diri dari peradaban karena penafsiran terhadap wahyu yang sempit.
- Faktor Eksternal / lingkungan
Faktor lingkungan fisik dan sosial, berperan banyak mempengaruhi lemahnya tradisi keilmuan di kalangan perempuan pada masa sekarang. Faktor-faktor fisik dan sosial, mencakup filsafat dan sistem pendidikan yang masih berkiblat kepada pendidikan sekuler-Barat, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung budaya ilmu, merupakan faktor primer dari tenggelamnya tradisi keilmuan Islam secara umum yang juga berdampak kepada kaum perempuan. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan krisis keilmuan adalah :
- Lemahnya kepemimpinan laki-laki. Saat ini, banyak lelaki muslim kurang memiliki pemahaman tentang konsep keluarga dalam Islam, sehingga perempuan dan anak-anak banyak yang menjadi korban dari ketidakharmonisan rumah tangga. Padahal kewajiban utama suami adalah mendidik keluarga dalam meniti jalan ilmu dan membimbing mereka agar selamat dari fitnah dunia. Tidak bisa dinafikan, salah satu penyebab feminisme begitu mudah diterima oleh kalangan muslimah, disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan laki-laki karena mereka tidak lagi menjadi representasi dari keindahan ajaran Islam.
- Lingkungan fisik yang kurang mendukung perempuan untuk menuntut ilmu. Sebagai contoh, buruknya sarana transportasi umum yang menyebabkan sulitnya para perempuan untuk beraktivitas secara efektif dan aman dari ancaman kejahatan seksual. Meskipun saat ini banyak pilihan belajar online dari rumah, namun serbuan entertainment juga membuat perempuan mudah teralihkan dan tidak fokus dalam menuntut ilmu. Padahal salah satu kunci keberhasilan dalam belajar menurut ulama adalah “free yourself from worldly distraction.”
- Kurangnya otoritas keilmuan yang memahami permasalahan perempuan, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Hal ini menimbulkan banyak orang yang kurang berilmu namun menjadi otoritas, terutama dalam permasalahan fikih. Munculnya penulis-penulis yang sekedar “writer” dan bukan “author” –yaitu yang menulis dengan otoritas– sehingga banyak perempuan menuntut “ilmu” pada orang-orang yang kurang kompeten baik secara ilmu maupun adab. Padahal menurut al-Attas, ilmu Islam dan Islamic worldview harus berdasarkan pada otoritas yang sebenar dan bukan yang palsu.[12]
- Kurangnya referensi tentang tokoh-tokoh intelektual muslimah di masa lalu yang bisa menjadi teladan bagi perempuan masa kini. Salah satu strategi feminis liberal dalam mengkampanyekan ideologinya adalah dengan menampilkan ikon-ikon perempuan modern yang dikesankan sebagai perempuan cerdas, cantik, modis, bebas dan mandiri. Mereka berusaha mempengaruhi kaum muslimah untuk menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai idola dan mengikuti gaya hidup mereka yang jauh dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, umat Islam perlu memperkenalkan dan mensosialisasikan biografi para ulama perempuan untuk membangkitkan semangat para muslimah dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama.
- Kurangnya perhatian terhadap upaya pembersihan jiwa di kalangan komunitas muslimah yang menyebabkan munculnya penyakit hati seperti iri dan dengki, kurang bersyukur, tidak sabar dan lain lain. Penyakit hati tersebut akhirnya menjadi penyebab utama dari perpecahan di kalangan umat termasuk muslimah. Menurut Wan Abdullah, dalam tradisi intelektual Islam, ada dua pendekatan utama dalam menghadapi problem kejiwaan; pertama berdasarkan ajaran Islam dan pendekatan kedua mengikuti tradisi asing. Pendekatan pertama dapat ditemukan dalam berbagai tradisi keilmuan Islam, terutama kalam, fikih dan tasawuf. [13] Kurangnya pengkajian terhadap kondisi jiwa tersebut disebabkan oleh penolakan sebagian masyarakat muslim terhadap cabang ilmu tentang ihsan, tazkia atau tasawuf. Akibatnya, banyak perempuan di zaman ini, saling berlomba menampakan “kesalehan fisik” namun lupa untuk mengasah jiwa agar senantiasa ikhlas. Sejak dulu para ulama Islam menaruh perhatian khusus kepada ilmu makrifat ini karena keutamaannya yang tinggi. Ibnu Atha’illah berkata, “Amal itu seumpama jasad, sedangkan keikhlasan adalah ruhnya.”[14]
Sedangkan Imam al Ghazali telah membagi ilmu menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah ilmu yang sudah jelas kebenarannya, termasuk di dalamnya adalah ilmu agama Islam. Ilmu ini dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebijaksanaan dalam berpikir. Sifat manusia sebagai insan yang paling mulia terletak pada kerja akal. Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai khilafah, pengemban amanah di muka bumi untuk memakmurkannnya. Kedua, ilmu dinilai berdasarkan kemanfaatan bagi manusia secara umum di dunia maupun di akhirat. Namun kita harus meninggalkan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Manusia mulia bukan karena jasad fisiknya. Kemuliaan manusia terletak pada jiwanya. Maka, ilmu kategori ketiga ini terkait dengan tempat termulia dalam diri manusia, yaitu jiwa. Ilmu yang mengajarkan cara untuk membersihkan hati manusia dari kotoran dan kemaksiatan, membimbing manusia untuk mendekatkan manusia pada Allah SWT. Berilmu adalah sifat hamba Allah ‘Azza wa Jalla, yang akan membawa dirinya masuk ke dalam surga.
Menurut Wan Daud dalam bukunya Budaya Ilmu, penanaman dan penyuburan budaya ilmu yang sempurna memerlukan keikhlasan dan kesungguhan karena upaya tersebut tidaklah mudah dan memerlukan proses yang lama. Membangun budaya ilmu juga memerlukan keberanian karena jika tidak maka timbul kompromi-kompromi terhadap hal yang sebenarnya tidak bisa dikompromikan, atau merubah pondasi dan institusi yang sebenarnya tidak boleh diubah.[15] Oleh karena itu, bukan hanya laki-laki, namun kaum perempuan juga memiliki peran sangat stategis dalam mewujudkan budaya ilmu. Caranya dengan menempa diri untuk menjadi “virtuous person”, yaitu pribadi yang ikhlas dan sungguh-sungguh serta memiliki keberanian dalam menempuh jalan ilmu, semata-mata hanya untuk meraih cinta dan ridho dari Tuhannya, yaitu Rabb Semesta Alam.
REFERENSI
Acikgenc , Alparslan. 1996. Islamic Science; Towards a Definition, Kuala Lumpur: ISTAC.
Al Husyt, Muhammad Utsman. 2003. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan : Tinjauan Psikologi, Fisiologi, Sosiologi dan Islam, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim.
Al-Attas, Syed M. Naquib, Islam: The Concept of Religion and The Foundation of Ethics and Morality, Kuala Lumpur : IBFIM, 2013.
Al-Attas, Syed M. Naquib. 2002. Ma’na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam, Kuala Lumpur : ISTAC.
Al-Ghazali, Imam. 2011. Ihya Ulumuddin 1: Ilmu dan Keyakinan, Jakarta : Republika.
Dinar Dewi Kania. 2018. Pemikiran Epistemologi Al-Attas & Schuon. Ponorogo : Unida Gontor Press
Jenkins, Muhammad Al-Mahdi & Abdul Aziz Azimullah. 2016. Positive Islamic Psychology, Kuala Lumpur : Excellent Ummah Development Association.
Nadwi, Mohammad Akram. 2007. Al-Muhaddithat : The Women Scholars in Islam, Oxford : Interface Publication.
Wan Abdullah, Wan Suhaimi. 2015. “The Nature of Man and The Meaning of Happiness : an Obersvation on Some Major Keywords”, A Companion to The Worldview of Islam : Course Materials for Wise Summer School 2015, Selangor: Himpunan Keilmuan Muslim.
Wan Daud, Wan Mohd. Nor. 1989. Konsep Ilmu dalam Islam, Bandung: Penerbit Pustaka.
Wan Daud, Wan Mohd. Nor. 2019. Budaya Ilmu : Makna dan Manifestasi dalam Sejarah Masa Kini. Kuala Lumbur : Casis – Hakim
FootNote:
[1] Peneliti Insists & Direktur CGS
[2] Mohammad Akram Nadwi. 2007. Al-Muhaddithat : The Women Scholars in Islam, Oxford : Interface Publication, hlm. XV
[3] Ibid. hlm. XIV
[4] Struktur ilmu dalam pandangan alam Islam (Islamic Worldview) dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu. Alparslan mengemukakan apabila sejarah intelektual Islam pada masa awal dipelajari secara teliti maka akan terlihat benih dari beberapa ilmu/sains telah tampak sejak masa Rasulullah terutama pada periode ketiga seperti sejarah, hukum, kesusasteraan, grammar, falsafah, dan teologi yang kesemuanya masih pada tahap awal. Pada akhir abad kesatu Hijriah, kebanyakan ilmu telah terakumulasi dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut dan berproses untuk menjadi ilmu/sains. Pada proses ini dapat disimpulkan bahwa struktur ilmu telah terbentuk pada Islamic worldview. Lihat Alparslan Acikgenc. 1996. Islamic Science; Towards a Definition, Kuala Lumpur: ISTAC, hlm. 76, 80
[5] Menurut Wan Daud, dilihat dari aspek linguistik, kata‘ilm bermakna luas. Sejak dahulu umat Islam menganggap ‘ilm (ilmu) berarti al-Qur’an; syari’at; sunnah, Islam, iman; ilmu spiritual (‘ilm al-ladunni), hikmah dan ma’rifah, atau sering disebut juga sebagai cahaya (nūr); pikiran (fikrah), sains (khususnya ‘ilm yang jamaknya ‘ulūm), dan pendidikan – yang kesemuanya menghimpun hakikal ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab digambarkan dengan istilah al-‘ilm, al-ma’rifah, dan al-syu’ūr (kesadaran). Namun, dalam pandangan dunia Islam, yang pertamalah yang terpenting karena ia merupakan salah satu sifat Tuhan. Julukan-julukan yang dikenakan kepada Tuhan adalah al-‘Âlim, al-‘Alîm dan al-‘Allâm, yang semuanya berarti Maha Mengetahui; tetapi Dia tidak pernah disebut al-‘Ârif atau al-Syâ’ir. Wan Muhammad Nor Wan Daud. 1989. Konsep Ilmu dalam Islam, Bandung: Penerbit Pustaka, hlm. 65
[6] Muhammad Al-Mahdi Jenkins & Abdul Aziz Azimullah. 2016. Positive Islamic Psychology, Kuala Lumpur : Excellent Ummah Development Association,
[7] Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Positive Aspects of Tasawwuf, hlm. 3
[8] Dinar Dewi Kania. 2018. Pemikiran Epistemologi Al-Attas & Schuon. Ponorogo : Unida Press
[9] Syeikh Hamza Yusuf dalam berbagai lecturenya.
[10] Muhammad Utsman al Husyt. 2003. Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan : Tinjauan Psikologi, Fisiologi, Sosiologi dan Islam, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, hlm. 14-15
[11] Mohammad Akram Nadwi, al-Muhaddithah, hlm. XXI dan 141
[12] Al-Attas, S.M. Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur : ISTAC. hlm. 107
[13] Wan Suhaimi Wan Abdullah. 2015. “The Nature of Man and The Meaning of Happiness : an Observation on Some Major Keywords”, A Companion to The Worldview of Islam : Course Materials for Wise Summer School 2015, Selangor: Himpunan Keilmuan Muslim. hlm. 42
[14] Ibnu Atha’illah as-Sakandari, Al Hikam : Kitab Rujukan Ilmu Tasawuf Edisi Lengkap 3 Bahasa, Jakarta : Wali Pustaka, 2016.
[15] Wan Mohd Nor Wan Daud. 2019. Budaya Ilmu : Makna dan Manifestasi dalam Sejarah Masa Kini. Kuala Lumbur : Casis – Hakim. hlm. 10-11.