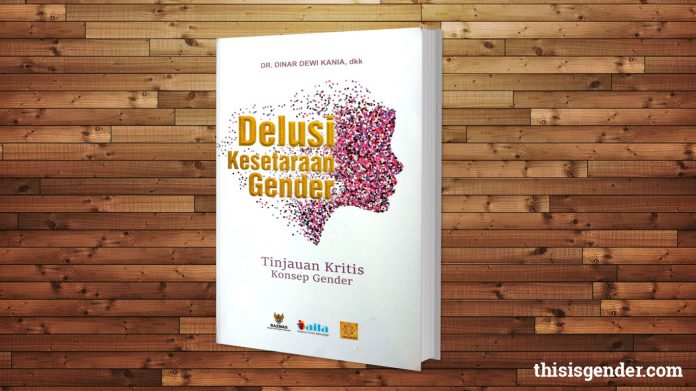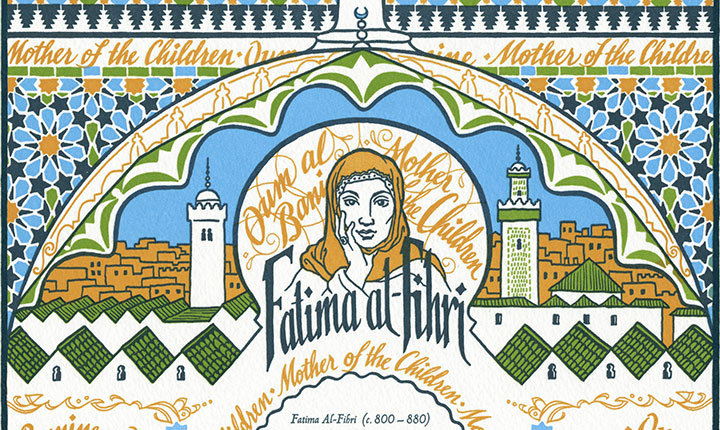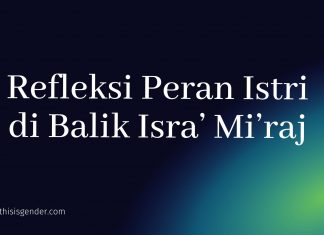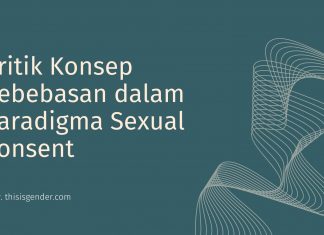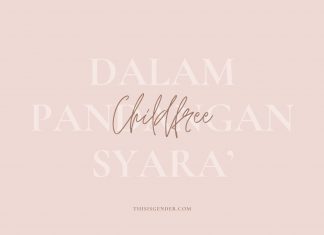Oleh: Moh. Khuza’i, M.A
PENDAHULUAN
Para feminis dalam membangun wacana kesetaran gender seringkali memulainya dengan pembedaan antara definisi seks dan gender.[1] Dua istilah tersebut lazim kita anggap sama, yakni bermakna jenis kelamin manusia yang terdiri dari lelaki atau perempuan dan sifatnya mutlak harus diterima sebagaimana mestinya.[2] Namun, menurut mereka hal tersebut hanya terbatas pada pembagian manusia secara biologis, inilah yang didefinisikan sebagai seks,[3] sedangkan gender diberi definisi baru sebagai kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki (maskulin) atau perempuan (feminim).[4] Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang meliputi perbedaan organ-organ seks dan juga hormon tidak menjadi perdebatan, namun pendapat tentang ada atau tidaknya pengaruh dari perbedaan tersebut dalam pembentukan sifat maskulin atau feminim masih belum menemukan kata sepakat. Akhirnya, dari dua argumen ini kemudian muncul konsep nature dan nurture.
Pemahaman yang tepat dan mendalam mengenai definisi gender serta konsep nature dan nurture merupakan faktor yang menentukan dalam memahami kajian feminisme. Pegiat feminisme yang jelas terpengaruh liberalisme pemikiran dan juga humanisme tentunya lebih condong pada konsep nurture.[5] Dari sanalah tatanan agama, budaya, dan norma yang awalnya dianggap mapan secara perlahan didekonstruksi karena dianggap sebagai bentuk hegemoni laki-laki dan sumber penindasan atas perempuan.[6] Kini, dengan maraknya wacana tentang kesetaraan gender, maka konsep tersebut juga semakin dibenarkan, sedangkan di sisi lain konsep nature dikaji dengan sangat hati-hati bahkan cenderung ditinggalkan.[7] Lazimnya, pemaknaan gender dan juga dua konsep tersebut dikaji secara netral dan komprehensif, agar perempuan yang dalam hal ini menjadi subjek sekaligus objek kajian mampu menimbang dengan bijak isu-isu feminisme yang berkembang, bukan dengan emosi karena asumsi ketimpangan gender, subordinasi perempuan, dan lain sebagainya.[8]
Makalah ini berusaha untuk mengkaji konsep nature dan nurture melalui pendekatan dan metode sebagai berikut: Pertama, dengan mengkaji definisi dari term gender, nature, dan nurture dari beberapa aspek yang bisa penulis jangkau sekaligus meninjau secara sosio-historis mengenai munculnya term-term tersebut dalam diskursus gender. Kedua, kritik terhadap definisi gender serta konsep nature dan nurture secara khusus dengan negasi dari wacana yang berkembang serta membandingkannya dengan realitas kekinian. Terakhir, menyimpulkan dengan perspektif Islam dan juga mencoba menyajikan alternatif dalam menyikapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau dengan memberikan bukti adakah kecondongan Islam kepada salah satu dari konsep yang diperdebatkan.
DEFINISI DAN RUANG LINGKUP
Istilah gender serta konsep nature dan nurture sebelumnya tidak dikenal dalam kebudayaan Indonesia. Term-term tersebut merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, makna yang dikandungnya merupakan asimilasi atau terjemahan langsung sebagaimana makna dalam bahasa aslinya. Berikut adalah penjabaran definisi dari kata-kata tersebut:
- Gender
Dalam kajian Feminisme, Gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis.[9] Pegiat kesetaraan gender secara sederhana membedakan definisi seks sebagai jenis kelamin biologis sejak lahir yakni laki-laki atau perempuan berdasar alat kelamin yang dimiliki, sedangkan gender adalah “jenis kelamin” sosial berupa atribut maskulin atau feminim yang merupakan konstruksi sosial budaya.[10] Menurut mereka atribut maskulin tidak harus dilekatkan pada jenis kelamin laki-laki dan sifat feminim juga tidak mesti untuk perempuan, karena atribut-atribut tersebut bukan merupakan bawaan yang bersifat kodrati, melainkan terbentuk secara sosio-historis yang sifatnya tidak tetap dan bisa dipelajari, sehingga bisa dipertukarkan lintas seks.[11] Pendefinisian semacam ini berbeda dengan makna awal kata tersebut dalam bahasa aslinya dan ketika diperkenalkan dalam bahasa lain juga terjadi problem, karena sebelumnya memang tidak ada bahasa dan kebudayaan yang membedakan antara jenis kelamin biologis dengan “jenis kelamin” sosial.[12]
Sejarah munculnya terminologi gender tidak bisa dilepaskan dari kajian ilmu humaniora, terutama psikologi dan juga terkait dengan tren transseksual.[13] Dalam bahasa Inggris, pembedaan makna antara sex dan gender pertama kali dikenalkan oleh para psikiater Amerika dan Inggris serta para petugas medis yang bekerja dengan pasien transseksual dan interseks pada tahun 1960-an dan 1970-an.[14] Istilah ini kemudian dipergunakan oleh para feminis sebagai sanggahan melawan argumen tentang faktor biologi gender sebagai takdir.[15] Sejak saat itu konsep ini diadopsi secara luas sebagai sistem analisa kajian pengembangan gender gerakan feminisme global.[16]
- Nature
Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia.[17] Dalam kajian gender, term nature diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks). Disebut sebagai teori nature karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya secara alami.[18] Jadi, seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan mencipatakan hubungan yang serasi.[19]
Teori nature akrab dengan ilmuwan klasik dan religius. Terkadang teori ini juga dikaitkan dengan Rousseau, Kant, dan Hegel, namun yang dianggap sebagai peletak dasar teori ini secara ilmiah adalah Charles Darwin[20] dan didukung oleh teori hereditas Gregor Mendel.[21] Dalam kajian gender, teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan[22] dan Alice Rossi[23] yang pada akhirnya membelokkan diskursus feminisme ke arah biological essentialism pasca tahun 1980-an yang ditandai dengan penerimaan kembali konsep perbedaan peran gender. Dibarengi dengan konsep ekofeminisme,[24] argumentasi ini mampu membawa konsep nature menjadi lebih dominan. Para penggagas teori ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman.[25]
- Nurture
Secara etimologi nurture berarti kegiatan perawatan/pemeliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak.[26] Terminologi kajian gender memaknainya sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya.[27] Dinamakan nurture karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun.[28] Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep culture.[29] Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami.[30]
Perbedaan konstruk sosial dalam masyarakat mengakibatkan relatifitas tolak ukur atribut maskulin dan feminim antar budaya. Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya.[31] Dari sini feminis dan pegiat gender mulai membedakan gender dengan seks dan menyimpulkan bahwa gender–dengan definisi barunya–adalah sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya.[32]
Definisi baru tersebut juga menjurus pada dekonstruksi norma dan tatanan yang ada.[33] Peraturan, kebiasaan, penilaian, dan perlakuan yang di dalamnya terdapat perbedaan dan pembedaan antara lelaki dan perempuan mulai dikaji ulang dengan sudut pandang feminisme dan kesetaraan gender, dari sinilah muncul istilah-istilah semacam ketimpangan gender,[34] bias gender,[35] hegemoni patriarki,[36] sexisme,[37] dan misogini.[38] Jadi, menurut mereka kesetaran secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin adalah satu-satunya solusi dari perbedaan yang terjadi.[39]
Perkembangan konsep ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pengusungnya. Di antaranya adalah Margaret Mead, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir,[40] Sigmund Freud,[41] Hilary M. Lips, Ann Oakley,[42] Nancy Chodorow, Judith Butler, dan lain-lain.[43] Berbeda dengan teori nature yang kebanyakan tokohnya adalah ilmuwan yang agamis, teori nurture diusung oleh pakar ilmu-ilmu humaniora yang cenderung humanis dan dekonstruktifis.[44] Perbedaan metodologi yang digunakan dan juga cara pandang antar tokoh dalam kedua konsep ini menyebabkan perdebatan antara nature dan nurture belum menemukan titik temu dan belum dapat diketahui yang mana pemenangnya.[45]
Perdebatan antara dua konsep ini memiliki pengaruh dominan dalam mewarnai pergerakan feminisme, begitu pula perbedaan dalam memaknai term gender. Keduanya sudah berlangsung kurang lebih selama 50 tahun. Penganut konsep nurture yang didominasi feminis liberal dan sosialis mengklaim bahwa perkembangan teknologi kelak justru akan mampu membuktikan bahwa faktor biologis tidak memiliki peran dalam pembentukan karakteristik manusia serta menghilangkan batas-batas gender dan jenis kelamin.[46] Klaim berbeda diungkapkan penganut konsep nature, menurut mereka feminis penganut nurture justru merendahkan, merugikan, serta melenceng dari tujuan awal feminisme dan kelak akan ditinggalkan oleh perempuan.[47] Namun ada poin yang menarik dari tiga belas agenda manifesto [feminis] gelombang ketiga, salah satunya mengakui bahwa meskipun ada kemungkinan feminis berseberangan pendapat, namun kesemuanya berbagi tujuan yang sama yakni kesetaraan, dan saling mendukung sesama dalam usaha memperoleh kekuatan untuk menciptakan pilihan.[48] Jadi, seharusnya kedua konsep ini tetap harus dikaji lebih mendalam, bukan secara serta-merta diterima.
KRITIK TERHADAP DEFINISI GENDER SERTA KONSEP NATURE DAN NURTURE
Dari uraian-uraian sebelumnya, sekilas saja sudah cukup menggambarkan bahwa memang ada problem dalam definisi gender serta konsep nature dan nurture. Problem akibat feminisme yang dihadapi perempuan Barat, seharusnya tidak akan terjadi juga di Timur apabila pengarusutamaan gender dan feminisme global disikapi dengan kritis, baik dari sudut pandang agama maupun sosio historis. Namun, di saat konsep-konsep tersebut mulai ditinggalkan di negara-negara asalnya, ternyata justru merebak di negara-negara berkembang karena dianggap sebagai pembaharuan.[49]
Feminisme lahir di peradaban Barat dengan kondisi sosio-historis yang belum tentu sama dengan kondisi perempuan Timur, khususnya Islam. Namun, klaim penerapan kesetaraan gender sebagai satu-satunya solusi atas ketertinggalan perempuan Timur, ternyata diamini tanpa kritik dan kontrol.[50] Yang juga perlu disayangkan adalah hal-hal yang membawa dampak negatif seperti kebebasan dan anti kemapanan justru yang lebih banyak diambil, seakan kebebasan semacam itu yang menyebabkan kemajuan Barat. Adapun isu-isu tentang pengembangan pendidikan dan keterampilam perempuan serta masalah-masalah lain justru jarang menjadi fokus, jadi saat kesempatan memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki terbuka lebar, ternyata belum dibarengi dengan kemampuan perempuan dalam menjalankan kewajiban yang melekat dengan hak-hak tersebut. Akhirnya, feminisme tidak lagi menjadi gerakan pemberdayaan perempuan melainkan memperdaya perempuan dengan klaim tentang ketertindasan, diskriminasi, dan lain sebagainya.
Konsep nature sekilas mengakui adanya “fitrah” yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik secara biologis maupun sosial, namun konsep yang ada tidak terintegrasi dengan worldview tentang Tuhan serta agama sehingga memungkinkan terjadinya miskonsepsi.[51] Konsep ini memang mengakui adanya kekuatan alam berupa kodrat biologis serta pengaruhnya dalam pembedaan peran serta perilaku antara laki-laki dan perempuan, namun konsep tersebut ternyata juga belum mampu memberikan batasan yang jelas. Akibatnya, perbedaan budaya yang dihasilkan manusia dalam memahami alam dapat mengaburkan konsep ini, meski secara garis besar ada kesamaan, namun perbedaan yang ditemukan juga banyak.[52] Universalitas ajaran dan syariat Islam dengan tauhiêd dan diên sebagai dasarnya adalah solusi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dan mengantarkan manusia pada hakikat fitrah.
Makna dari term kodrat dan hukum alam dalam konsep nature masih lebih sempit cakupannya dibanding konsep fitrah dalam Islam. Penemuan-penemuan ilmiah dalam ilmu pengetahuan modern tentang perbedaan gen, fungsi hormonal, perbedaan psikologis antar jenis kelamin, dan lain sebagainya cukup dimaknai sebagai hikmah di balik pembedaan tata cara ibadah dan pembagian peran yang disyariatkan Islam. Iman dan ibadah semata-mata karena Allah harus tetap menjadi alasan dan tujuan dari ketaatan dalam menjalankan syariat-syariat tersebut. Konsep fitrah mewakili semua itu, penciptaan manusia dalam perspektif Islam lebih dari sekedar proses alami, tetapi dengan tujuan serta amanah khusus yang diemban, yakni sebagai wakil Allah di bumi juga sebagai hamba yang wajib mematuhi hukum-Nya.[53]
Definisi gender yang diwacanakan konsep nurture, ternyata memisahkan antara aspek biologis dan sosial. Padahal, ada pula aspek biologis yang bersifat kodrati yang turut mempengaruhi konstruk sosial dalam membedakan peran dan kebiasaan antara laki-laki dan perempuan,[54] Selain itu, pada kenyataannya feminis juga belum mampu memberi batasan yang jelas mana yang konstruk sosial dan mana yang kodrat.[55] Permasalahan lainnya, aspek budaya yang dianggap sebagai pembentuk gender bersifat relatif, sehingga setiap individu seakan mendapat pembenaran atas perbuatannya. Salah satu akibatnya adalah perilaku seksual menyimpang yang dulu dianggap tabu, sekarang justru dianggap modernitas dan hak asasi.[56] Banyak dari kalangan feminis sendiri yang tidak setuju dengan konsep ini, karena dianggap telah menyimpang dari tujuan awal dan justru mengakibatkan perempuan kehilangan jati diri dan moral. Tentang penyimpangan seksual yang terjadi, apabila kajian humaniora berpijak pada kebenaran ilmu pengetahuan harusnya tidak akan membenarkan hal tersebut.[57] Lagipula, pada kenyataannya tetap lebih banyak manusia dengan orientasi seks yang normal serta berpasangan dengan gender yang berbeda dengan tujuan mendapat keturunan adalah berlaku secara universal, lintas budaya dan peradaban, bahkan dalam dunia hewan dan tumbuhan yang tidak memungkinkan adanya kebudayaan sekompleks manusia sekalipun.
Islam tidak memisahkan gender dengan jenis kelamin dan agama tidak seharusnya disamakan dengan budaya. Menurut para feminis dan pegiat gender, doktrin agama berupa hal-hal yang mengatur hubungan antar gender[58] atau ketentuan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan[59] harus disesuaikan dengan sudut pandang kesetaraan gender.[60] Tidak jarang tuntutan tersebut disertai tuduhan bahwa syariat yang sampai pada kita sekarang bukan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, melainkan rekayasa budaya patriarki melalui para mufassir dan fuqahá’ untuk melanggengkan hegemoninya.[61] Padahal, tidak semua orang dapat menjadi mujtahid, ada syarat yang ketat berupa ilmu dan juga akhlak, itulah mengapa dalam tradisi Islam sebelumnya meski terkadang ditemukan beberapa perbedaan pendapat antar mujtahid, namun tidak pernah ada tuduhan-tuduhan semacam itu sebelumnya. Akhirnya, karena syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para feminis dan pegiat gender, maka tidak mengherankan bila hasil “ijtihad” dengan dalih pembaharuan yang mereka lakukan selain melenceng jauh dari ijtihad ulama terdahulu ternyata juga lebih sarat kepentingan, terlalu memaksakan dalil-dalil agama sebagai pembenaran atas wacana feminisme dan humanisme yang mereka usung.[62]
PENUTUP
Masuknya faham feminisme harus disikapi dengan kritis, karena secara historis tidak membuat wanita menjadi lebih baik. Selain karena problem dalam konsepnya juga karena akibat negatif yang ditimbulkannya. Kehati-hatian juga sangat dibutuhkan, karena seringkali para pegiat gender menunjukkan fakta tentang ketertinggalan perempuan serta penindasan atasnya, namun dengan penyebab dan alasan yang telah diselewengkan. Dibanding feminisme, Islam memiliki konsep yang lebih baik dalam menyikapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yakni berupa konsep fitrah dan amanah.
Pada hakikatya, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Keduanya memiliki tujuan serta amanah yang sama, adapun perbedaan peran dan perilaku antara keduanya adalah sesuai fitrah dan pembedaan dalam ibadah amaliyah serta syariat yang harus dijalankannya mengandung hikmah. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut bukan berarti salah satu gender diistimewakan dibanding yang lain, buktinya Allah menjanjikan surga yang sama bagi mereka yang beriman dan neraka yang sama bagi mereka yang ingkar, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Di antara feminis sendiri ada perdebatan dalam memaknai perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta kesetaraan. Pertama, penganut konsep nature yang menganggap perbedaan adalah alami, sehingga kesetaraan yang dibutuhkan adalah keadilan sesuai konteks. Kedua, penganut konsep nurture yang menganggap perbedaan adalah buatan manusia, terutama oleh laki-laki, sehingga dalam menyikapi perbedaan kelompok ini menuntut penghapusan batas-batas gender dan memaknai kesetaran adalah persamaan secara kuantitatif.
Adapun definisi gender yang hendak dibedakan dari jenis kelamin memiliki efek negatif bagi perempuan. Ketika perbedaan peran dan perilaku dianggap tidak terikat dengan faktor biologis, justru mengakibatkan hilangnya jati diri perempuan, karena saat batas antar gender dihapus yang terjadi adalah perempuan merasa rendah diri dengan sifat feminimnya dan akhirnya meniru sifat maskulin. Definisi baru tersebut juga berakibat pada merosotnya moral, karena norma dan tatanan yang berlaku tidak lagi dianggap sifat alami manusia, karena budaya serta konstruk sosial juga sudah direlatifkan, akhirnya setiap individu memiliki standar moral sendiri.
Tidak seharusnya agama disamakan dengan konstruk sosial serta budaya dan tidak ada pembenaran untuk merubah-rubah hukum Islam dengan alasan kesetaraan gender atau dengan alasan yang lain. Bukan konstruk sosial dan budaya yang membentuk karakter seseorang, sebaliknya dari kesamaan sifat bawaan setiap individu terbentuklah budaya. Dari sifat bawaan maskulin dan feminim terbentuk budaya yang mengatur perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal tersebut berlaku global, perubahan atasnya pasti akan dianggap menyimpang oleh banyak orang. Budaya yang merupakan ciptaan manusia saja tidak semudah itu dirubah atas nama kesetaraan gender, apalagi untuk merubah peraturan agama ciptaan Tuhan.
DAFTAR PUSTAKA
Arif, Syamsuddin. 2008. Orientalis & Diabolisme Pemikiran. Depok: Gema Insani Press.
Baharuddin. 2004. Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bryson, Valerie. 2003. Feminist Political Theory: an Introduction, Ed. II. New York: Palgrave Macmillan.
Butler, Judith. 2004. Undoing gender, Cet. X. New York dan London: Routledge.
Esplen, Emily dan Susie Jolly. 2006. Gender and Sex: A Sample of Definitions. Brighton: BRIDGE.
Freedman, Estelle B., (editor). 2007. The Essentsial Feminist Reader. New York: The Modern Library.
Gardner, Catherine Villanueva. 2006. Historical dictionary of feminist philosophy. Maryland: Scarecrow Press.
Gilligan, Carol. 2003. In a different voice: Psychological Theory and Women’s Development, (cet. 38; Cambridge, Massachusetts, & London: Harvard University Press, 2003)
Hastuti, Sugi dan Siti Hariti Sastriyani. 2007. Glosarium Seks dan Gender. Yogyakarta: Çarasvati Books.
Hooks, Bell. 2000. Feminism is for Everybody: Passionate Politics. Cambrigde: South End Press.
Hornby, A S, et. al., 2010. Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition.
Humm, Maggie. 2007. Dictionary of Feminist Theories, penj. Mundi Rahayu. Yogjakarta: Fajar Pustaka.
Ilyas, Hamim, et. Al. 2009. Perempuan Tertindas?; Kajian Hadis-hadis “Misoginis” Cet. IV. Yogyakarta: eLSAQ.
Kuiper, Kathleen. 2010. The 100 most Influential Women of All Time. New York: Britannica Educational Publishing.
Lippa, Richard A., 2005. Gender, Nature, and Nurture, Ed. II. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
Mead, Margaret. 1963. Sex and Temperament in Three Primitive Societies, Cet. III. New York: Morrow.
Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Penerbit Mizan.
Mulia, Musdah. 2011. Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi. Jakarta: Penerbit MARJA.
Muslikhati, Siti. 2004. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam. Depok: Gema Insani Press.
Pilcher, Jane dan Imelda Whelehan. 2004. Fifty Key Concepts in Gender Studies. London, California, dan New Delhi: SAGE Publications.
Plomin, Robert dan Gerald E. McClearn, (editor). 1993. Nature, nurture, and psychology. Washington DC: American Psychological Association.
Shalahuddin, Henri, et.al., 2012. Indahnya Keserasian Gender dalam Islam. Jakarta: KMKI.
Stanton, Elizabeth Cady. 1898. The Woman’s Bible. New York: European Publishing Company.
Sterling, Anne Fausto. 2000. Sexing the Body: gender politics and the construction of sexuality. New York: Basic Books.
Umar, Nasaruddin. 2001. Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ân, Cet. II. Jakarta: Penerbit PARAMADINA.
Wadud, Amina. 1999. Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. New York: Oxford University Press, Inc.
Worell, Judith, (editor). 2002. Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender. California: Academic Press.
Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2010. Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis, Cet. II. Ponorogo: CIOS.
Arsip, software, dan referensi dari internet
Firdaus, Muhammad Royyan, “HAM untuk LGBT” (http://islamlib.com/id/artikel/ham-untuk-lgbti.htm.
Merriam-Webster 11th Collegiate Dictionaryز
Pappas, Theodore, et al., Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (Ed. XVI; Encyclopaedia Britannica, Inc., 2012) [DVD]
Rancangan Undang-undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (Agustus 2011) [PDF]
[1] Misalnya Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ân, (Cet. II; Jakarta: Penerbit PARAMADINA, 2001), h. 33‐35. Dengan mengutip dari Tierney (tanpa tahun: 153), Lips (1993: 4), Lindsey (1990: 2), Wilson (1989: 2), dan Showalter (1989: 3), Nasaruddin menyimpulkan gender sebagai konsep untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Lihat juga Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi (Jakarta: Penerbit MARJA, 2011), h. 64‐55. Musdah yang juga mengutip dari Tierney dan Showalter menyimpulkan bahwa gender merupakan sesuatu yang dibentuk secara sosial dan bukan sesuatu yang kodrati dala diri manusia. Keduanya meletakkan penjelasan mengenai definisi gender sebelum masuk pada pokok pembahasan.
[2] Gender merupakan kosa kata baru yang belum ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada bahasa-bahasa lain kata tersebut lazimnya juga masih disamakan definisinya dengan seks.
[3] Seks merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris “sex” yang diterjemahkan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pembagian manusia secara biologis, yaitu lelaki atau wanita. Namun, dalam pemakaian sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, kata ini disalahartikan sebagai hubungan badan. Lihat Siti Muslikhati, Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam, (Depok: Gema Insani Press, 2004), h. 19.
[4] Maggie Humm, Dictionary of Feminist Theories, diterjemahkan oleh Mundi Rahayu dengan judul Ensiklopedia Feminisme (Jogjakarta: Fajar Pustaka, 2007), h. 177-180. Secara perlahan feminis kontemprer membedakan antara jenis kelamin dan gender. Berlandaskan pada Mead (1935), teori ini menempatkan pandangan bahwa jenis kelamin adalah biologis dan perilaku gender adalah konstruksi sosial.
[5] Bell Hooks, Feminism is for Everybody: Passionate Politics (Cambrigde: South End Press, 2000), h. 7 dan 19. Dengan semboyan “Feminists are made, not born.” Selain itu, Hooks juga berasumsi bahwa diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin senantiasa tersosialisasikan melalui orang tua dan lingkungan, maka atas dasar itu feminis harus segera melakukan tantangan dan perubahan.
[6] Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis (Cet. II; Ponorogo: CIOS, 2010), h. 111-117., feminisme seringkali dibenturkan dengan doktrin keagamaan, yang ketika masuk ke dalam wacana pemikiran Islam justru menghasilkan “ijtihad” yang tidak merujuk pada pendapat ulama-ulama sebelumnya.
[7] Lihat Valerie Bryson, Feminist Political Theory: an Introduction (Ed. II; New York: Palgrave Macmillan, 2003), h. 186-187. Bryson mewanti-wanti dengan ungkapan “…fearing that in a patriarchal society this will always be used to the detriment of women.” Menurutnya, masyarakat kini masih didominasi budaya patriarki dan acap kali menjadikan konsep nature sebagai pembenaran atas “penindasan” perempuan.
[8] Lihat Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 93. Menurutnya, mengerti konsep gender dan dua konsep tersebut adalah faktor penting untuk membuktikan apakah kesetaraan gender 50/50 dapat terwujud atau tidak. Lihat juga “Feminisme dan Teori Kemarahan” dalam Henri Shalahuddin dkk., Indahnya Keserasian Gender dalam Islam (Jakarta: KMKI, 2012), h. 65-67.
[9] Lihat “Gender” dalam Merriam-Webster 11th Collegiate Dictionary (Ver. 3.0; Merriam-Webster, Inc., 2003) [DVD] Secara etimologi gender berasal dari Bahasa Inggris Abad Pertengahan “gendre,” dari Bahasa Anglo-French “genre,” “gendre,” dan dari Bahasa Latin “gener-,” “genus,” mulai dipergunakan sejak abad XIV dengan makna “The behavioral, cultural, or psychological traits typically associated with one sex.” Bandingkan dengan “Gender” dalam A S Hornby et. al., Oxford Advanced Learner’s Dictionary: International Student’s Edition (Oxford: Oxford University Press, 2010) hlm. 622., yang mengartikannya sebagai “The fact of being male or female, especially when considered with reference to social and cultural differences, not differences in biology.”
[10] Maggie Humm, op. cit., h. 177-178. Meski definisi semacam ini pertama kali dikenalkan oleh Mead pada tahun 1935, namun saat itu belum menjadi isu pokok feminisme. Lihat juga Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies (Cet. III; New York: Morrow, 1963), h. 279-88. Studinya pada tiga suku primitif di New Guinea (Arapesh, Mundugumor, dan Tehambuli) mengarahkannya pada beberapa temuan tentang adanya perbedaan kontras lintas budaya dalam pelabelan maskulinitas atau feminitas dan hal tersebut senantiasa berlanjut ke generasi berikutnya. Ciri, peran, sifat, dan kebiasaan yang dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu di suatu budaya belum tentu berlaku di budaya yang lain, bahkan dalam temuannya sebuah tatanan masyarakat tanpa batasan gender ternyata bisa berlaku. Akhirnya, Mead menyimpulkan bahwa kondisi sosial budaya setempat lebih berperan dibanding faktor biologis dalam membedakan kebiasaan laki-laki dan perempuan. Sayangnya, studi yang dilakukan Mead terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan yang ia temukan, seandainya ia memberi porsi yang sama pada kesamaan antar suku kesimpulan yang dihasilkan pasti akan berbeda. Bandingkan dengan Richard A. Lippa, Gender, Nature, and Nurture (Ed. II; New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc., 2005) h. 54, 79-80, dan 259-260. Meski studinya dipengaruhi oleh asumsi Bem (1987: 309) “…masculinity and femininity do not exist ‘out there’ in the world of objective realities… [they] exist only in the mind of the perceiver.,” dan berargumen bahwa “Gender is not simply a matter of sex differences. It is also a matter of variations within each sex.,” namun tetap mengakui adanya “dogma” global bahwa laki-laki sebaiknya maskulin dan wanita sebaiknya feminim. Perbedaan antara atribut gender bukan berarti salah satunya lebih baik, melainkan lebih pada kesesuaian, yakni atribut gender yang melekat dirasa sebagai yang terbaik untuk masing-masing jenis kelamin.
[11] Judith Butler, Undoing gender (Cet. X; New York & London: Routledge, 2004), h. 1-2., menurutnya kelangsungan gender tidak lepas dari keinginan “desire” yang bisa berbeda tiap individu, menjadi gender tertentu adalah sama dengan melakukan suatu perbuatan, bukan bersifat otomatis atau melalui mekanisme alami. Definisi semacam ini juga ditemukan dalam draft RUU KKG 2012 dalam Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 1 Point 1., meski setelah itu mengalami revisi dan untung saja tetap tidak disahkan, karena kenyataannya definisi semacam ini tidak hanya merusak norma tentang bagaimana menjadi laki-laki atau perempuan, tetapi juga menjadi pembenaran atas transgender dan transsexuality.
[12] Misalnya, dalam Bahasa Indonesia term gender diserap menjadi gender atau jender, namun istilah baru ini belum dikenal dan masih dianggap satu makna dengan seks/jenis kelamin hal serupa juga ditemukan dalam Bahasa India. Dalam bahasa Melayu (Malaysia) kata sex dan gender juga diserap, namun keduanya hanya memiliki satu padanan kata yakni jantina (jantan atau betina), hal serupa juga berlaku dalam bahasa jepang dan Korea. Dalam Bahasa Arab, sex diterjemahkan menjadi الجنس “al-jins,” sedangkan gender diterjemahkan dengan kata turunannya yakni الجنسين “al-jinsain” atau الجنسانية “al-jinséniyyah,” hal serupa juga dilakukan Bahasa China dan Perancis.
[13] Baca Emily Esplen dan Susie Jolly, Gender and Sex: A Sample of Definitions (Brighton: BRIDGE, 2006), h. 2-4.
[14] Lihat Judith Butler, op. cit., h. 6, sejak gender dianggap sebagai konstruksi sosial budaya, maka pilihan untuk menjadi idenditas gender tertentu menentang bawaan jenis kelamin biologis menjadi isu yang sangat penting bagi kajian feminisme.
[15] Lihat Emily Esplen …, op. cit., h. 2.
[16] Lihat Richard A. Lippa, op. cit., h. 117-118., salah satu jargon yang digunakan adalah “Gender is not something we are; rather, it is something we do.”
[17] Lihat “nature” dalam Merriam-Webster, op. cit., berasal dari Bahasa latin “natura” yang berarti “dilahirkan.” Dipergunakan sejak abad ke-14.
[18] Lihat Ratna Megawangi, op. cit., h. 94. Baca juga Richard A. Lippa, op. cit., 138-140 dan 145-154., kesimpulan tersebut berdasar eksperimen pada hewan dan terutama pada penelitian tentang karakter genetik dan kinerja hormonal, baik sebelum maupun sesudah lahir.
[19] Ibid., h. 101., caranya adalah dengan menyadarkan masing-masing jenis kelamin agar menganggap sifat yang melekat padanya sebagai anugerah dan keagungan, tanpa menganggap maskulin atau feminim lebih tinggi atau lebih rendah dibanding yang lain.
[20] Lihat Gregory A. Kimble “Evolution of the Nature-Nurture Issue in the History of Psychology” dalam Robert Plomin and Gerald E. McClearn (ed.), Nature, nurture, and psychology (Washington DC: American Psychological Association, 1993), h. 5, dalam teori evolusinya, Darwin (1859) menyebutkan adanya tiga faktor yang memungkinkan terjadinya hal tersebut: Pertama, hereditas/keturunan (keturunan/anak selalu mirip orang tuanya). Kedua, variasi (meski cenderung ada persamaan, namun ada perbedaan pada keturunan/anak). Dan ketiga, seleksi alam (hanya varian/jenis terbaik/yang mampu menyesuaikan dengan alam yang akan bertahan, yang tidak mampu menyesuaikan diri akan punah dalam persaingan eksistensi. Lihat juga Stephanie A. Shields dan Kristen M. Eyssell “History of the Study of Gender Psychology” dalam Judith Worell (ed.), Encyclopedia of Women and Gender: Sex Similarities and Differences and the Impact of Society on Gender (California: Academic Press, 2002), h. 94, teori evolusi Darwin kemudian dikembangkan oleh Degler yang mengkaji secara aplikatif teori Darwin dengan mengutip dari Thomas (1897). Selain itu, juga dipopulerkan oleh Hardaker (1882), Cattel (1909), dan Thordike (1914). Lihat juga ibid., hlm. 95-99. Teori nature tidak disenangi oleh feminis dan pegiat kesetaraan gender karena condong mendiskreditkan perempuan dan kebetulan banyak penggagasnya adalah laki-laki. Boas (1911) mengambil jalan tengah dengan mengakui teori nature, namun berpendapat bahwa perbedaan biologis yang ada tidak membuat perempuan menjadi lebih inferior dibanding laki-laki.
[21] Ibid., studi Mendel (1866) mengenai genetika melengkapi detail dalam teori Darwin yang pertama. Teori Mendel menjelaskan perbedaan fenotip (ciri yang nampak) dan genotip (ciri bawaan gen) sebagai sesuatu yang bisa diperhitungkan.
[22] Lihat juga Carol Gilligan, In a different voice: Psychological Theory and Women’s Development (cet. 38; Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press, 2003), yang memuat sanggahan terhadap Lever (1976), Piaget (1968), Kohlberg (1969) atas wacana penentuan kematangan kepribadian berdasar standar maskulin yang berimbas pada krisis identitas dan moral yang terjadi di kalangan perempuan, terbukti dengan maraknya aborsi dan merebaknya kultur androgini (perempuan meniru laki-laki)
[23] Ibid., h. 98., pada tahun 1960-an Rossi menentang adanya perbedaan peran antar jenis kelamin, namun sejak 1976 berbalik mendukung konsep nature dengan ide pokok tentang keragaman antarseks sebagai faktor perbedaan peran gender dan tidak tergantikannya figur ibu sebagai pengasuh.
[24] Ibid., h. 181-183 dan 191-192., konsep ini berkembang sebagai respon atas “penghianatan” feminisme liberal dan sosialis serta menyeruhkan perempuan agar bangkit melestarikan kualitas feminim. Salah satu tokohnya adalah Vandana Shiva (1991) dengan konsep equality in diversity.
[25] Ibid., h. 225., setara di sini bukan berarti sama secara matematis, tetapi adil sesuai konteks.
[26] Lihat “nurture” dalam Merriam-Webster, op. cit., berasal dari Bahasa Inggris Abad Pertengahan “norture,” “nurture,” dari Bahasa Anglo-French “nureture,” dan dari Bahasa Latin “nutritura,” mulai dipergunakan sejak abad XIV. Selain itu juga dimaknai sebagi kegiatan memberi makan, terutama menyusui.
[27] Lihat Richard A. Lippa, op. cit., h. 187-188. Kesimpulannya “The research summarized here shows that social and environmental factors have a powerful influence on many of the phenomena described by the term gender.” Hasil dari banyak riset yang dilakukan olehnya dan juga peneliti-peneliti lain mengungkap kuatnya pengaruh faktor sosial dan lingkungan dalam fenomena tentang gender. Namun, metodologi ilmu humaniora yag berupa sosiometri dan pengambilan sampel responden yang dipakai masih bisa diragukan kebenarannya.
[28] Ibid., h. 157-172., stereotip timbul di antaranya karena pengaruh orang tua, teman sebaya, sekolah, media massa, bahasa, dan lain-lain. Di antara contoh dari pembentukan stereotip adalah penamaan anak dengan nama yang lazim sesuai jenis kelaminnya, pemilihan baju, mainan, dan lain sebagainya.
[29] Lihat Margaret Mead, op. cit., Mead (1935) sendiri yang dianggap sebagai peletak dasar teori nurture masih menyebutnya sebagai faktor budaya (culture).
[30] Lihat Judith Butler, op.cit., h. 2., menurutnya setiap orang punya hasrat untuk menjadi gender sesuai keinginannya, tetapi standar yang dianggap alami “memaksa” mereka menjadi gender sesuai jenis kelaminnya.
[31] Ibid., dalam penelitiannya, Mead (1935) menemukan 3 suku di New Guinea yang memiliki perbedaan sangat kontras dalam kebiasaan serta pembagian peran berdasar gender. Itulah yang menjadi landasan teorinya.
[32] Pengembangan radikal dari konsep ini adalah pembenaran atas transgender dan transsexual, jadi bukan hanya pertukaran sifat maskulin dan feminim lintas gender, bahkan pertukaran untuk antar jenis kelamin pun dimungkinkan dan harus dianggap wajar. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi bedah dan terapi hormonal, untuk menjadi lelaki atau perempuan sekarang adalah berdasar keinginan dan pilihan. Lihat “Of Gender and Genitals: The Use and Abuse of the Modern Intersexual.” Anne Fausto Sterling, Sexing the Body: gender politics and the construction of sexuality (New York: Basic Books, 2000) h. 77.
[33] Lihat Judith Butler, op.cit., h. 2, perbedaan dan pembedaan yang ada harus dihapus, karena itu adalah satu-satunya cara agar menjadi gender tertentu menjadi terserah keinginan dan bukan keterpaksaan sosial. Hala senada juga diungkapkan Mead (1949) “that only fairly complicated social arrangements can break it down entirely.” Lihat Judith Worell., op. cit., h. 234.
[34] Gender inequality; lawan dari kesetaraan gender, berupa pembedaan atau ketidakadilan berdasar gender. Misalnya, dari 560 anggota DPR RI hanya ada 102 anggota perempuan atau sekitar 18.2% (Inter-Parliamentary Union and UN Women: 2012), hal ini tidak adil menurut feminis dan pegiat kesetaraan gender, karena tolak ukur yang mereka gunakan adalah kesamaan secara kuantitatif.
[35] Gender bias; memberikan atau menghasilkan penilaian yang menyimpang atas gender tertentu, biasanya cenderung negatif dan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Lihat Sugi hastuti dan Siti Hariti Sastriyani, Glosarium Seks dan Gender (Yogyakarta: ÇarasvatiBooks, 2007), h. 26. Hal semacam ini banyak ditemukan dalam Bibel, salah satunya adalah doktrin tentang dosa warisan yang menyebabkan gereja dan umat Kristen dulu merendahkan perempuan. Lihat kata pengantar Elizabeth Cady Stanton dalam The Woman’s Bible (New York: European Publishing Company, 1898)
[36] Hegemony, berasal dari bahasa Yunani hēgemonia, asal katanya hēgemēn yang berarti pembimbing atau pemimpin yang secara terminologi bermakna pengaruh dan otoritas yang bersifat superior. Patriarch, berasal dari Bahasa Inggris Abad Pertengahan patriark, bahasa Perancis Kuno patriarche, dab Bahasa Latin patriarcha, diserap dari Bahasa Yunani patriarchēs, yang berarti nasab, keturunan, klan, dan keluarga yang secara terminologi bermakna sekumpulan yang diatur laki-laki sebagai pemimpinnya.
[37] Sexism, penindasan dan diskriminasi berdasar jenis kelamin. Misalnya adalah tidak adanya hak bagi wanita untuk memilih dalam pemilihan umum di Amerika Serikat, kebijakan tersebut baru dihapus tahun 1920 setelah adanya gerakan yang dipimpin oleh Susan B. Anthony dan Elizabeth Cady Stanton. Lihat Kathleen Kuiper, The 100 most Influential Women of All Time (New York: Britannica Educational Publishing, 2010)
[38] Lihat “miso-” dalam Merriam-Webster, op.cit., dari bahasa yunani misein yang berarti benci. Misoginy, kebencian terhadap perempuan. Antonym dari kata ini adalah misandry, kebencian terhadap laki-laki. untuk contoh, lihat Waryono dalam Hamim Ilyas, dkk., Perempuan Tertindas?; Kajian Hadis-hadis “Misoginis” (Cet. IV; Yogyakarta: eLSAQ, 2009), 70-71., hadits-hadits tentang perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hukum fiqih seperti dalam aqiqah, najis air kencing balita, aurat, dan lain sebagainya dianggap sebagai hadits misoginis.
[39] Judith Butler, op.cit., h. 2.
[40] Lihat “Beauvoir, Simone De (1908-1986)” dalam Catherine Villanueva Gardner, Historical dictionary of feminist philosophy (Scarecrow Press, Inc.: Maryland, 2006), hlm. 28-31., Beauvoir (1949) bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali melontarkan analisa atas penindasan berbasis gender, efek yang diakibatkan, serta penyebabnya. Klaimnya, tidak ada seorangpun yang terlahir sebagai seorang wanita, melainkan dibentuk oleh budaya sebagai gambar negatif [dari laki-laki], sebagai sesuatu “yang lain” yang lebih rendah atas sifat maskulin [yang tidak dimilikinya]. Konstruksi semacam ini lah yang menurutnya menjadi penyebab [baik sadar maupun tidak] atas penindasan perempuan. Selain itu, filsafat eksistesialis yang dianutnya dengan kebebasan manusia sebagai gagasan utama juga banyak mempengaruhi gerakan feminisme.
[41] Dalam psychosexual stages/phases Freud menyatakan bahwa seseorang menyadari tentang jenis kelaminnya pada antara umur 3-5 tahun. Beberapa argumen dalam teori Freud menjadi landasan dalam teori nurture, namun di sisi lain juga mendapat kritik hebat dari para feminis karena teori pe*** envy dan wacana tentang subordinasi sifat feminim atas maskulin; “Women held a status which not only was essentially masculinized, but also considered to be inferior to that of men.” Lihat Judith Worell., op. cit., h. 526 dan 597.
[42] Ann Oakley dan bukunya Sex, Gender and Society (1972) dianggap sebagai peletak konsep nurture dalam diskursus gender. Lihat “gender” dalam Jane Pilcher and Imelda Whelehan, Fifty Key Concepts in Gender Studies (London, California, & New Delhi: SAGE Publications, 2004), h. 56-59.
[43] Lihat “gender” dalam Maggie Humm, op. cit., h. 177-180.
[44] Bernice Lott dan Diane Maluso “Gender Development: Social Learning” dalam Judith Worell (ed.), op. cit., h. 537-550, terutama dalam point IV, The Reconstruction of Gender.
[45] Bandingkan dengan konsep nature dan nurture dalam ranah psikologi. Perdebatan antara dua teori yang sudah ada bahkan sebelum psikologi sendiri, ternyata terhenti–meski mungkin hanya untuk sementara–dengan sebuah konsensus dan dua varian rumus, “Of the many answers that are available, the one that seems best to embrace the diversity of psychology comes from behavioral genetics.” Lihat Gregory A. Kimble, op.cit., hlm. 21-22.
[46] Judith Butler, op.cit., h. 92.
[47] Sebagaimana dikutip Megawangi dari Kaminer (1993: 59), kepercayaan pada stereotip gender yang bukan karena faktor kodrati (alam), is at least ten years out of date. Lihat Ratna Megawangi, op.cit., hlm. 102. Lihat juga Carol Gillgan, op. cit., 124-127., menurutnya konsep nurture memicu nihilisme moral perempuan, salah satu indikasi yang dengan tegas dikritiknya adalah berkurangnya rasa tanggung jawab dan juga ikatannya [dengan ikatan-ikatan sosial dan juga individu lain, terutama dengan suami dan anak], perannya sebagai istri dan ibu ingin ditinggalkan sehingga hubungan tanpa pernikahan dan aborsi yang dipilih.
[48] Jennifer Baumgardner and Amy Richards “Manifesta: Young Women, Feminism, and the Future (United Status. 2000)” dalam Estelle B. Freedman (ed.), The Essentsial Feminist Reader, (New York: The Modern Library, 2007), h. 426., yang membedakan dua kubu dalam feminis ini hanya pada pemaknaan equality (kesetaraan)
[49] Misalnya di Indonesia, dengan dalih emansipasi wanita pengarusutmaan gender tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi sudah menjadi kajian akademis dan dipolitisasi, bahkan diajukan sebagai rancangan undang-undang.
[50] Syamsuddin Arif, Orientalis & Diabolisme Pemikiran (Depok: Gema Insani Press, 2008), h. 103-115.
[51] Misalnya Muhammad Royyan Firdaus “HAM untuk LGBTI” dalam http://islamlib.com/id/artikel/ham-untuk-lgbti.htm, diakses pada tanggal 9 Desember 2012., yang membagi perilaku homoseks dalam dua kategori, yakni sebagai konstruksi budaya dan yang bersifat “given” yang merupakan hak mutlak Tuhan. Sebagaimana laporan yang ia kutip tentang potensi setiap laki-laki untuk “menjadi” perempuan tergantung kadar sel kromoson Y dalam sex chromosomes, akhirnya disimpulkan bahwa penyimpangan orientasi seksual adalah hal yang alami.
[52] Lihat “culture” dalam Merriam-Webster, op.cit. Budaya biasanya berasal dari apa yang dianggap bisa mewakili keseluruhan bentuk dari kebiasaan manusia berupa pemikiran, perkataan, perbuatan, dan artefak serta bergantung pada kapasitasnya dalam belajar dan menyerap pengetahuan dari alam, hal tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya melalui alat-alat, bahasa, dan sistem. Perbedaan kapasitas manusia dalam belajar dan menyerap pengetahuan mengakibatkan perbedaan antar budaya.
[53] Tugas manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi dengan hak untuk mengelola dan kewajiban untuk memelihara alam tidak bisa dipisahkan dari tugasnya sebagai Abdullah berupa tanggung jawab kepada Allah atas hukum-hukum yang diturunkan-Nya. Lihat Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami: Studi tentang Elemen Psikologi dari al-Quran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 355.
[54] Untuk contoh aspek biologis yang bersifat kodrati yang turut mempengaruhi konstruk sosial lihat “estrogen,” “prolactin,” dan “mammary gland” dalam Theodore Pappas et al., Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite (Ed. 16; Encyclopaedia Britannica, Inc., 2012) [DVD], dalam tubuh manusia terdapat hormon estrogen yang mempengaruhi perbedaan struktur tubuh laki-laki dan perempuan, hormon ini menstimulus hormon prolactin agar berproses bersama hormon-hormon lain untuk memproduksi ASI dalam kelenjar susu (mammary glands), kerja hormonal ini turut mempengaruhi bentuk fisik dan kondisi psikis ibu. Karena hal ini bersifat umum akhirnya timbullah konstruk sosial yang melazimkan seorang ibu menyusui anaknya. Proses serupa juga terjadi pada hewan-hewan mamalia.
[55] Lihat Hamid Fahmy Zarkasyi, op. cit., h. 111. Lihat juga “Ketentuan Umum RUU Gender Problematik!” dalam Henri Shalahuddin dkk., op. cit., h. 10.
[56] Orientasi seksual yang lebih terhormat, yang dibatasi ikatan pernikahan antara lelaki dan perempuan dengan bertujuan melestarikan keturunan dianggap sebagai Sex-negative cultures, lihat Patricia Whelehan “Cross-Cultural Sexual Practices” dalam Judith Worell., op. cit., h. 291-302. Selain itu, pelarangan terhadap perzinaan dan hubungan sesama jenis justru dianggap sebagai homophobia dan pelanggaran HAM.
[57] Metodologi yang dipergunakan seperti sosiometri, pengambilan sampel, dan studi kasus dibuat karena mustahil seorang peneliti meneliti seluruh orang di dunia. Apabila ada beberapa kasus atau banyak responden mengindikasikan kecondongan untuk menyimpang secara seksual, seilmiah apapun penelitian tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menggeneralisirnya sebagai sebuah kelaziman.
[58] Seperti pernikahan, rumah tangga, dan lain sebagainya.
[59] Seperti tentang Shalat Jum’at, batasan aurat, hak waris, kesaksian, dan lain sebagainya.
[60] Berbeda dengan feminis Barat yang memisahkan agama dari feminisme, sebaliknya feminis muslim seringkali menjadikan dalil-dalil agama yang telah dirubah sebagai pembenaran atas pemikiran dan perbuatannya.
[61] Misalnya Amina Wadud, Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective (New York: Oxford University Press, Inc., 1999), h. 2, “…what concerns me most about ‘traditional’ tafasiris that they were exclusively written by males. This means that men and men’s experiences were included and women and women’s experiences were either excluded or interpreted through the male vision, perspective, desire, or needs of woman.”
[62] Hamid Fahmy Zarkasyi, op. cit., h. 112-117.