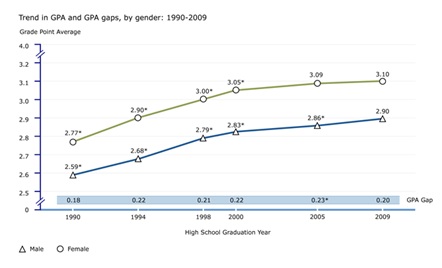Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)
Oleh: Ayub*
Pendahuluan
Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat Barat. Cikal bakal lahirnya gerakan ini adalah pembentukan Gay Liberation Front (GLF) di London tahun 1970.[1] Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di Stonewall.[2] Kampanye LGBT berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat umum bahwa perilaku mereka bukan penyimpangan sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain.
Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme.[3] Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi pernikahan sesama jenis. Peneliti INSISTS, Rita Soebagio menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang digodok di parlemen hingga tahun 2014 memiliki celah tersebut.[4] Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia. Contoh yang mencolok dan cukup terkenal adalah publikasi ilmiah Fakultas Syari’ah IAIN Wali Songo dalam jurnal Justisia edisi 25, Th. XI 2004. Akademisi muslim liberal yang menulis di dalam jurnal tersebut secara tegas mendukung semua jenis ekspresi seksual dan mengajak masyarakat untuk setuju terhadap legalisasi perkawinan sejenis dan pengakuan untuk para penyimpang seksual lainnya.[5]
Masalah teologis selama ini memang menjadi titik penting di dalam perdebatan homoseksualitas dan LGBT secara umum. Perlawanan masyarakat yang religius—khususnya Islam—adalah tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum LGBT. Colin Spencer mencatat bahwa negara-negara Islam/mayoritas Muslim masih menjadi tempat yang tidak mengakomodasi hak seksual homoseks dan LGBT.[6] Karena itu,Karena itu, wajar apabila upaya pembongkaran terhadap ajaran agama yang dianggap heteronormatif giat dilakukan oleh akademisi muslim pendukung LGBT di negara mayoritas muslim seperti Indonesia.
Selain melakukan kampanye dengan dalih teologis, penganjur legalitas LGBT juga menggunakan dalih psikologi. Dahulu di dalam DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Desorder), homoseksulitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa, akhirnya setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1974 APA (American Psychiatric Association) menghapus homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dideklasifikasi olah APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.[7]
Berdasarkan penjelasan di atas, maka fenomena LGBT perlu mendapatkan kajian serius dari umat Islam. Makalah ini akan membahas persoalan LGBT dari perspektif psikologis dan teologis dengan membatasi bahasan pada persoalan homoseksualitas. Istilah homoseksualitas di dalam makalah ini dapat dilihat di dalam dua aspek, pertama sebagai sebuah rasa ketertarikan secara seksual (sexual orientation) kepada sesama jenis, baik laki-laki kepada laki-laki maupun perempuan kepada sesamanya. Istilah ini juga bisa digunakan untuk merujuk kepada kegiatan seksual (sexual acts or behavior) yang dilampiaskan kepada sesama jenis.[8] Karena itu, istilah ini mencakup gay dan lesbian.

Homoseksualitas Dalam Diskursus Psikologi
Perkembangan diskursus homoseksualitas di dalam psikologi sangat dipengaruhi oleh basis epistemologi ilmu ini. Karena itu, perlu untuk membahasnya secara ringkas terlebih dahulu. Psikologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu tentang jiwa. Secara istilah psikologi adalah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia. Psikologi modern dinyatakan independen ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig tahun 1873.[9] Suatu ilmu tentu akan dipengaruhi oleh worldview peradaban tempat ia lahir, termasuk psikologi[10]. Pengaruh worldview Barat di dalam landasan epistemologi psikologi akan akan nampak bila melihat lanskap intelektual kelahirannya. Ilmu ini lahir pada kembangkitan intelektual Barat yang kedua ditandai dengan berkembangnya epistemologi empirisisme.[11]Paradigma empirisisme inilah yang selanjutnya menyulut perkembangan psikologi modern dalam memandang jiwa manusia.
Dalam sejarahnya ada beberapa paradigma yang berkembang di dalam psikologi, tapi semuanya masih di atas koridor empirisisme. Hal itu membuatnya tetap menolak mengaitkan sesuatu yang spritual dengan jiwa manusia. Sebelum Wundt pemikiran psikologi disamapaikan antara lain oleh John Locke (1623 – 1704) dan James Mill (1773-1836). Mereka mengkaji jiwa dengan prinsip-prinsip kausalitas dan melahirkan aliran Association. Selanjutnya psikologi menjadi sangat dipengaruhi oleh metode eksperimental fisika, sehingga lahirlah aliran Strukturalisme. Aliran ini memandang jiwa sebagai bagian-bagian yang berhubungan dalam satu sistem. Tokohnya antara lain adalah William Wundt (1832-1920). Berikutnya muncul aliran Fungsionalisme yang mengkaji jiwa sebagai daya hidup dinamis dan pragmatis yang mendorong aktivitas tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Tokoh-tokohnya antara lain John Dewey (1859 – 1952). Usaha untuk memadukan kedua aliran ini adalah teori Gestalt. Setelah itu muncul Sigmund Freud (1856 – 1939) dengan teori psikoanalisis yang mendalami alam bawah sadar melalui konsep id, ego, dan superego. Aliran ini dianggap terlalu subjektif sehingga muncul Behaviorisme dengan tokoh antara lain B.F. Skinner (1904 – 1990). Behaviorisme dianggap puncak dari psikologi empiris yang melihat jiwa secara positivisik dan mekanis.[12]
Perkembangan psikologi pasca Behaviorisme masih tetap empiris. Reaksi terhadap positivisme reduksionis sesungguhnya terlihat pada psikologi Humanis yang dikembangkan antara lain oleh Abraham Maslow, begitupula psikologi transpersonal. Namun demikian keduanya tidak luput dari kritikan dalam cara mereka menggambarakan manusia. Psikologi Humanistik memang memuliakan manusia lebih dari determinisme biologis Psikoanalisis atau mekanis Behaviorisme. Tapi psikologi Humanis dinilai sangat optimistik dan bahkan terlampau optimistik terhadap upaya pengembangan sumber daya manusia, sehingga manusia dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan play-God (peran Tuhan).[13] Begitu pula psikologi Transpersonal, konsep spritual yang disebut oleh pelopornya seperti Frakl adalah neotic yang dimaknai sebagai sumber aspirasi manusia untuk hidup bermakna, dan sumber dari kualitas-kualitas insani.[14] Pemaknaan ini masih dalam koridor empirisisme dan menolak kaitan jiwa dengan sesuatu yang metafisik.
Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa ilmu psikologi, dengan semua aliran arus utamanya dibangun di atas epistemologi Barat yang sekuler.[15] Dampaknya adalah penolakan terhadap jiwa spritual sehingga terjadi reduksi terhadap konsep jiwa. Hilangnya jiwa yang spritual ini diakui oleh Otto Rank, salah satu murid terbaik Freud penelitian
Prescientific and nonscientific psychology has always been the true psychological dicipline and the source of all psychologies including those that study the soul scientifically. Scientific psychology which seems to know very little about the soul claims to seek the truth about it, but reject the contribution of ancient beliefs…to explain it. It performs experiment which seem always to prove that the soul does not exist.[16]
Otto Rank melihat psikologi saintifik gagal mengenali jiwa karena menolak interpretasi religius dan spritual. Metode eksperimen yang dilakukan oleh psikologi modern justru mengarahkannya untuk semakin menjauhi konsep jiwa spiritual tersebut. Pada saatnya sikap ini berdampak pada diskursus homoseksualitas dimana pandangan-pandangan terhadap fenomena ini yang berasal dari pandangan agama akan dikesampingkan.
Epistemologi sekuler tidak mengakui wahyu sebagai sumber ilmu, sehingga semuanya bergantung kepada indra dan nalar yang penemuannya terus berubah.[17] Proses ekplorasi nalar dan indra tersebut bersifat resiprokal dengan nilai-nilai di dalam tatanan sekuler yang ever shifthing, selalu berubah. Di dalam sekulerisme tidak ditemukan pegangan yang tetap sebagai tolak ukur kebenaran.[18] Selain itu sekulerisme bersifat materialistik, menolak klaim kebenaran yang berdasarkan otoritas metafisis. Watak epistemologi sekuler ini pada gilirannya berpengaruh di dalam kesimpulan-kesimpulan para psikolog, termasuk dalam diskursus homoseksualitas.
Salah satu bagian psikologi yang rentan terhadap bias sekulerisme barat adalah penentuan abnormalitas. Bias sangat mungkin terjadi sebab kriteria abnormalitas cukup relatif.[19] Bias yang terdapat di dalam penentuan abnormalitas ini telah disadari oleh para psikolog. Secara cukup radikal Thomas S. Szasz, menggugat konsep abnormalitas atau gangguan mental. Baginya, gangguan mental hanya mitos. Masalah sebenarnya adalah problem individual, sosial dan etika dalam masyarakat.[20] Kritik ini lahir dari kesadaran bahwa konsep ini sangat dipengaruhi oleh konstruk kultural. Sifat value-laden psikologi terus berpengaruh dalam evolusi konsep abnormalitas. Setelah mencatat evolusi kriteria gangguan mental atau abnormalitas temasuk pada DSM, Gerrig, Zimbardo, Campbell, Cumming, dan Wilkes menegaskan bahwa semua itu terjadi bukan hanya karena perubahan opini para psikolog, tapi juga sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai yang terjadi secara konstan dalam masyarakat Barat.[21]
Secara umum Getzfeld menyebutkan adanya tiga perspektif yang digunakan sebagai kriteria dalam menentukan abnormalitas penelitian sudut pandang statistik, sudut pandang norma-norma umum dan sudut pandang maladaptive.[22] Sudut pandang statistik menggunakan hitungan matermatis yang ditampilkan di dalam kurva. Orang-orang normal berada di tengah grafik sedangkan persebaran abnormal berada di pinggiran kurva. Sudut pandang norma berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan sudut pandang maladaptive adalah ketidakmampuan seseorang untuk beradaptasi pada situasi tertentu sebab keadaan jiwanya. Ketiga sudut pandang ini memang sangat memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan standar abnormalitas bila di dalam masyarakat terjadi perubahan nilai.
Menurut Malik Badri, ketiga kriteria ini memiliki banyak kekurangan. Sudut pandang statistik misalnya berpotensi menempatkan seorang yang jenius dan mempunyai kestabilan mental pada posisi yang sama dengan seorang neurotik. Sudut pandang norma jelas bermasalah seiring semakin relatifnya nilai yang menjadi basis norma khususnya pada masyarakat Barat. Begitu pula dengan ketidak mampuan beradaptasi. Seorang muslim yang memegang teguh ajaran agamanya misalnya, akan dianggap tidak normal bila ia merasa tertekan di tengah masyarakat yang serba permisif.[23] Diakhir analisisnya, Malik Badri menyebutkan kekurangan fundamental kriteria ini penelitian
Jelas bahwa kriteria yang ditentukan oleh psikologi Barat terhadap individu yang mempunyai penyesuaian diri yang baik, tidak dikembangkan berdasarkan penelitian empiris yang ilmiah, namun lebih dilandasi konsep kultural. Konsep yang pada dasarnya berasal dari Barat, atau tradisi-tradisi masyarakat modern yang materialistis.[24]
Malik Badri menekankan bahwa posisi abnormalitas dalam psikologi Barat memang banyak pada keadaan maladaptive. Prinsip ini juga tertuang di dalam DSM yakni inflexible and maladaptive traits that cause significant functional impairment or subjective distress.[25]Dalam konteks homosekualitas, kriteria ini sangat menentukan. Seksualitas abnormal disebutkan sebagai perilaku seksual yang dapat menyesuaikan diri, bukan hanya dengan tuntutan masyarakat tapi juga kebutuhan diri sendiri dalam hal mencapai kebahagiaan.[26] Dari pemaparan ini, terlihat bahwa perubahan nilai di dalam masyarakat sangat mungkin membimbing pada perubahan paradigma tentang homoseksualitas. Akibatnya, terjadi perubahan arah paradigma dalam meneliti homoseksualitas, sebagaimana akan dijelaskan pada uraian berikut.
- Evolusi Diagnosis Homoseksual
Sejak awal, penelitian para psikolog terhadap homoseksualitas telah menggambarkan perubahan yang terjadi pada peradaban Barat. Ketika masyarakat Barat masih didominasi oleh Gereja, homoseksualitas dipandang sebagai sebuah dosa[27]. Ketika terjadi pertentangan antara otoritas Gereja dan Raja Henry VIII.Raja Inggris ini mengintegrasikan larangan homoseksual ke dalam hukum sekuler untuk menandingi kekuasaan Paus.[28] Maka homoseksual pun berubah menjadi pelanggaran hukum dan penyimpangan sosial. Gelombang revolusi sains mendorong para peneliti untuk mengamati homoseksual dari kaca mata ilmu pengetahuan, dalam hal ini psikologi. Penelitian-penelitian itu bermula pada abad ke-19, sebagai upaya untuk mencari penjelasan ilmiah yang lepas dari kontrol agama atas setiap fenomena. Penelitian tersebut meskipun dianggap telah membentuk citra homoseksual sebagai sebuah penyimpangan mental, juga memiliki dampak baik bagi kaum homoseksual. Temuan para peneliti bahwa kaum homoseks adalah “orang-orang sakit” menjadikan status kesalahan mereka lebih ringan di mata hukum.[29]
Ahli pertama yang diketahui meneliti homoseksualitas secara khusus adalah seorang seksolog berkebangsaan Jerman bernama Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895). Sebagai seorang ahli hukum yang juga gay, Ulrichs mengarahkan penelitiannya untuk melawan kriminalisasi terhadap tindakan sodomi di dalam hukum Jerman. Argumennya adalah bahwa homoseksualitas adalah pengaruh faktor biologis.[30] Ia memperkenalkan istilah urning dan urnining untuk menggambarkan seseorang yang memiliki “jiwa” seksual yang berbeda dari kondisi biologisnya. Rekan seperjuangan Ulrich bernama Karl Maria Kertbeny (1824-1882) memperkenalkan istilah homosexuality pertama kali untuk menggambarkan hubungan sesama jenis.[31] Bila dilihat dari konteks sosiopolitik, kemunculan istilah “homosexual” sangat dipengaruhi perjuangan Kertbeny mempertahankan posisi liberalisme Jerman di depan hegemoni Prusia.[32] Meskipun istilah ini kemudian diambil alih oleh dunia medis dan psikologi.
Kepeloporan kedua tokoh ini memancing penelitian-penelitian selanjutnya tentang homoseksual. Salah seorang ahli yang terpengaruh oleh Ulrich adalah Karl Westphal (1833-1890). Pada tahun 1869, ia mempublikasikan hasil risetnya tentang para laki-laki yang memiliki sifat feminin serta perempuan yang bersifat seperti laki-laki dan memiliki rasa tertarik kepada sesama jenis. Ia memperkenalkan istilah “contrary sexual feeling”[33] Temuan Westphal ini mulai memberikan basis ilimiah bagi argumen bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang berbeda dari keadaan seksual normal. Istilah yang ditemukan Westphal tersebut diadopsi oleh Arrigo Tamassia (1878) dan diperkenalkan di Italia sebagai “inversione dell istinto sessuale” yang artinya insting seksual terbalik.[34] Hal yang sama dilakukan oleh psikolog dan neurolog ternama asal Prancis, Jean Martin Charcot (1825-1993), ia mempopulerkan temuan tersebut di negaranya. Charcot memasukan homoseksualitas ke dalam kelompok sexual perversions, penyimpangan-penyimpangan seksual dan termasuk gangguan jiwa. Ia menganggap homoseksual sebagai “degrading consequences of a weakening of morals in a vitited society.”[35].
Setelah kepeloporan tokoh-tokoh ini, penelitian dengan paradigma homoseksualitas sebagai sebuah penyimpangan terus berlanjut. Peneliti yang dianggap berperan menegaskan status kecacatan homoseksualitas adalah Richard von Krafft-Ebing (1840-1902). Penelitiannya tentang homoseksualitas tertuang di dalam bukunya Psychopathia Sexualis with Especial Reference to the Antipathic Sexual Instinct: A Medico-Forensic Study (1886).[36] Buku ini adalah sebuah eksiklopedia tentang kelainan, kecacatan, serta penyimpangan seksual yang ditemukan oleh Kraff-Ebing. Seperti kebanyaakan tokoh pada masanya, ia meneliti homoseksualitas dalam perspektif degenerate heredity. Homoseksual dianggap sebagai bentuk kecacatan sebab seharusnya sebuah organisme berjalan kian berkembang, tapi kaum homo justru semakin simpel. Teori ini tentu sangat dipengaruhi oleh Darwinisme.[37] Meskipun telah menegaskan kecacatan kaum homoseksual, menurut Oosterhuis, Kraff-Ebing telah berperan meletakan dengan kokoh pijakan ilmiah homoseksualitas dan terpisah dari konsep immoral. Ia juga menghilangkan anggapan bahwa seorang lelaki menjadi homoseks sebab ia memiliki jiwa feminin atau perempuan berjiwa maskulin.[38]
Peralihan abad XIX ke XX di Eropa ditandai dengan bangkitnya intelektual liberal radikal yang mengembangkan pendekatan permisif terhadap homoseksualitas. Tercatat nama Havelock Ellis (1859-1939), seorang intelektual liberal radikal di Inggris yang menulis buku “Sexual Inversion”, di dalamnya Ellis meyakinkan publik bahwa homoseksual adalah bawaan lahir (congenital) dan pelakunya tidak akan membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.[39] Jejak Ellis diperkuat oleh Magnus Hirschfeld (1868-1935) psikolog dan seksolog asal Jerman. Ia adalah psikolog yang secara terbuka mengakui status homoseksnya. Menurut Hirschfeld, homoseksualitas adalah hal yang alami sebagai “gender ketiga”. Karena itu, hukum yang menghalangi mereka harus dihilangkan dari Jerman. Untuk tujuan tersebut ia mendirikan Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WHK, Scientific-Humanitarian Committee) yang memperjuangkan hak-hak kaum homoseksual dengan basis sains.[40] Namun semua usahanya tersebut terhenti dengan menguatnya kekuatan Nazi di Jerman.[41] Meski demikian, suara para peneliti yang hendak menjadikan homoseksualitas sebagai variasi seks yang normal semakin menguat mengikuti jejak Ellis dan Hirschfeld.
Kajian homoseksualitas memiliki arah baru dengan kehadiran Sigmund Freud (1856–1939) dan pengikutnya dengan pendekatan psikoanalisis. Freud menawarkan pendekatan yang tidak berdasarkan asumsi degeneracy theory yang berkaitan erat dengan Darwinisme. Psikoanalisis yang ia bangun menawarkan pandangan baru tentang homoseksualtias. Di dalam karyanya Three Essays on the Theory of Sexuality Freud menyatakan bahwa manusia pada dasarnya biseksual, apabila ia gagal berkembang karena masalah psiko-seksual, maka ia akan menjadi seorang homoseksual. Ia menjadikan sifat feminin pada para pelacur laki-laki sebagai bukti penguat argumennya tersebut. Meskipun demikian, ia tidak menganggap homoseksualitas sebagai suatu penyakit.[42] Teori Freud ini belakangan ditantang oleh para psikoanalis sendiri. Tiga psikoanalis terkenal yang meyakini bahwa homoseksual adalah penyakit yang harus disembuhkan adalah Sandor Rado (1940), Irving Beiber (1962), dan Charles Socarides. Dari kaca mata psikoanalisis, mereka menjelaskan bahwa homoseksualitas adalah bentuk penyakit mental sehingga perlu ada terapi untuk mengobatinya.[43]
Kajian para psikolog terhadap homoseksualitas dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mengarah pada tiga perubahan besar dalam memandang fenomena homoseksualitas. Pertama, penelitian-penelitian tersebut meskipun memiliki kesimpulan yang beragam, semuanya mempertegas perubahan paradigma masyarakat Barat terhadap homoseksualitas. Fenomena tersebut tidak lagi dilihat dari perspektif teologis tapi murni sebagai objek kajian sains dan medis. Perubahan ini bisa dilihat sebagai cerminan sekulerisasi masyarakat Barat yang kian menguat. Kedua, kajian-kajian tersebut menciptakan kategori orientasi seks bernama homoseksualitas yang sebelumnya tidak diakui. Secara tidak langsung, hal ini memberikan identitas bagi orang-orang yang memiliki kecenderungan seks di luar heteroseksual. Ketiga, stigma negatif yang diarahkan kepada kaum homoseksual perlahan pudar. Kajian-kajian tersebut membuang stigma amoral dan pendosa dari diri kaum homoseks. Citra yang terbentuk kemudian adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sakit dan perlu pengobatan. Ketiga perubahan ini pada gilirannya akan mengantar kepada perubahan yang lebih radikal di pertengahan abad ke-20, yakni normalisasi homoseksualitas. Fenomena ini akan didiskusikan pada bagian selanjutnya.
- Deklasifikasi Homoseksualitas Dari Daftar Gangguan Mental
Tahapan paling menentukan dalam perubahan paradigma psikologi memandang homoseksualitas adalah periode deklasifikasi homoseksualitas dari daftar gangguan mental. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya dianggap memiliki dampak tidak langsung terhadap perubahan ini, tapi proses deklasifikasi tetap meninggalkan kontroversi. Pada bahasan kali ini, terlebih dahulu akan diuraikan kronologi deklasifikasi tersebut serta penelitian-penelitian yang dianggap mendukungnya kemudian akan dipaparkan argumen-argumen pihak yang menentang keputusan tersebut. Agar peristiwa ini bisa lebih dipahami akan dibahas pula mengenai revolusi seksual di Ameria Serikat selama tahun 60-an hingga 70-an yang menjadi konteks perubahan ini.
Setidaknya ada dua ilmuwan yang publikasi ilmiahnya dianggap memiliki peran cukup signifikan dalam mengubah paradigma terhadap homoseksualitas sehingga dianggap normal. Mereka adalah Alfred Kinsey dan Evelyn Hooker. Pada tahun 1948, Kinsey mempublikasikan hasil penelitiannya bersama beberapa kolega di dalam buku berjudul Sexual Behavior in the Human Male, selanjutnya pada tahun 1953 terbit Sexual Behavior in the Human Female. Kinsey menunjukan bahwa seksualitas manusia tidaklah kaku menjadi heteroseksual dan homoseksual. Seseorang tidak bisa disebut murni homoseksual atau heteroseksual. Ia memperkenalkan skala yang disebut Kinsey Scale yang menunjukan gradasi orientasi seksual manusia dengan rasio 0-6 penelitian dari murni homoseksual bergradasi hingga murni heteroseksual.[44] Seorang manusia bisa saja pada satu masa dalam hidupnya adalah homoseksual dan terus berkembang menjadi heteroseksual atau sebaliknya. Ia menegaskan hal tersebut setelah menunjukan skalanya penelitian
Males do not represent two discrete populations, heterosexual and homosexual. The world is not to be divided into sheep and goats. Not all things are black nor all things white. It is a fundamental of taxonomy that nature rarely deals with discrete categories. Only the human mind invents categories and tries to force facts into separated pigeon-holes. The living world is a continum in each and every one of its aspects. The sooner we learn this concerning human sexual behavior, the sooner we shall reach a sound understanding of the realities of sex.[45]
Di dalam penjelasannya di atas, Kinsey memberikan pandangan yang sangat revolusioner tentang seksualitas. Selama ini para peneliti melihat dua kecenderungan tersebut sebagai dua entitas terpisah yang bisa berada di dalam diri seseorang. Kinsey menunjukan bahwa homoseksualitas adalah varian normal dari kehidupan seksual seseorang.
Dengan semangat yang sama, pada tahun 1956 Evelyn Hooker mempublikasikan jurnah yang mendukung normalisasi homoseksualitas. Hooker adalah seorang psikolog peneliti dari UCLA (University of California Lost Angeles). Selama tahun lima puluhan ia melakukan penelitian untuk menguji asumsi umum bahwa seseorang yang tertarik kepada sesama jenis (Same Sex Atraction, SSA) digolongkan sakit secara mental dan bukan pula penyebab sakit mental.[46] Hooker menegaskan bahwa homoseksualitas bukan penyakit juga bukan sebab penyakit mental. Paradigma ini semakin menguat pada tahun 50-an hingga tahun 60-an. Pada tahun-trahun tersebut, tepatnya pada tahun 1951 terbit pula buku Patterns of Sexual Behavior karya dua antropolog Clellan Ford dan Frank Beach. Buku ini membahas seksualitas dalam kajian lintas-budaya. Kedua antropolog ini meneliti seksualitas 190 negara termasuk Amerika Serikat sendiri. Sumbangsih terbesar buku ini adalah mengungkap keberadaan homoseksualitas di dalam berbagai kebudayaan umat manusia. Mereka bahkan meneliti seksualitas primata dan mengklaim menemukan homoseksualitas[47]
Pada tahun 1952, The American Psychiatric Association (APA) menerbitkan DSM untuk pertama kalinya. DSM adalah The Diagnostic and Statistical Manual, Mental Disorders, panduan resmi yang dikeluarkan lembaga tersebut untuk menentukan penyakit mental.[48] Pada seri pertama tersebut homoseksualitas dianggap penyimpangan seksual yang bisa digolongkan sebagai sociopathic personality disorders. Di sini homoseksualitas masih dipandang sebagai sebuah penyakit seksual yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Pada seri kedua yang terbit tahun 1968, homoseksualitas masih tetap dimasukan kategori penyimpangan seksual tapi lebih ringan. [49] Baru pada seri DSM-III yang terbit pada tahun 1973, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Di dalam seri ini homoseksualitas tidak lagi dianggap penyimpangan. Homoseksualitas hanya boleh dianggap gangguan mental bila yang bersangkutan mengalami ketidakpuasan terhadap keadaannya tersebut.[50] Perubahan ini cukup signifikan sebab masalah bukan lagi pada orientasi homoseksualitas tapi lebih pada depresi yang dialami sebab tekanan orang-orang terhadapnya.
Proses deklasifikasi ini tidak bisa dilepaskan dari peran beberapa karya radikal yang dipublikasikan selama kurun 50-an dan 60-an. Karya-karya tersebut menggugat otoritas psikiatri untuk menentukan seseorang “gila” atau tidak. Mereka juga menentang perlakuan “penyembuhan” terhadap pasien psikiatri yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Di antara karya semacam ini yang sangat berpengaruh adalah tulisan filsuf Prancis yang juga seorang gay, Michel Foucault. Pemikrian-pemikiran Foucault di dalam Madness and Civilization yang terbit tahun 1961 berdampak besar dalam delegitimasi otoritas psikiatri dalam menentukan homoseksual sebagai penyakit. Rosario menanggap karya Foucault ini menegaskan bahwa psikiatri adalah upaya untuk meminggirkan mereka yang secara politis tidak diinginkan.[51]Karya lain yang menyumbangkan basis intelektual bagi gerakan anti-psikiatri ini adalah tulsian radikal seorang psikolog bernama Thomas S. Szasz berjudul Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, terbit pertama kali pada tahun 1961. Szasz menegaskan bahwa “penyakit mental” hanyalah mitos, masalah sesungguhnya ada pada cara masyarakat melihat fenomena-fenomena tersebut.[52]
- Kritik Psikolog Terhadap Deklasifikasi Homoseksualitas Dari DSM
Keputusan APA untuk mendeklasifikasi homoseksualitas dari DSM sebagai penyakit mental tidak begitu saja diterima oleh semua kalangan psikolog. Meskipun itu tidak berarti mengakuinya sebagai orientasi yang betul-betul normal. Banyak ahli yang tidak sependapat. Mereka melakukan evaluasi terhadap basis ilmiah keputusan tersebut, yakni temuan-temuan Evelyn Hooker. Krik Cameron dan Paul Cameron dua psikolog dari University of Colorado menguji ulang temuan bersejarah Hooker tersebut, kesimpulan mereka adalah penelitian
Re-examination of her work indicates that Hooker’s study was neither rigorous nor reliable. Among other problems, homosexual subjects were easily identified on test protocolspenelitian her reports of how she obtained her samples were incomplete and contradictorypenelitian and her study generated results supportive of obsession/compulsivity in homosexuals. Thus Hooker’s study was seriously flawed. Moreover, because it was marketed by the APA as central in transforming homosexual activity from an illness/crime into acceptable behavior—yet Hooker did not correct those who mischaracterized her work—APA misrepresentations of Hooker over the past 40 years appear to be more in line with ideology than science.[53]
Perdebatan para ahli pasca deklasifikasi homoseksualitas dari DSM berpusat pada dua poin utama. Pertama sebab (etiologi) homoseksualitas. Aktivis prohomoseksual berpendapat—b erdasarkan penelitian ilmiah terutama oleh LeVay (2010)– bahwa homoseksualitas adalah pengaruh hormon.[54] Dengan demikian, mereka berargumen bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terdeterminasi secara biologis. Argumen ini sesungguhnya adalah penguat kesimpulan Kinsey seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua adalah apakah orientasi seksual bisa berubah atau tidak. APA, sesuai garis kebijakannya yang mendukung homoseksual, telah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada satupun penelitian yang menunjukan bahwa orang-orang homoseksual bisa dirubah orientasi seksualnya melalui terapi. Perdebatan ikutan juga meliputi akibat dari homoseksualitas, menurut aktivis progay, homoseksual tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat.
Bagaimanapun, ada banyak peneliti yang bebas dari kepentingan pro-gay mengemukakan hasil penelitian yang berbeda. Neil N. Whitehead adalah seorang ahli biokimia yang telah meneliti “gay gen” selama empat puluh tahun. Dari hasil studinya tersebut ia mengkritisi pendapat mereka yang menerapkan determinasi biologis bagi orientasi seksual seseorang. Hasil penelitiannya pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 berjudul My genes made me do it!, lalu direvisi dengan penambahan bukti kemudian terbit lagi pada tahun 2013 dengan judul My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence. Bukti terkuat menurut Whitehead adalah penelitian Twin studies. Secara sederhana twin studies adalah studi yang dilakukan terhadap orang-orang homoseksual yang memiliki saudara kembar. Apabila homoseksual adalah pengaruh gen, maka dua orang kembar seharusnya sama-sama berorientasi homoseksual sebab secara gen mereka identik. Namun demikian, studi yang dilakukan secara ekstensif terhadap kembar identik menunjukan bahwa dari sembilan pasangan kembar yang salah satunya homoseksual, hanya satu dari sembilan yang pasangannya juga homoseksual. Menurut Whitehead, hasil studi ini tidak hanya menafikan aspek genetik, tapi semua aspek biologis lainnya.[55]
Argumen Whitehead yang lain adalah menguji hasil temuan Kinsey bahwa 1 dari 10 orang adalah homoseksual (10%). Whitehead membandingkan temuan Kinsey ini dengan hasil survey modern, tahun 2010, dan ternyata hasilnya sangat jauh. Survey dari lembaga independen menunjukan homoseks termasuk biseks hanya 2-3% dari populasi. Sebagai ahli genetika, Whitehead menyimpulkan bahwa jumlah ini menunjukan faktor nurture lebih dominan bila dibandingkan dengan faktor nature, “modern surveys when interpreted show the genetic contribution to SSA is minor and the environmental contribution is much greater”[56] Temuan Whitehead ini hanya mempertegas hasil penelitian Dean Byrd, seorang profesor Psikologi klinis dari University of Utah School of Medicine. Dalam studinya yang dipublikasikan pada tahun 2001, Byrd menyimpulkan bahwa “the main studies on whether homosexuality is caused by biology appear to lack a significant amount of scientific support”.[57] Jadi, bisa disimpulkan bahwa adanya unsur genetika yang membawa “gay gen” pada seseorang tidak otomatis membuatnya menjadi seorang homoseksual. Faktor terpenting adalah pola asuh pada keluarga dan lingkungannya.
Isu perdebatan penting lainnya adalah persoalan perubahan orientasi seksual seseorang dengan kecenderungan homoseksual. APA telah mengklaim bahwa tidak ada satupun bukti keberhasilan terapi semacam itu. Bahkan para ahli yang menyuarakan pendapat berbeda akan mendapatkan tekanan. Salah satunya adalah Robert L. Spitzer, pada tahun 2003, ia mempublikasikan hasil penelitiannya yang menunjukan keberhasilan perubahan orientasi seksual dari 200 orang yang menjalani terapi.[58] Sejak saat itu ia mengalami tekanan dari komunitas gay sehingga mencabut kembali hasil penelitiannya tersebut di dalam sebuah tulisan singkat.[59] Keputusan Spitzer tersebut dikritik oleh sekelompok psikolog, Jerry A. Armelli, Elton L. Moose Anne Paulk, dan James E. Phelan. Menurut mereka keputusan Spitzer untuk menarik hasil penelitiannya hanya karena desakan seorang gay sangat bermasalah. Apalagi gay yang mendatangi rumahnya tersebut bukanlah partisipan di dalam studi Spitzer. Mereka menutup tanggapan tersebut dengan penegasan, “however, one can apologize for the consequences of a study, but one cannot undo the evidentiary data. Well-intended sentiments cannot undo facts.”[60]
Di dalam sebuah laporan yang ditulis khusus untuk membantah klaim APA, tim dari National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH) menunujukan bahwa studi yang dilakukan selama 125 tahun belakangan menunjukan bahwa orientasi seksual seseorang bisa berubah melalui berbagai macam pendekatan. Hanya setelah APA mendeklasifikasi homoseksualitas dari DSM, paradigma terhadap homoseksual pun berubah dari “mengubah orientasi” menjadi membantu klien menerima keadaan homoseksualitas mereka.[61] NARTH adalah lembaga psikolog yang berpusat di Amerika Serikat, beberapa anggotanya adalah psikolog ternama, seperti mantan presiden APA, Nicholas Cummings.
Pada perubahan orientasi seksual, ada beragam faktor yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor yang paling besar dalam perubahan orientasi seksual adalah motivasi orang-orang homoseksual tersebut. Motivasi tersebut akan sangat kuat bila berasal dari dorongan keimanan. Dadang Hawari, psikolog kenamaan dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa seorang homoseks bisa berubah asalkan ia memiliki kemauan yang kuat.[62] Selain itu juga perlu diperhatikan dukungan keluarga, lingkungan, kuat lemahnya kadar homoseksual, dan libido.[63] Faktor iman, ternyata menempati posisi yang penting. Temuan Spitzer tentang 200 orang homoseksual yang berhasil melewati terapi adalah kebanyakan berasal dari kalangan religius, “the vast majority (93%) of the participants reported that religion was “extremely” or “very” important in their lives. “[64] Hasil temuan ini sejalan dengan upaya psikolog berlatar belakang agama yang baik seperti Dadang Hawari untuk melakukan terapi spritual, selain biologis, sosial, dan psikologis.[65]
Bahasan terakhir adalah dampak dari perilaku homoseksualitas. Hingga saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kaum homoseksual yang melakukan hubungan seks sejenis adalah kelompok yang paling rentan teriveksi virus HIV/AIDS. Bahkan ketika penurunan penyebaran virus ini terjadi, pada mereka yang melakukan hubungan seks sejenis justru menunjukan peningkatan. Dalam laporannya, Chris Beyre, seorang profesor kesehatan dari John Hopkins School of Public Health menyimpulkanpenelitian
Our findings show that the high probability of transmission per act through receptive anal intercourse has a central role in explaining the disproportionate disease burden in MSM (Man Sex With Man). HIV can be transmitted through large MSM networks at great speed…. This risk has been present since the syndrome now known as AIDS was first described in previously healthy homosexual men in Los Angeles (CA, USA) in 1981. Despite decades of research and community, medical, and public health efforts, high HIV prevalence and incidence burdens have been reported in MSM throughout the world.[66]
Selain virus HIV yang menyebabkan seseorang menderita AIDS, di antara komunitas homoseksual, penyakit-penyakit menular seksual pun sangat rentan tersebar. Pengidap Gonorrhea di antara kaum homoseksual meningkat sejak 1990, menyusul pula Sipilis, hepatitis C yang didapatkan dari hubungan seksual serta lymphogranuloma venereum yang biasanya menjadi penyakit ikutan bagi pria yang positif HIV.[67]
- Dimensi Politik Deklasifikasi Homoseksualitas
Deklasifikasi homoseksual dari daftar penyakit mental sarat dengan kepentingan politis sehingga menimbulkan kontroversi. Muatan politis ini membuat keputusan tersebut tidak dilihat sebagai sebuah keputusan yang murni berdasarkan sains. Sejumlah peneliti menegaskannya. Ronald Bayer di dalam bukunya Homosexuality and American Psychiatrypenelitian The Politics of Diagnosis yang terbit pada tahun 1987, menegaskanpenelitian
the result was not a conclusion based upon an approximation of the scientific truth as dictated by reason, but was instead an action demanded by the ideological temper of the times[68]
Simpulan serupa dengan Bayer di atas diperkuat oleh Jeffrey Satinover di dalam bukunya yang terbit pada tahun 1997, Homosexuality and the Politics of Truth. Menurut Satinover, unsur tekanan politis sangat kuat dalam proses deklasifikasi homoseksual dari DSM tersebut. Bahkan para pendukung homoseksualitas pun mengakuinya.[69] Selain mereka, ilmuwan-ilmuwan lain yang menyebutkan adanya unsur tekanan politis di dalam deklasifikasi tersebut antara lain Greenberg (1997), Cotton dan Riding (2011)[70] serta Zachar dan Kendler (2012). Peneliti yang terakhir disebut ini menyebutkan bahwa protes aktivis gay serta keberadaan para psikolog yang ternyata homoseksual memiliki pengaruh di dalam peristiwa tersebut.[71] Cotton dan Ridding menggambarkan DSM sebagai a political document— a social construction— shaped more by sociocultural influences than the demands of practicing professionals in the field of mental health.[72]
Kepentingan politik yang disebut di atas adalah gerakan Gay Movement yang merupakan bagian dari revolusi hak-hak sipil. Era 50-an sampai 60-an adalah masa-masa yang penting dalam revolusi budaya dan seksual di Amerika Serikat. Pada saat inilah geliat-geliat untuk pecahnya revolusi yang mencapai puncaknya pada tahun 70-an serta berpengaruh ke suluruh dunia dimulai.[73] Gerakan kaum gay ini bermula pada tahun 1969 menyusul keributan di penginapan Stonewell, yakni keributan yang timbul ketika polisi hendak menggeledah pusat aktivitas kaum gay. Sebagai reaksi atas kekerasan tersebut para aktivis gay yang semakin radikal membentuk Gay Liberation Front (GLF) sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak kaum kaum homoseks dengan sangat militan.[74] Dengan memakai strategi dan model gerakan New Left (gerakan kiri baru) GLF segera membentuk cabang-cabangnya di berbagai Negara Bagian di Amerika Serikat, mereka juga menginisasi perhelatan Gay Pride Parade untuk memperingati kerusuhan Stonewell setiap tahunnya.[75] Salah satu aksi para penggerak aktivis gay adalah mengintervensi pertemuan APA (Asosiasi Psikolog Amerika) pada tahun 1970, mereka meminta agar ada psikolog homoseks di pihak mereka, mereka juga melakukan demonstrasi dan menekan para psikolog yang hendak membuat nomenklatur patologi pada DSM.[76]
Unsur politis dalam keputusan APA ini telah menghilangkan kredibilitas psikiatri khususnya mereka yang di bawah naungan APA. Salah satu tokoh yang menyayangkan hal ini adalah Nicholas Cumming, mantan presiden APA. Menurut Cummings, ketundukan APA kepada tekanan politis dalam kasus homoseksualitas ini adalah sebuah bentuk perkembangan yang destruktif terhadap ilmu psikologi sendiri. Dalam pandangannya, diagnosis terhadap kaum homoseksual pasca-revolusi seks bersifat politispenelitian
Diagnosis today in psychology and psychiatry is cluttered with politically correct verbiage, which seemingly has taken precedence over sound professional experience and scientific validation. [77]
Menurut Cummings, ketika melakukan deklasifikasi homoseksual dari DSM, APA telah melanggar Leona Tyler Principle, yaitu pernyataan bahwa psikolog yang tergabung di dalam APA akan mengambil keputusan bersadarkan temuan saintifik murni dan tidak menyerah pada tekanan politik dari satu individu atau kelompok. Di dalam pengambilan keputusan tersebut, menurut Cummings, APA telah tunduk kepada tuntutan politis aktivis gay.[78] Melihat keadaan ini, Cummings menggugah komunitas psikologi di Amerika Serikat, untuk melakukan reformasi di dalam tubuh American Psychological Association (APA) sehingga mereka bisa kembali independen bebas dari agenda ideologi tertentu.[79]
Tekanan politik yang dihadapi oleh APA dalam proses deklasifikasi homoseksualitas membuat mereka bersikap ambigu. Sebagai kompensasi terhadap tekanan kolega psikolog yang tetap pada keputusan bahwa homoseksualitas adalah tidak normal, mereka memberikan catata bahwa keputusan APA mendeklasifikasi homoseksualitas tidak boleh dijadikan dalih oleh aktivis pro-gay
No doubt, homosexual activist groups will claim that psychiatry has at last recognized that homosexuality is as “normal” as heterosexuality. They will be wrong. In removing homosexuality per se from the nomenclature we are only recognizing that by itself homosexuality does not meet the criteria for being considered a psychiatric disorder. We will in no way be aligning ourselves with any particular viewpoint regarding the etiology or desirability of homosexual behavior.[80]
Bagaimana pun, keputusan APA mendeklasifikasikan homoseksualitas dari DSM akan membuat masyarakat percaya bahwa menjadi homoseksual sesungguhnya normal.
Dilema di atas membuat posisi APA terhadap orientasi seksual yang normal menjadi sangat relatif, mengikut nilai humanisme sekuler. Hal ini dipertegas keterangan APA di dalam DSM IV bahwa kriteria normal memang beragam berdasarkan kulturpenelitian
It is important to note that notions of deviance, standards of sexual performance, and concepts of appropriate gender role can vary from culture to culture.[81]
Dengan demikian, APA tetap kembali menyerahkan kepada budaya masing-masing masyarakat untuk menetukan perilaku seks menyimpang. Karena itu,, menjadikan psikologi sebagai satu-satunya basis bagi penerimaan homoseksualitas tidaklah tepat. Sebagai muslim, keputusan harus dikembalikan kepada wahyu sebagaiaman akan didiskusikan pada bagian selanjutnya.
Homoseksualitas Dalam Tinjauan Islam
Pandangan Islam terhadap homoseksualitas selain didasarkan atas penemuan ilmuwan tentang fenomena ini, harus pula didasarkan atas wahyu. Wahyu yang terkandung di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw adalah petunjuk yang tetap. Dengan demikian, dasar penilaian terhadap homoseksualitas tidak berubah seiring perkembangan masyarakat, melainkan turut pada keputusan Allah. Karena itu,, para ulama telah sepakat bahwa homoseksualitas adalah sesuatu yang terlarang.[82] Kesepakatan tersebut terjadi sebab larangan homoseksual telah jelas di dalam wahyu, bukan karena pengaruh heteronormativisme seperti yang diyakini pemikir liberal.[83] Pada bahasan ini, akan dipaparkan pandangan Islam mengenai homoseksualitas dari dua sudut pandang. Pertama dari segi konsep kejiwaan manusia menurut Islam untuk melihat homoseksualitas dari sudut pandang fitrah jiwa manusia. Selanjutnya homoseksualitas akan dianalisis dari sudut pandang (tujuan syariah) maqāşid asy-syarī‘ah beserta hukum yang telah ditetapkan wahyu atasnya.
Sebelum membahas pandangan Islam tentang homoseksualitas, perlu dijelaskan dahulu istilah yang digunakan untuk homoseksualitas di dalam perspektif Islam. Istilah yang umum digunakan untuk homoseksual adalah liwāṭ. Namun demikian, pemikir seperti Musdah Mulia dan Husein Muhammad membedakan liwāṭ dengan homoseksual, menurut mereka liwāṭ adalah perbuatan sodomi atau anal seks yang bisa dilakukan siapa saja termasuk pria heteroseks dan biseksual, sedangkan homoseksualitas lebih bersifat psikologis sehingga lebih tepat digunakan istilah mukhannaṡ.[84]Arah argumen mereka adalah untuk membenarkan homoseksualitas sebab para ahli fikih memang menerima adanya mukhannaṡ bi al-khalq, yaitu mereka yang terlahir sebagai pria dengan sifat-sifat feminin. Inti dari pendapat ini adalah mengarahkan pengharaman hanya kepada tindakan sodomi (praktik anal seks) sedangkan orientasi homoseksual harus diterima dengan rida.[85]
Argumen mereka tidak tepat, baik dari sudut pandang psikologi maupun Islam. Istilah mukhannaṡ lebih tepat diartikan effeminate yang berarti “keperempuan-perempuanan” atau “bersifat seperti perempuan”. Hadis tentang mukhannaṡ jelas merujuk kepada keadaan ini. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Ibnu Abbas di dalam Sahih Bukhari, ، لَعَنَ النَّبِىُّ ، عليه السَّلام ، الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ ،. artinya “Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” Menurut Ibnu Baththal, Rasulullah melaknat mereka bukan karena memang adanya sifat perempuan dalam dirinya yang merupakan ciptaan Allah. Laknat itu disebabkan oleh mereka yang memperturutkan kecenderungan itu dan berdandan seperti perempuan, laknat ini juga berlaku bagi laki-laki tulen yang sengaja menyerupai perempuan.[86] Jadi istilah mukhannaṡ tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis, melainkan pada perilaku menyerupai penampilan lawan jenis, maka ia lebih tepat diartikan effeminate, bukan homosexual. Mengidentikan homoseksualitas dengan effeminate jelas keliru. Mengasosiasikan kaum homoseksual dengan sifat tersebut, oleh psikolog dan pembela hak-hak LGBT justru dianggap homofobia.[87]
Istilah yang tepat untuk homoseksualitas adalah istilah liwāṭ (اللواط) sedangkan pelakunya disebut lūṭiy (اللوطي), para ulama dari kalangan ahli fikih, mufassir, ahli hadis dan ahli bahasa telah sepakat dengan penggunaan terminologi ini.[88] Istilah ini (liwāṭ dan lūṭiy) bukan saja merujuk kepada tindakan seksual (sexual behavior) tapi juga merujuk kepada orientasi seksual, yang secara psikologis melibatkan perasaan cinta dan ketertarikan. Hal ini bisa dilihat dari akar kata “لوط ” yang secara etimologis mengandung pengertian cinta dan melekat atau cinta yang melekat di hati (al-hub al-lāziq bi al-qalbi) sebagaimana disebutkan di dalam Lisān al-‘Arab.[89] Meskipun istilah liwāṭ sesungguhnya diambil dari nama Nabi Luth, tapi makna kebahasaan yang terkandung di dalam akar katanya tetap mengikut di dalam kata liwāṭ dalam kaitannya dengan homoseksualitas. Bakr bin Abdillah Abu Zayd menegaskan di dalam Mu’jam Manāhī al-Lafẓiyahpenelitian
أن المعنى لُغة لا يأبي دخوله في مشموله ، ومن ثم إطلاقه عليه ؛ لتوفر معانيه في هذه الفِعْلة من جهة قوة الباعث: الحب والشهوة للذكران ، انظر إلى قول الله – تعالى – عن قوم لوط في تقريعه ولومه لهم -: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} [ لأعراف:81] ، فقوله شهوة فيه معنى الحب الذي هو من معاني لَوَطَ
Kedudukan kata syahwah (شهوة) di dalam surah al-A’rāf ayat 81 dan an-Naml ayat 55 sebagai maf’ūl li ajlih, semakin mempertegas unsur orientasi seksual di dalam perbuatan kaum Luth.[90] Kutukan yang diturunkan kepada mereka juga ada kaitannya dengan orientasi yang mereka perturutkan. Selain kata liwāṭ bagi homoseksualitas yang melibatkan perempuan, atau lesbianisme di dalam khazanah Islam dikenal isitlah siḥāq (سحاق). Istilah ini digunakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya dan menyebutnya sama kejinya dengan zina.[91] Secara istilah dan bahasa, siḥāq adalah perbuatan perempuan terhadap perempuan lainnya sebagaimana yang ia lakukan bersama laki-laki.[92] Jadi siḥāq mencakup praktik lesbianisme, kecenderungan terhadapnya (orientasi seks lesbian) jelas merupakan syahwat yang harus dilawan.
Allah tentu tidak menghukum bila homoseksualitas hanya berupa keinginan dalam hati, tapi membiarkannya dan tidak melawannya lalu memperturutkannya adalah sebab turunnya laknat. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dibahas tentang pandangan Islam terhadap kecenderungan homoseksual yang muncul di dalam hati manusia.
- Homoseksualitas dan Konsep Fitrah
Salah satu tema sentral dalam problem homoseksual dari segi teologis adalah bahwa keadaan tersebut—orientasi seksual kepada sesama jenis—adalah bagian dari kodrat Allah kepada seseorang. Beberapa pemikir liberal pun menghalalkan homoseksual dengan dalih ini. Tim penulis Fiqih Seksualitas misalnya menyatakan bahwa homoseksualitas adalah takdir, sehingga harus diterima (rida) oleh yang bersangkutan dan ditolerir oleh masyarakat.[93] Di dalam Islam, konsep yang memiliki kaitan dengan ini adalah fitrah penciptaan manusia. Sebab term fitrah digunakan untuk menggambarkan keadaan manusia ketika lahir di muka bumi ini.[94] Istilah ini bahkan digunakan di dalam al-Qur’an dalam narasi yang menggambarkan penciptaan langit, bumi, dan manusia.[95]
Secara etimologi fitrah memiliki beberapa makna. Kata fitrah adalah serapan dari bahasa Arab فطرة, sehingga pengertiannya akan dibahas dari sudut pandang bahasa Arab. Kata ini berasal dari فطر (fa ṭa ra) yang berarti menguak atau membelah. Sementara para ahli bahasa menambahkan bahwa fitrah adalah menciptakan sesuatu untuk pertama kali/ tanpa ada bentuk sebelumnya, fitrah juga bisa diartikan asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar[96], fitrah juga bisa diartikan keadilan suci[97]. Artinya fitrah merupakan penciptaan seseorang yang sesuai dengan agama yang benar dan tuntutan akan hakikat kehidupan yaitu mencari keadilan tentang penyembahan akan Tuhan. Fitrah merupakan sifat bawaan yang ada sejak lahir[98]. Dari sini disimpulkan bahwa dalam konsep fitrah, manusia pada dasarnya sudah memiliki kecenderungan untuk mengikuti kebaikan. Karena itu, konsep fitrah tidak bisa disamakan dengan teori tabularasa bahwa manusia lahir dalam keadaan netral tidak memiliki potensi apa-apa.[99]
Potensi kebaikan yang tertanam di dalam diri manusia sesuai fitrahnya adalah potensi untuk taat kepada Allah. Hal tersebut jelas, sebab tujuan penciptaan manusia adalah menjadi hamba yang taat kepada-Nya.[100] Untuk mencapai ketaatan tersebut tentu saja manusia telah dikaruniai pengetahuan tentang Allah sejak perjanjian primordial.[101]Al-Attas di dalam penejelasanya mengenai nature of man, menyatakan bahwa agama dan pengetahuan instrinsik di dalam jiwa manusia merupakan bagian dari fitrah penciptaannya.[102] Penggunaan kata fitrah di dalam surah ar-Rum: 30, menguatkan pengertian ini. Di dalam ayat tersebut, frasa fitratallāhi disandingkan dengan ad-dīn hanīfah. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menegaskan bahwa Allah memang menciptakan (faţara) makhluknya di atas keislaman. Abu Hurairah mengutip ayat tersebut setelah meriwayatkan hadis pokok tentang fitrah, ini menunjukan bahwa Abu Hurairah memahami fitrah terkait erat dengan kebaikan dan secara khusus kepada Islam.[103]
Berdasarkan konsep fitrah ini, maka dalam konteks normalitas dari perspektif Islam, seorang yang normal adalah seorang yang berada di atas fitrahnya yaitu cenderung kepada kebaikan. Konsep normal dan abnormal sangat penting dipahami sebab dari sinilah akan ditputuskan, apakah homoseksualitas merupakan keadaan asal yang normal bagi manusia atau bukan. Normalitas dari perspektif para ulama disebut sebagai keadaan hati yang sehat (al-qalb as-salīm). Di dalam karyanya Igāṡah al-Luhfān, Ibn al-Qayyim al-Jauzīyah merangkum pendapat para ulama mengenai karakteristik hati yang sehat, yakni hati yang selamat (salima) dari setiap keinginan (syahwah) yang bertentangan dengan perintah atau melanggar larangan Allah serta hati yang selamat dari keragu-raguan (syubhāt) yang bertentangan dengan kabar dari-Nya.[104] Jadi ada dua penyebab utama hati menjadi sakit penelitian syahwah dan syubhah.
Syahwat di dalam bahasa Indonesia lebih berkonotasi pada nafsu seksual, tapi dalam pengertian al-Qur’an, syahwat pada dasarnya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dan harus digunakan pada jalan kebaikan. Al-Ragib al-Asfahānī di dalam al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān menjelaskan bahwa syahwat adalah dorongan kuat terhadap jiwa agar meraih yang diinginkannya. Syahwat memiliki dua bentuk, ada yang baik (syahwah ṣādiqah) dan ada pula yang buruk (kāżibah).[105] Syahwat yang buruk adalah dorongan jiwa untuk meraih sesuatu yang dilarang oleh Allah. Homoseksualitas di dalam al-Qur’an disifati sebagai syahwat yang buruk (fāḥisyah).[106] Perbuatan lain yang disifati dengan kata fāḥisyah oleh al-Qur’an adalah perzinaan. Karena itu, beberapa ulama menyamakan antara perbuatan liwāţ kaum homoseks dengan perbuatan zina. Hubungan dari keduanya adalah sama-sama ekspresi syahwat yang keluar dari fitrah manusia.
Godaan untuk menyimpang dari fitrah melalui syahwat adalah bentuk ujian Allah kepada manusia. Manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus suci sepanjang hidup mereka. Syed Muhammad Naquib al-Attas menjelaskan bahwa meskipun telah memiliki fitrah yang innate pada dirinya, manusia tetap memiliki potensi untuk berbuat salah. Perbuatan tersebut berasal dari kelupaannya terhadap fitrah dirinya. Manusia disebut al-insān, karena sebab ini. Insān seakar dengan kata nisyān, yang berarti lupa.[107] Di dalam al-Qur’an sendiri telah disebutkan bahwa Allah mengilhamkan fujūr dan taqwa ke dalam jiwa manusia (nafs).[108] Fujūr menurut ar-Rāgib berarti tercabiknya tabir agama (syaqq satri diyānah).[109] Maka fujūr yang telah diilhamkan Allah kepada jiwa manusia adalah potensi kerusakan fitrah. Namun demikian, Allah pun telah mengilhamkan taqwa yang berarti menjaga diri.
Dari perspektif ini, homoseksualitas dipandang sebagai bagian dari fujūr yang harus dilawan dengan taqwa oleh mereka yang merasakan kecenderungannya. Telah dipaparkan pada bagian kajian psikologis, bahwa meskipun ada kemungkinan genetik dalam etiologi homoseksual, faktor lingkungan tetap yang paling dominan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa fitrah bisa berubah karena faktor lingkungan dan pola asuh di kelaurganya.[110]Meski demikian, ia bisa saja berubah jika memiliki motivasi yang kuat. Taqwa adalah sumber motivasi tersebut. Manusia harus melawan semua kecenderungan buruk pada dirinya. Para ulama telah merumuskan upaya beranjaknya jiwa manusia dari tingkatan pergolakan melawan fujūr hingga menjadi jiwa yang tenang (an-nafs al-muţmainnah). Rumusan tersebut diderivasi dari pembagian al-Qur’an atas jiwa manusia menjadi tiga macam penelitian an-nafs al-ammārah bi as-su’, an-nafs al-lawwāmah, dan an-nafs al-muţmainnah.[111]
Pembagian nafsu menjadi tiga di atas sebenarnya adalah entitas yang sangat dinamis, manusia senantiasa berusaha beranjak menjadi lebih baik. Fitrah manusia senantiasa beredar di antara tiga keadaan tersebut. Keadaan pertama adalah an-nafs al-ammārah bi as-su’, secara literal berarti jiwa yang selalu mengarahkan diri pada keburukan.[112] At-Tustari di dalam tafsirnya menyebutkan empat tabiat dari nafsu ini yang membuatnya menjadi tingkatan terendah penelitian pertama nafsu hewani (bahāim) yang berpusat pada pemuasan birahi seksual dan nafsu makan penelitian kedua nafsu syaitani (tab’u asy-syayāţīn) yang mendorong manusia untuk tenggelam dalam perbuatan yang sia-sia penelitian ketiga nafsu ini akan mendorong orang-orang untuk berbuat licik dan menipu penelitian keempat, nafsu ini selalu mendorong seseorang untuk berlaku sombong dan angkuh seperti Iblis (al-abālisah al-istikbār).[113] Orientasi homoseksual jelas merupakan dorongan dari nafsu ini, khususnya pada tabiat bahāim yang mendorong seseorang untuk selalu mencari kepuasan seksual. Bila diikuti, maka nafsu ini akan meminta pemenuhan menjadi tindakan homoseksual. Apabila tidak ada perlawanan, maka seseorang berorientasi homoseksual akan melakukan come out, dan menjadi gay. Ia akan merasa bangga atas maksiat yang dilakukannya. Pada tahap ini, ia telah jatuh di dalam perangkap keempat yakni menjadi angkuh dengan penyimpangannya dari fitrah.
Allah telah memberikan potensi kepada manusia untuk melawan kecenderungan nafsu yang buruk. Meskipun manusia bisa saja jatuh ke dalam keadaan buruk sebab kealpaannya, Allah telah memberikan mereka potensi berupa ilmu serta kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian manusia diberikan petunjuk langsung berupa wahyu. Allah memberikan manusia kekutan ikhtiyār, yakni kemampuan untuk selalu memilih jalan terbaik.[114] Bahkan manusia yang telah jatuh ke dalam keburukan akan merasa gelisah atas keadannya tersebut. Keadaan gelisah karena penyimpangan ini disebut an-nafs al-lawwāmah.[115] Secara literal lawwāmah berarti selalu menyalahkan dirinya, menyesali keadannya. Seorang yang berada pada keadaan ini selalu menyesali dirinya sembari terus bersungguh-sungguh melakukan kebaikan.[116] Keadaan ini merupakan langkah besar pertama dalam perkembangan psiko-spritual seseorang. Dari perspektif lain, Ibn al-Qayyim menyebut keadaan ini sebagai hati yang sakit (al-qalb al-marīḍ). Ciri hati sakit adalah padanya ada kecintaan kepada Allah tapi ia senantiasa dibayangi syahwat yang berusaha memalingkannya dan selalu ia lawan dengan gelisah.[117]
Dalam keadaan nafs al-lawwāmah seseorang harus terus menerus mengikuti ilmu dari Allah (wahyu) serta mengikuti akal sehatnya. Al-Attas menegaskan bahwa manusia di dalam tahapan ini sedang berjuang melawan nafsu hewani (animal powers). Untuk memenangkan pertarungan tersebut, ia harus memakai ilmu pengetahuannya, akhlak yang sempurna, serta usaha yang kuat.[118] Muslim yang mengalami keadaan ini juga perlu senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, Dia akan senantiasa memenuhi permohonannya.[119] Seorang yang memiliki kecenderungan homoseksualitas di dalam dirinya dan merasa gelisah atas keadaan tersebut sedang berada di fase ini. Maka ia seharusnya mengikuti tuntunan wahyu untuk menjauhinya. Kajian psikologi yang telah disebutkan di atas telah menunjukan bahwa ia bisa berubah bila menguatkan motivasinya. Akal sehat harus didahulukan di atas keinginan nafsunya. Telah terbukti bahwa kaum homoseksual yang berkecimpung di dalam kehidupan gay adalah kelompok paling rentan terhadap penularan penyakit kelamin dan AIDS. Seorang yang memiliki akal sehat akan menghindarkan dirinya dari kecelakaan dunia dan akhirat.
Manusia yang berhasil melewati tahapan an-nafs al-lawwāmah akan memperolah ketenangan batin di sisi Allah. Keadaan ini disebut a-nafs al-muţmainnah yang secara literal berarti jiwa yang tenang.[120] Al-Khāzin di dalam tafsirnya menggambarkan jiwa ini sebagai jiwa yang menetapi keimanan, ketakwaan, membenarkan dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ia rida terhadap keadaan dirinya sesuai ciptaan Allah.[121] Bagi seorang yang memiliki kecenderungan homoseksual dan berhasil mengatasinya, ia harus tunduk kepada ketentuan Allah meskipun itu tidak mudah. Ia rida terhadap cobaan dari Allah berupa kecenderungan menyukai sesama jenis. Bentuk keridaannya ini bukanlah dengan mengikuti kecenderungan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh kaum liberal. Keridaan yang sesungguhnya, sebagaiman ditegaskan al-Khazin, adalah rida mengikuti ketentuan wahyu meskipun ia harus berusaha melawan kecenderungan buruk dalam dirinya. Allah memastikan ujian yang diberikan pasti bisa dilewati oleh hamba-Nya.[122] Apabila dirinya sukar dalam usaha tersebut, ia jatuh kembali di dalam homoseksualitas selama terapi, maka ia tidak boleh berputus asa. Allah bersedia senantiasa menerima taubat dari hamba-Nya[123]
- Homoseksualitas Dari Perspektif Hukum Syariah
Dari perspektif lain, homoseksualitas menyalahi fitrah penciptaan tubuh manusia. Secara biologis manusia telah diciptakan saling berpasangan sebagai akomodasi dari kecenderungan untuk saling ketertarikan di antara laki-laki dan perempuan. Struktur tubuh perempuan telah dibuat untuk bisa mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki untuk membuahi perempuan. Al-Hasan al-Bashri, sebagaimana disebutkan oleh az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa kata mawaddah di dalam surah Rum ayat 21 –yang berbicara tentang pernikahan—adalah kiasan bagi hubungan intim (jima’) sedangkan rahmah adalah kiasan untuk anak keturunan.[124] Karena itu,, fitrah peciptaan syahwat yang disalurkan lewat lembaga pernikahan adalah memperoleh keturunan (prokreasi), selain tentu saja untuk berbagi rasa sayang dan cinta. Aktivitas seksual prokreasi adalah sesuatu yang penting. Dengan memadukan analisa Ibnu Khaldun dan Giambattista Vico, sejarawan Italia Angelo Bertolo memperingatkan kolapsnya peradaban Barat akibat angka kelahiran yang semakin menurun.[125]
Keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi adalah bagian dari fitrah penciptannya. Sejak awal, manusia diberikan amanah untuk menjadi khalīfah di muka bumi.[126] Amanah ini menurut al-Attas bukan hanya berarti penguasaan atas bumi dalam konteks sosiopolitik atau mengontrol alam melalui temuan sains, tapi lebih pada pertanggung jawaban untuk memeliharanya dengan jiwa (nafs) dan akal yang jernih.[127] Beban khalīfah juga termasuk beban memelihara dirinya sendiri. Untuk menjalankan amanah ini maka keberlangsungan hidup umat manusia adalah sebuah priorias penting yang dijaga oleh syariah. Para ulama telah merumuskan bahwa salah satu tujuan syariah (maqāṣid as-syarī’ah) adalah menjaga keberlangsungan garis keturunan manusia (hifẓ an-nasl). Selain itu, syariah juga bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia (hifẓ an-nafs).[128] Karena itu, perbuatan-perbuatan yang mengancam kedua hal tersebut menjadi tindakan-tindakan terlarang di dalam syariat dan padanya dikenai hukuman. Al-Ghazāli menyebutkan homoseksual sebagai dosa yang diharamkan karena akan memutuskan keuturunan.[129] Selain itu, penemuan sains menunjukan gaya hidup homoseksual beresiko besar terinfeksi virus mematikan, AIDS. Dengan demikian, pada perbuatan ini syariat mengenakan hukuman-hukuman tertentu.
Dalam menjatuhkan hukuman, syariah hanya berkaitan dengan tindakan lahir dan tidak menyentuh keadaan batin manusia. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa ia hanya memberikan hukuman bagi sesuatu yang zahir dan membiarkan Allah mengurusi batin manusia.[130] Dengan demikian, aspek homoseksualitas yang dikenai hukuman bila terbukti hanyalah dimensi perbuatannya saja yakni praktik hubungan seksual sejenis. Baik antara laki-laki maupun perempuan (lesbianisme). Homoseksualitas dalam pengertian orientasi seksual yang masih berupa kecenderungan dalam hati untuk menyukai sesama jenis tidak dikenai hukuman. Namun demikian, ia tetaplah syahwat terlarang yang harus dilawan, tidak boleh dibiarkan atau dilampiaskan sebagaiman telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini juga menunjukan bahwa hukuman dikenakan kepada siapapun pelaku hubungan seksual sesama jenis (liwāţ atau siḥāq), termasuk laki-laki atau perempuan yang secara psikologis heteroseksual. Hukuman yang disebutkan di sini tidak termasuk anal seks yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan (liwāţ as-sugrā).
Di dalam hukum liwāţ dan siḥāq terdapat masalah-masalah yang telah disepakati ulama dan ada pula yang masih menjadi perbedaan pendapat. Para ulama telah sepakat terhadap keharaman perbuatan ini dan bahwa padanya harus dijatuhi hukuman. Dasar pengharamannya adalah ayat-ayat al-Qur’an, hadis, dan ijma’. Mereka juga sepakat bahwa hukuman hanya bisa ditetapkan apabila terdapat saksi yang melihat langsung seperti pada ketentuan zina penelitianImam Ahmad, Imam Syafi’i dan Imam Malik mensyaratkan saksinya empat sedangkan Imam Abu Hanifah menetapkan dengan dua saksi.[131] Hukuman juga bisa berlaku dengan pengakuan pelakunya. Di dalam liwāţ atau siḥāq juga berlaku hukuman qażf bagi mereka yang menuduh seseorang melakukan perbuatan tersebut tapi tidak bisa membutikannya.[132] Oleh karena itu, di dalam Islam tidak akan ditemukan tindakan diskriminatif terhadap orang-orang homoseksual hanya karena orientasi atau kecenderungan dalam diri mereka, tapi bila ia melakukan tindakan homoseksual maka ia wajib dikenai hukuman. Seseorang yang secara serampangan menuduh orang lain seorang pelaku praktik homoseksual tanpa bisa membuktikan diancam hukuman cambuk, sebagai realisasi pidana qażf.
Ulama berbeda pendapat dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman liwāţ adalah sama dengan hukuman hadd bagi pezina, yakni rajam bagi pelaku muḥṣān (telah beristri) dan cambuk serta diasingkan bagi pelaku gair muḥṣān (belum beristri). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman pelaku liwāţ hanyalah berupa ta’ẓir, dimana bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.[133] Adapun bentuk hukuman bagi pelaku lesbianisme atau sihāq adalah ta’zhir. Para ulama bersepakat bahwa pelaku lesbianisme atau sihāq tidak dikenai hukuman hādd seperti pada pelaku zina. Bagi mereka hanya dikenakan hukuman ta’zhir, yakni bentuk hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim. Hukuman yang diberikan hendaknya bisa membuat jera.[134]
Dua pendapat ini masing-masing memiliki perincian. Meskipun Imam Abu Hanifah menetapkan hukuman ta’zhir kepada pelaku liwāţ, tapi muridnya yakni Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat seperti jumhur. Lebih jauh lagi, menurut mereka apabila pelaku liwāţ yang masih bujangan terus-menerus mengulangi perbuatannya meski telah dikenai hukuman cambuk maka orang tersebut boleh dijatuhi hukuman mati. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth keduanya dikenai hukuman rajam, baik yang melakukan penetrasi (al-fā’il) maupun pasangannya (al-maf’ūl). Syarat dijatuhkannya hukuman ini menurut mereka hanyalah sampainya umur balig (at-taklīf) tidak disyaratkan harus Islam. Sedangkan mazhab Syafi’iyah juga berpendapat sama, yakni pelaku maupun pasangannya sama-sama dibunuh berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dimana Rasulullah memerintahkan untuk membunuh kedua pasangan yang didapati melakukan perbuatan liwāţ. Ulama Hanabilah sepakat dengan pendapat ini. Sebagian ulama Syafi’iyah memilih pendapat seperti Imam Abu Hanifah yakni dikenai hukuman ta’zhir kepada pelaku penetrasi (al-fā’il). Adapun pasangan yang padanya dilakukan penetrasi (al-maf’ūl) apabila ia masih anak-anak, atau dipaksa, atau orang gila maka ia tidak dikenai hukuman. Namun apabila ia sudah balig serta melakukannya dengan sukarela maka ia dikenai hukuman cambuk atau diasingkan, baik ia muhsan maupun gair muhsan.[135]
Dari pemaparan di atas, dapat disimplukan bahwa semua ulama sepakat tentang keharaman tindakan homoseksualitas, baik liwāţ maupun sihāq. Mereka juga sepakat tentang keharusan menjatuhkan hukuman atas mereka. Perbedaan hanya pada takyīf atau tata cara hukuman yang dijatuhkan. Sebagian berpendapat harus diterapkan hukuman hādd zina dimana bentuk hukumnya sudah tetap penelitian rajam dan cambuk. Sedangkan ulama lainnnya berpendapat hukumannya berbentuk ta’zhir dimana bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Untuk konteks Indonesia dimana hukum pidana Islam belum diterapkan, hukum ta’zhir lebih aplikatif yakni hukuman bagi pelaku homoseksualitas diserahkan kepada pemerintah melalui penetapan peraturan tertentu.
Kesimpulan
Diskursus homoseksualitas di dalam psikologi sangat dipengaruhi oleh dasar epistemologinya yang sekuler. Harus diingat bahwa ilmu, termasuk psikologi tidaklah bebas nilai. Epistemologi ini lahir dari worldview Barat sebagai tempatnya berkembang yang salah satu cirinya adalah ever-shifting (selalu berubah). Salah satu bagian yang sangat bias nilai barat adalah patokan normal dan abnomal. Patokan ini, diakui oleh para psikolog sendiri sangat relatif. Ukurannya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Evolusi diagnosis terhadap homoseksualitas pun sejajar dengan perubahan nilai di dalam masyarakat Barat penelitian dari hegemoni Kristen menjadi sekuler-liberal. Selain itu, diskursus homoseksualitas tidak lepas dari tekanan politik gerakan-gerakan kaum gay. Puncaknya adalah deklasifikasi homoseksualitas dari DSM yang diterbitkan APA. Setelelah deklasifikasi tersebut, timbul berbagai kritikan dari psikolog lain. Banyak psikolog yang mengkritik deklasifikasi homoseksualitas sebagai sebuah keputusan yang tidak murni saintifik tapi sarat kepentingan politis. Mereka menunjukan hasil-hasil penelitian yang menunjukan bahwa homoseksualitas adalah sebuah kelainan psikologis, bukan semata-mata faktor genetik. Mereka juga menujukan bahwa orientasi seksual bisa dirubah melalui terapi.
Sebagai muslim, pandangan terhadap homoseksualitas (liwāţ dan sihāq) haruslah didasarkan atas wahyu bukan evolusi nilai masyarakat. Patokan normal dan abnormal adalah fitrah penciptaan manusia di alam wahyu. Fitrah manusia adalah menjadi hamba Allah yang senantiasa mematuhi-Nya, termasuk menghindari homoseksualitas. Hal tersebut dianggap syahwat yang harus ia lawan dengan menguatkan iman, berdoa, dan berusaha melalui terapi. Perasaan tersebut adalah ujian yang harus ia tempuh sebagai hamba Allah. Dengan demikian, Islam tidak menghukum seseorang hanya karena ia memiliki rasa tertarik kepada sesama jenis. Hukuman syariah hanya dijatuhkan kepada mereka yang memperturutkan syahwat dan menjalani gaya hidup homoseksual, mejadi gay atau lesbian.
Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman pelaku liwāţ dan sihāq seperti hādd zina, sedangkan kalangan Hanafiyah menetapkan hukuman ta’zhir, yakni ketentuannya diserahkan kepada pemerintah. Untuk kontesk Indonesia, hukuman ta’zhir lebih aplikasif. Meskipun demikian, seorang tidak bisa langsung dihukum hanya karena tuduhan, melainkan harus ada saksi dan bukti. Pidana qazf akan dikenakan kepada mereka yang menuduh orang lain melakukan liwāţ dan sihāq tanpa saksi dan bukti. Hukuman-hukuman ini ditetapkan syariat sebab manusia diciptakan untuk menjadi khalīfah-Nya untuk mmakmurkan bumi. Amanah inilah yang diproteksi oleh syari’ah melalui hifẓ an-nasl (menjaga keturunan) dan hifẓ an-nafs (menjaga keselamatan jiwa). Karena itu, syariah melarang dan memberikan hukuman kepada manusia yang melakoni gaya hidup yang memutus keturunan (nasl) dan beresiko besar terkena penyakit mematikan, AIDS. Petunjuk dan hukum syariah ditetapkan untuk kebaikan umat manusia sendiri. Wallāhu a’lam bi as-sawab. []
Daftar Pustaka
Abu Zayd, Bakr bin Abdillah, Mu’jam Manahi al-Lafdzhiyah wa Ma’ahu Fawaid fi Alfadz, (Riyad: Dar al-‘Ashimah, 1996)
al-Asfahani, Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhdhal Abu al-Qasim al-Raghib, Mufradat fi Gharib al-Qur’an, (Damaskus: Dar al-‘Ilm, 1412 H)
al-Attas, Syed Muhammad Naquib, Islam dan Sekulerisme, (Bandung: PIMPIN, 2010)
, Prolegomena to The Metaphysics of Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995)
al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, Ihya’ Ulim ad-Din, (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H)
al-Haitsami, al-Hafidz Nur ad-Din Ali bin Abi Bakr, Majma’ Dzawaid wa Manba’al-Fawaid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
al-Jauziyah, Muhammad bin Abu Bakar Ayyub az-Zar’i Abu Abdullah Ibnul Qayyim, Ighatsah al-Luhfan, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975)
al-Jazairi, Abd ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
al-Khazin, Alauddin Ali bin Muhammad Abu al-Hasan, Lubab at-Ta’wil bi Ma’ani at-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415)
al-Maragi, Amhad bin Mustafa, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Syirkah Mustafa Bab al-Halabi wa Abnah, 1946)
al-Mahalli, Jalal ad-Din Muhammad Ahmad dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, Tafsir al-Jalalaini, (Kairo: Dar al-Hadis, tt)
al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar as-Shadir, tt)
al-Qurtubi, Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri, Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Baththal, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003)
American Psychiatr. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth Edition (Washington: American Psychiatric Association, 1996)
an-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi, al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ila Rasulillah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt)
Armelli, Jerry A, et al. “A Response to Spitzer’s (2012) Reassessment of His 2003 Study of Reparative Therapy of Homosexuality.” Archives Of Sexual Behavior (2012): 1-2.
as-Syathibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnathi, al-Muwafaqat, (tt: Dar Ibn ‘Affan, 1997)
asy-Syaibani, Al-Wazir Abu al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah, Ikhtilaf al-Aimmati al-‘Ulama, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, 2002)
at-Tustari, Abu Muhammad Sahl bin Abdillah bin Yunus bin Rafi’, Tafsir at-Tustari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H)
az-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiy, tt)
Badri, Malik, The Dilemma of Muslim Psychologyst, Tjm. Siti Zainab Luxfiati, Dilema Psikolog Muslim, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
Baharuddin, Aktualisasi Psikolog Islam, (Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2011)
Bayer, Ronald, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, (New Jersey: Princeton University Press, 1981)
Benette, Paul, Abnormal And Clinical Psychology: An Introductory Textbook , (New York: Mc Graw Hill International, 2011)
Beyrer, Chris, et al. “Global Epidemiology Of HIV Infection In Men Who Have Sex With Men.” The Lancet 380.9839 (2012), hal 367-368.
Bertolo, Angelo, The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization, (Indiana: iUniverse, 2012)
Breen, Margaret Sönser dan Fiona Peters, Genealogies of Identity: Interdisciplinary Readings on Sex and Sexuality, (New York: Rodopi, 2005)
Byrd, A. Dean dan Stony Olsen. “Homosexuality: Innate and Immutable.”Regent UL Rev. 14 (2001), hal 422.
Cameron, Paul dan Kirk Cameron. “Re-Examining Evelyn Hooker: Setting the Record Straight with Comments on Schumm’s (2012) Reanalysis.” Marriage & Family Review 48.6 (2012), hal 49.
Colman, Andrew M., A Dictionary of Psychology, (New York: Oxford University Press, 2009)
Cotten, Christopher dan John W. Ridings. “Getting Out/Getting In: The DSM, Political Activism, and the Social Construction of Mental Disorders.” dalam Social Work in Mental Health 9.3 (2011), hal 182
Cox, Harvey, The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective, (New Jersey: Princeton University Press, 2013) hal 37
Crompton, Louis, Homosexuality and Civilization (London: The Belknap Press Of Harvard University Press , 2003)
Cummings, Nicholas A “The APA And Psychology Need Reform.” Makalah disampaikan pada Annual Convention Of The American Psychological Association (August 12). New Orleans, LA. 2006.
Darwisy, Muhyiddin bin Ahmad Musthafa, I’rab al-Qur’an wa Bayanuhu, (Damaskus dan Beirut: Dar al-Yamamah, 1415H )
Djayadi, M.T, Kamus Lengkap Islamologi, (Yogyakarta, 2009)
Does, Ralf, Magnus Hirschfeld: The Origins of the Gay Liberation Movement, (New York: NYU Press, 2014)
Dynes, Wayne R., Stephen Donaldson, Homosexuality and Medicine, Health, and Science, (ttp: Taylor & Francis,1992)
Gerrig, Richard J et al, Psychology and Life, (tt: Pearson Education Australia, 2010)
Getzfeld, Andrew R., Essentials of Abnormal Psychology, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2006)
Hawari, Dadang, Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual, (Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2009)
Husain, M. G ed, Psychology and Society in Islamic Perspective, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996)
Husaini, Adian, Seputar Paham Kesetaraan Gender, (Depok: Adabi Press, 2012)
, et al, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)
Jenkins, John dan John Pigram (ed), Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, (tt: Routledge, 2004)
Kinsey, Alfred, et al. Sexual Behavior In The Human Male,( Philadelphia: The Saunders Company,1948)
LeVay, Simon, Gay, Straight, And The Reason Why: The Science Of Sexual Orientation (Oxford University Press, 2010)
Maramis, Willy F., Ilmu Kedoteran Jiwa, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010)
Ma’luf, Louis dan Fr. Bernard Tottel, Qamus al-Mujid (Bairut:Darul al-Mausyaraq, 2003)
Minton, Henry L., Departing from Deviance: A History of Homosexual Rights and Emancipatory Science in America, (Chicago: The University of Chicago, 2002)
Muhammad, Husein et al, Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas, (tt: PKBI, tth)
Mohamed, Yasien. “Fitrah And Its Bearing On The Principles Of Psychology.”American Journal of Islamic Social Science 12.1 (1995),
Munawir, Achmad Warson, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
Myers, Joanne, Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage, (USA: Scarecrow Press, 2003)
National Association for Research and Therapy of Homosexuality (US). Scientific Advisory Committee, et al. What Research Shows: NARTH’s Response to the APA Claims on Homosexuality: a Report of the Scientific Adisory Committee of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality. National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 2009.
Nicolosi, Joseph, “The Removal Of Homosexuality From The Psychiatric Manual.”dalam Catholic Social Science Review ( 2001): 71 – 72.
Nordenfelt, Lennart, On the Nature of Health, (Springer Science & Business Media, 1995)
Nurseha, Qasim, “Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual”, Islamia, 3.5. (2010),hal 141
Oosterhuis, Harry, Stepchildren of Nature: Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity, (Chicago: Universtiy of Chicago Press, 2008)
Pickett, Brent L., Historical Dictionary of Homosexuality, (Plymouth: The Scarecrow Press, 2009)
Reiss, Ira L dan Albert Ellis, At the Dawn of the Sexual Revolution: Reflections on a Dialogue, (Boston: AltaMira Press, 2002)
Richards, R. Scott dan Allen E. Bergin, A Spritual Strategy for Coseuling and Psychoteraphy Second Edition, (Washington DC: American Psychological Asosiation, 2007)
Rosario, Vernon A., Homosexuality and Science: A Guide to the Debates, (Calivornia: ABC-CLIO, 2002.)
Rönn, Minttu, et al. “Developing A Conceptual Framework Of Seroadaptive Behaviors In HIV-Diagnosed Men Who Have Sex With Men.” Journal of Infectious Diseases 2.10. (2014), hal 586
Sampson, Mark et al, Personality Disorder and Community Mental Health Teams: A Practitioner’s Guide, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2006)
Satinover, Jeffrey, Homosexuality and the Politics of Truth (tt: Baker Books, 1996)
Spencer, Colin, Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang, diterj oleh Ninik Rochani Sjams, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011)
Spitzer, Robert L. “Can Some Gay Men And Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting A Change From Homosexual To Heterosexual Orientation.” Archives of sexual behavior 32.5 (2003): 403-417.
. “Spitzer Reassesses His 2003 Study Of Reparative Therapy Of Homosexuality.” Archives of sexual behavior (2012): 1-1.
Soebagio, Rita, LGBT dan RUU KKG,(http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg) diakses 25 Desember 2014.
,Homophobia (http://thisisgender.com/kampanye-lesbi-berkemasan-psikologi/) diakses 25 Desember 2014.
Szasz, Thomas S., Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, (New York: Harper Perrenial, 1974)
Walsh, Richard T. G et al, A Critical History and Philosophy of Psychology,(United Kingdom: Cambridge University Press, 2014)
Wright, Rogers H dan Nicholas A. Cummings, eds. Destructive Trends in Mental Health: The Well Intentioned Path to Harm. (tt: Routledge, 2005)
Whitehead, Neil L dan Briar Whitehead, My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence, (Whitehead Associates, 2013)
Wizarah al-Awfaq wa Syuun al-Islami, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (tt: Dar as-Safwah, 1427H)
Zarkasyi, Hamid Fahmy, Liberalisasi Pemikiran Islam penelitian Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis, (Ponorogo, CIOS, 2007)
, Liberalism, “Liberalization and Their Impacts of Muslim Education” Tsaqofah, vol. 8, 2012, hal. 198.
Zachar, Peter dan Kenneth S. Kendler. “The Removal Of Pluto From The Class Of Planets And Homosexuality From The Class Of Psychiatric Disorders: A Comparison.” dalam Philos Ethics Humanit Med 7.4 (2012) hal 3-4
Zijlstra, Iris. “The Turbulent Evolution Of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference.” Dalam, Social Cosmos 5.1 (2014) hal 32.
*Peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA Gontor dan YDSA Surabaya
[1]Colin Spencer, Sejarah Homoseksualitas dari Zaman Kuno hingga Sekarang, diterj oleh Ninik Rochani Sjams, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), cet ke-2, hal. 447.
[2]Joanne Myers, Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage, (USA: Scarecrow Press, 2003) , hal. 1.
[3]Salah satu buktinya dapat dilihat dari terbitnya jurnal perempuan (edisi Mei, 2008), yang memperjuangkan perkawinan sesama jenis perempuan (lesbianisme), karena lesbianisme dianggap sebagai bentuk kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tertinggi. Adian Husaini, Seputar Paham Kesetaraan Gender, (Depok: Adabi Press, 2012) hal. 7
[4]Rita Soebagio, LGBT dan RUKKG,(http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg) Diakses 25 Desember 2014.
[5]Lihat Justisia, Indahnya Kawin Sesama Jenis, edisi 25, Th. XI 2004.
[6] Colin Spencer, Sejarah Homoseksualitas…hal 472
[7] Rita Subagio, Homophobia http://thisisgender.com/kampanye-lesbi-berkemasan-psikologi/, diakses 25 Desember 2014.
[8]Di dalam makalah ini, kata homoseksualitas merujuk kepada kedua maknanya tersebut. Dengan demikian, penggunakan istilah ini juga merujuk kepada kamu Gay dan lesbian, yakni para perempuan dan pria homoseks yang memutuskan untuk come out dan menjadikan orientasi seksual mereka sebagai identitas sosial yang dibanggakan. Lihat John Jenkins dan John Pigram (ed), Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation, (tt: Routledge, 2004), hal 231, 196
[9] Andrew M. Colman, A Dictionary of Psychology, (New York: Oxford University Press, 2009) hal 619.
[10] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dan Sekulerisme, (Bandung: PIMPIN, 2010) Hal 166. Dalam konteks psikologi, Richard T. G. Walsh,Thomas Teo, Angelina Baydala, A Critical History and Philosophy of Psychology, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2014) hal 600.
[11] Baharuddin, Aktualisasi Psikolog Islam, (Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2011), hal 32.
[12] Ibid, hal 43
[13]Septi Gumiandari, “Dimensi Spiritual Dalam Psikologi Modern (Psikologi Transpersonal sebagai Pola Baru Psikologi Spiritual)”. Paper dipresentasikan pada AICIS XII tahun 2012, 5-8 Nopember 2012, Surabaya. Hal 1040
[14] Ibid, hal 1046.
[15] Sharafat Hussain Khan, “Islamization of Knowledge: A Case for Islamic Psychology” dalam M. G Husain ed, Psychology and Society in Islamic Perspective, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1996) hal 45.
[16] Otto Rank, Psychology and The Soul, (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1950) hal 1
[17] Adian Husaini, “Urgensi Epistemologi Islam” dalam Adian Husaini et al, Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hal 44.
[18] Salah satu poin sekulerisasi yang menghasilkan sekulerisme adalah deconsecration of values penelitian penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehingga semuanya bersifat nisbi dan relativ. Lihat Harvey Cox, The Secular City: Secularization and Urbanization in Theological Perspective, (New Jersey: Princeton University Press, 2013) hal 37
[19] Paul Benette, Abnormal And Clinical Psychology: An Introductory Textbook , (New York: Mc Graw Hill International, 2011) Hal 12
[20] Thomas S. Szasz, Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct, (New York: Harper Perrenial, 1974) hal 262
[21] Richard J Gerrig et al, Psychology and Life, (tt: Pearson Education Australia, 2010) hal 534
[22]Andrew R. Getzfeld, Essentials of Abnormal Psychology, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2006) hal 1 -2.
[23] Malik Badri, The Dilemma of Muslim Psychologyst, Tjm. Siti Zainab Luxfiati, Dilema Psikolog Muslim, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal 12 – 15.
[24] Ibid, hal 16
[25] Mark Sampson, Remy McCubbin, Peter Tyrer, Personality Disorder and Community Mental Health Teams: A Practitioner’s Guide, (New Jersey: John Wiley and Sons, 2006) hal 36.
[26] Willy F. Maramis, Ilmu Kedoteran Jiwa, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010), hal 344
[27] Dasar larangan homoseksual terdapat dalam Genesis (Kejadian) 19:1-8 tentang penghacuran kaum Sodom dan Gomarah. Juga pada Leviticus (Imamat) 20:13 yang lebih eksplisit melarang kegiatan homoseksual.
[28] Louis Crompton, Homosexuality and Civilization (London: The Belknap Press Of Harvard University Press , 2003) hal 363.
[29] Ronald Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, (New Jersey: Princeton University Press, 1981), hal 16 – 19.
[30] Henry L. Minton, Departing from Deviance: A History of Homosexual Rights and Emancipatory Science in America, (Chicago: The University of Chicago, 2002) hal 11.
[31]Ibid. hal 11
[32] Margaret Sönser Breen, Fiona Peters, Genealogies of Identity: Interdisciplinary Readings on Sex and Sexuality, (New York: Rodopi, 2005) hal 6
[33] Ronald Baye, Homosexuality and American Psychiatry… hal 19
[34] Vernon A. Rosario, Homosexuality and Science: A Guide to the Debates, (Calivornia: ABC-CLIO, 2002.) hal 275.
[35] Wayne R. Dynes, Stephen Donaldson, Homosexuality and Medicine, Health, and Science, (ttp: Taylor & Francis,1992)hal 177
[36] Vernon A. Rosario, Homosexuality and Science….hal 18.
[37] Harry Oosterhuis, Stepchildren of Nature: Krafft-Ebing, Psychiatry, and the Making of Sexual Identity, (Chicago: Universtiy of Chicago Press, 2008) hal 52
[38] Ibid, hal 251
[39] Brent L. Pickett, Historical Dictionary of Homosexuality, (Plymouth: The Scarecrow Press, 2009) hal 52
[40] Ibid, hal 89 – 90
[41] Ralf Does, Magnus Hirschfeld: The Origins of the Gay Liberation Movement, (New York: NYU Press, 2014) hal 35
[42] Brent L. Pickett, Historical Dictionary of Homosexuality….hal 73-74.
[43] Lennart Nordenfelt, On the Nature of Health, (Springer Science & Business Media, 1995), hal 133
[44]Alfred Kinsey, et al. Sexual Behavior In The Human Male, (Philadelphia: The Saunders Company,1948) 638
[45] Ibid, hal 639
[46] Brent L. Pickett, Historical Dictionary of Homosexuality, hal 8
[47] Vernon A. Rosario, Homosexuality and Science: A Guide to the Debates, hal 133 – 134.
[48] American Psychiatry. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth Edition (Washington: American Psychiatric Association, 1996) hal xvii.
[49] Iris Zijlstra. “The Turbulent Evolution Of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference.” Dalam, Social Cosmos 5.1 (2014), hal 32.
[50] Joseph Nicolosi, “The Removal Of Homosexuality From The Psychiatric Manual.”dalam Catholic Social Science Review ( 2001): 71 – 72.
[51] Vernon A. Rosario, Homosexuality and Science: A Guide to the Debates… hal 143.
[52] Thomas S. Szasz, Myth of Mental Illness… 262
[53] Paul Cameron dan Kirk Cameron. “Re-Examining Evelyn Hooker: Setting the Record Straight with Comments on Schumm’s (2012) Reanalysis.” Marriage & Family Review 48.6 (2012), hal 49.
[54]Simon LeVay, Gay, Straight, And The Reason Why: The Science Of Sexual Orientation (Oxford University Press, 2010)
[55] Neil L Whitehead dan Briar Whitehead, My Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence, (Whitehead Associates, 2013), hal 177.
[56] Ibid, hal 56
[57] A. Dean Byrd and Stony Olsen. “Homosexuality: Innate and Immutable.”Regent UL Rev. 14 (2001), hal 422.
[58]Robert L. Spitzer “Can Some Gay Men And Lesbians Change Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting A Change From Homosexual To Heterosexual Orientation.” Archives of sexual behavior 32.5 (2003): 403-417.
[59]Robert L Spitzer. “Spitzer Reassesses His 2003 Study Of Reparative Therapy Of Homosexuality.” Archives of sexual behavior (2012): 1-1.
[60]Armelli, Jerry A., et al. “A Response to Spitzer’s (2012) Reassessment of His 2003 Study of Reparative Therapy of Homosexuality.” Archives Of Sexual Behavior (2012): 1-2.
[61]National Association for Research and Therapy of Homosexuality (US). Scientific Advisory Committee, et al. What Research Shows: NARTH’s Response to the APA Claims on Homosexuality: a Report of the Scientific Adisory Committee of the National Association for Research and Therapy of Homosexuality. National Association for Research and Therapy of Homosexuality, 2009. Hal 38.
[62] Dadang Hawari, Pendekatan Psikoreligi pada Homoseksual, (Jakarta: Balai Penerbitan FKUI, 2009), hal 62
[63] Ibid
[64] Robert L. Spitzer “Can Some Gay Men And Lesbians Change Their Sexual,…hal 406
[65] Dadang Hawari, Pendekatan Psikoreligi…hal 70 – 72.
[66] Chris Beyrer, et al. “Global Epidemiology Of HIV Infection In Men Who Have Sex With Men.” The Lancet 380.9839 (2012), hal 367-368.
[67] Minttu Rönn, et al. “Developing A Conceptual Framework Of Seroadaptive Behaviors In HIV-Diagnosed Men Who Have Sex With Men.” Journal of Infectious Diseases 2.10. (2014), hal 586
[68] Ronald Bayer, Homosexuality and American Psychiatry: The Politics of Diagnosis, (New Jersey: Princeton University Press, 1981), hal 3-4.
[69] Jeffrey Satinover, Homosexuality and the Politics of Truth (tt: Baker Books, 1996) hal 29
[70] Iris Zijlstra. “The Turbulent Evolution Of Homosexuality: From Mental Illness To Sexual Preference.” Dalam, Social Cosmos … hal 32.
[71] Peter Zachar dan Kenneth S. Kendler. “The Removal Of Pluto From The Class Of Planets And Homosexuality From The Class Of Psychiatric Disorders: A Comparison.” dalam Philos Ethics Humanit Med 7.4 (2012) hal 3-4
[72] Christopher Cotten dan John W. Ridings. “Getting Out/Getting In: The DSM, Political Activism, and the Social Construction of Mental Disorders.” dalam Social Work in Mental Health 9.3 (2011), hal 182
[73] Ira L. Reiss,Albert Ellis, At the Dawn of the Sexual Revolution: Reflections on a Dialogue, (Boston: AltaMira Press, 2002), hal vii
[74] Brent L. Pickett, Historical Dictionary of Homosexuality….hal 76
[75] Ibid
[76] Iris Zijlstra. “The Turbulent Evolution Of Homosexuality… hal 32.
[77] Rogers H Wright dan Nicholas A. Cummings, eds. Destructive Trends in Mental Health: The Well Intentioned Path to Harm. (tt: Routledge, 2005), hal 9
[78] Ibid, hal xiv
[79]Nicholas A Cummings. “The APA And Psychology Need Reform.” Makalah disampaikan pada Annual Convention Of The American Psychological Association (August 12). New Orleans, LA. 2006.
[80] American Psychiatric Association , Homosexuality and Sexual Orientation Disturbance: Proposed Change in DSM-II, 6th Printing, Page 44, Position Statement Retired., 1973. Hal 3
[81] American Psychiatr. Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders…. 493.
[82] Qasim Nurseha, “Kekeliruan Kaum Liberal Soal Homoseksual”, ISLAMIA, 3.5. (2010), hal 141
[83] Husein Muhammad et al, Fiqh Seksualitas Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas, (tt: PKBI, tth),hal 16 – 17
[84] I bid, hal 90.
[85] Ibid, hal 91-95
[86] Untuk penjelasan Ibnu Baththal, lihat Abu al-Hasan Ali bin Khalaf bin Abdil Malik bin Baththal al-Bakri al-Qurtubi, Syarhu Sahih al-Bukhari li Ibni al-Baththal, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2003) vol IX, hal 141-142
[87] Brent L. Pickett, Historical Dictionary of Homosexuality,…hal 93. Lihat juga Vernon A. Rosario, Homosexuality and Science… hal 120.
[88] Bakr bin Abdillah Abu Zayd, Mu’jam Manahi al-Lafdzhiyah wa Ma’ahu Fawaid fi Alfadz, (Riyad: Dar al-‘Ashimah, 1996), hal 477
[89] Teksnya berbunyi penelitian وإِني لأَجد له في قلبي لَوْطاً ولَيْطاً يعني الحُبَّ اللازِقَ بالقلب ولاط حُبُّه بقلبي يَلوط لَوْطاً لَزِقَ. Lihat, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar as-Shadir, tt) vol. VII. hal 394.
[90] Muhyiddin bin Ahmad Musthafa Darwisy, I’rab al-Qur’an wa Bayanuhu, (Damaskus dan Beirut: Dar al-Yamamah, 1415H ), vol. III, hal 395.
[91]عن واثلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «سحاق النساء بينهن زنا. Hadis tersebut diriwayatkan Abu Ya’la, dan at-Thabrani, rijalnya tsiqah. Lihat al-Hafidz Nur ad-Din Ali bin Abi Bakr al-Haitsami, Majma’ Dzawaid wa Manba’al-Fawaid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), vol. VI. hal 227
[92]Wizarah al-Awfaq wa Syuun al-Islami, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (tt: Dar as-Safwah, 1427H), vol. XXIV. hal 251
[93] Husein Muhammad et al, Fiqh Seksualitas… hal 17
[94] Yasien Mohamed. “Fitrah And Its Bearing On The Principles Of Psychology.”American Journal of Islamic Social Science 12.1 (1995), hal 2
[95] Baharuddin, Aktualisasi Psikolog Islam…., hal 17
[96]Louis Ma’luf dan Fr. Bernard Tottel, Qamus al-Mujid (Bairut:Darul al-Mausyaraq, 2003) hal. 577
[97]Dyayadi, M.T, Kamus Lengkap Islamologi, (Yogyakarta, 2009), hal.181
[98] Achmad Warson Munawar, Kamus Al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal.1063
[99] Baharuddin, Aktualisasi Psikolog Islam….hal 27.
[100] QS. adz-Dzariyat: 56
[101] Al-Maraghi menjelaskan bahwa makna “وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ” dalam surah adz-Dzariat: 56 adalah manusia diciptakan untuk mengenal Allah lalu menaatinya, sehingga pengetahuan tentang-Nya adalah pra-syarat ketaatan. Amhad bin Mustafa al-Maragi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo: Syirkah Mustafa Bab al-Halabi wa Abnah, 1946), vol. XXVII, hal 13.
[102] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to The Metaphysics of Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hal 144
[103] Hadis yang dimaksud adalah hadis riwawat Bukhari:
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ” مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاف لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِق ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
[104] Teks aslinya berbunyi penelitian
وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر الجامع لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره .
Muhammad bin Abu Bakar Ayyub az-Zar’i Abu Abdullah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ighatsah al-Luhfan, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1975) vol I, hal 7.
[105] Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhdhal Abū al-Qāsim al-Ragib al-Asfahani, al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān, (Damaskus: Dār al-‘Ilm, 1412 H), vol I. hal 468.
[106] QS. Al-A’raf (7): 80-81.
[107] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena….hal 144
[108] QS. Asy-Syams (91):
[109] Al-Husain bin Muhammad bin Mufadhdhal Abu al-Qasim al-Raghib al-Asfahani, Mufradat fi Gharib…hal 626.
[110] Ini merujuk kepada hadis yang telah disebutkan sebelumnya yakni lafal penelitian فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِه
[111] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena….hal 145
[112] QS. Yusuf (12): 53
[113] Abu Muhammad Sahl bin Abdillah bin Yunus bin Rafi’ at-Tustari, Tafsir at-Tustari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1423 H), vol I, hal 82
[114] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena….hal 145
[115] QS. Al-Qiyamah (75): 2
[116] Jalal ad-Din Muhammad Ahmad al-Mahalli dan Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, Tafsir al-Jalalaini, (Kairo: Dar al-Hadis, tt), vol I. hal 779.
[117] Muhammad bin Abu Bakar Ayyub az-Zar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ighatsah al-Luhfan…vol. I, hal 9.
[118] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena….hal 147
[119] QS Al Mukmin:60
[120] QS. Al-Fajr (89): 27
[121] Alauddin Ali bin Muhammad Abu al-Hasan al-Khazin, Lubab at-Ta’wil bi Ma’ani at-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415), vol. IV, hal 428
[122] QS. Al-Baqarah (2): 286
[123] QS. Az-Zumar (39): 53- 54
[124] Ayat yang dimaksud adalah
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Lihat penelitian Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad az-Zamakhsyari, al-Kasyaf an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiy), vol. III. hal 473
[125] Angelo Bertolo, The Imminent Collapse of America and of the Whole Western Civilization, (Indiana: iUniverse, 2012), hal 166.
[126] QS. Al-Baqarah (2): 30
[127] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena … hal 145
[128] Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnathi as-Syathibi, al-Muwafaqat, (tt: Dar Ibn ‘Affan, 1997), vol. II. Hal 17 – 19.
[129]Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, Ihya’ Ulim ad-Din, (Kairo: Lajnat Nashr al-Thaqafa al-Islamiyya, 1356 H), vol XI. hal 2100
[130] Hadis yang dimaksud adalah hadis panjang yang didalamnya terdapat lafal berbunyi penelitian إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوب النَّاس وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ. Hadis diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri. Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi dalam penjelasan ringkasnya tentang hadis ini mengikuti Imam Nawawi yang memaknai bahwa Nabi Muhammad hanya menghukumi zahirnya perilaku, sedangkan rahasia hati diserahkan kepada Allah. Lihat Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar bi Naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ila Rasulillah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, tt) vol. II, hal 742
[131] Al-Wazir Abu al-Muzaffar Yahya bin Muhammad bin Hubairah asy-Syaibani, Ikhtilaf al-Aimmati al-‘Ulama, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyah, 2002), vol. II. hal 255 – 256
[132] Wizarah al-Awfaq wa Syuun al-Islami, Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah…., vol. XXXV. hal 342
[133] Ibid. hal 340
[134] Abd ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), vol. V. hal 136
[135] Ibid, hal 339 – 342.