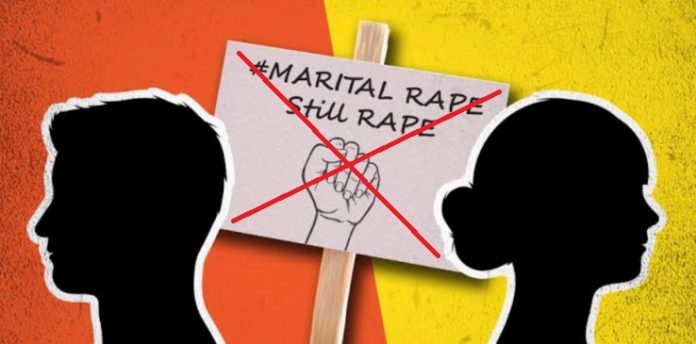oleh Fajri M. Muhammadin, S.H., LL.M., Ph.D (Cand)*
PENDAHULUAN
Salah satu perdebatan pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah terkait Marital Rape. Dalam perdebatan tersebut ada pihak pendukung konsep marital rape yang berhujjah dengan hukum Islam. Khususnya, dikatakan bahwa Islam mengakui larangan terhadap marital rape karena jelas sekali ada kewajiban mempergauli pasangan (suami atau istri) dengan baik dan haram hukumnya menyakiti suami atau istri. Dengan argumen tersebut, muncul fenomena menarik. Sebagian kalangan “Islamis” yang secara umum menolak RUU PKS justru turut mendukung kriminalisasi marital rape.
Akan tetapi, penulis menemukan bahwa pendapat seperti ini adalah akibat kesalahfahaman tentang konsep marital rape itu sendiri. Sebelumnya, penulis pernah menjelaskan masalah ini dalam tulisan yang telah disederhanakan untuk mempermudah pembaca.[1] Kali ini penulis mencoba untuk menguraikan dengan sedikit lebih mendalam agar menjadi jelas penarikan kesimpulan yang dimuat dalam tulisan singkat sebelumnya.
Sesungguhnya, pendapat yang lebih tepat terkait marital rape dan Islam adalah sebagai berikut:
Islam melarang menyetubuhi suami/istri dengan paksaan kekerasan, tapi tidak mengenal konsep “marital rape”.
Kesalahfahaman yang timbul biasanya adalah mengira bahwa marital rape sama dengan “menyetubuhi suami/istri dengan paksaan kekerasan”. Padahal terdapat perbedaan sangat fundamental yang membuat keduanya saling menyelisihi, sedangkan masih banyak yang belum memahaminya. Ada empat poin yang perlu difahami untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan fundamental ini.
POIN 1: HUBUNGAN RAPE, SEXUAL AUTONOMY, DAN PERNIKAHAN
Pertama, harus difahami secara utuh dulu apa maksud “marital rape”. Karena sebuah term mewakili sebuah konsep yang khusus. Salah satu yang menjadi masalah adalah orang awam sering menilai keliru sebuah istilah dan memberi makna sendiri, misalnya kekeliruan mengira bahwa “Genosida” bermakna “pembantaian massal” padahal konsep legalnya bukan itu.[2]
Karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu konsep hukum “rape” (perkosaan) karena banyak yang mengira bahwa ia bermakna melakukan seks dengan kekerasan fisik maupun psikis. Hal tersebut memang termasuk dalam perkosaan, akan tetapi ada poin fundamental yang tersirat dalam pemahaman tersebut dan akan menjadi tersurat apabila kita gali konsepnya lebih dalam.
Simpelnya: ‘perkosaan’ adalah seks di luar kehendak korban.
Jen Rubenfeld mengatakan bahwa ini adalah pandangan yang diterima secara umum.[3] Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) menjelaskan bahwa, sesuai hukum yang diterima secara internasional, salah satu unsur dari perkosaan adalah tidak adanya persetujuan atau kesukarelaan korban.[4]
Sedangkan Marital Rape merupakan rape (sebagaimana dipaparkan di atas) pada pelaku dan korban yang terikat pernikahan. Sehingga, seorang suami yang menyetubuhi istri (atau istri menyetubuhi suami) di luar kehendak si istri atau suami itu dapat terkena hukuman pidana.
Kekerasan fisik dan psikis tentu merupakan unsur yang sering dibahas, apalagi dalam banyak kasus perkosaan melibatkan penganiayaan. Apabila korban perkosaan sampai cedera atau mengalami gangguan psikis, tentu hukumannya bisa bertambah berat. Akan tetapi, nampaknya kekerasan fisik dan psikis sekedar menjadi contoh-contoh dari unsur yang utama: dilanggarnya kehendak.
Karena itu, secara konseptual difahami bahwa ‘rape’ adalah kejahatan terhadap sexual autonomy (‘otonomi seksual’).[5] Sehingga untuk memahami ‘rape’ ini kita tidak bisa lepas dari memahami sexual autonomy.
Sexual autonomy sangat sederhana: “tiap orang berhak memilih mau berhubungan seksual dengan siapa dan dalam keadaan apapun”.[6] Maknanya, dalam keadaan apapun seseorang memiliki hak seksual mutlak atas dirinya sendiri dan tidak dapat diintervensi orang lain.
Bila difahami lebih lanjut akan kita sadari hal ini bermakna bahwa ikatan pernikahan juga termasuk dalam kategori “berhak memilih… dalam keadaan apapun.” Karena itu, difahami juga bahwa atas alasan sexual autonomy, pasangan suami-istri pada dasarnya tidak memiliki hak seksual atas pasangannya kecuali apabila pasangannya itu menginginkannya.[7] Inilah dasar pemahaman mengapa pelaku marital rape diberi hukuman pidana.
POIN 2: NIKAH, HALAL HARAMNYA SEKS, DAN SEXUAL AUTONOMY
Dalam Islam hukum asal hubungan seksual adalah haram kecuali bila sesuatu membuatnya halal, yaitu akad nikah.[8] Hubungan seksual yang haram disebut dengan zina sebagaimana dalam Firman Allah, Surah Al-Mu’minun ayat 5-7:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)
“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. ” (QS. Al Mu’minun: 5-7)
Dalam Islam sangat jelas bahwa suami memiliki hak bersetubuh atas istrinya, dan istrinya itu tidak boleh menolak kecuali ada halangan (haid, sakit, kecapekan, dan lain-lain). Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim:
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
“Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh.”[9]
Akan tetapi perlu dicatat bahwa Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 228:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”
Dari akad nikah (artinya, diperjanjikan oleh kedua belah pihak), lahirlah hak atas hubungan seks yang bersama-sama dimiliki oleh suami maupun istri. Hak ini sifatnya adalah satu ke atas lainnya, sehingga memunculkan kewajiban. Maka darinya jumhur ulama mengatakan bahwa wajib juga hukumnya suami untuk berhubungan seks dengan istrinya.[10] Dengan demikian, suami dan istri memiliki hak seksual atas satu sama lain, bukannya mutlak hak individu belaka.
Oleh karena itu dapat dikatakan dengan jelas bahwa konsep sexual autonomy adalah konsep bathil. Selain karena ia membebaskan perzinaan dilakukan asalkan suka sama suka, ia juga menolak/menafikan adanya hak seksual pasangan menikah atas satu dengan lainnya.
Tapi apakah lantas boleh memaksakan hubungan seksual apalagi sampai menganiaya?
POIN 3: IGHTISHAAB DAN PERKOSAAN
Dalam Islam dikenal istilah al-ightishab dan inilah yang mirip perkosaan sebagaimana dipahami pada umumnya. Para fuqaha menyebutnya sebagai Al-Ikrah ‘ala Zina (pemaksaan untuk berzina).[11]
Terkait al-ightishab, kuncinya ada pada dua term tadi: Al-Ikrah (pemaksaan) dan Zina (persetubuhan yang haram). Karena zina-nya, al-ightishab prinsipnya dikenai hukuman hudud.[12] Sedangkan karena Al-Ikrah-nya, korbannya tidak kena hukuman karena dipaksa, sedangkan pelakunya bisa dipaksa membayar kompensasi senilai mahar (menurut sebagian ulama) dan bahkan tergantung situasinya bisa dikenai hukuman tambahan sampai hukuman bunuh.[13]
Penjelasan singkat mengenai al-ightishab memberikan tiga poin penting yang harus diingat:
Pertama, pemaksaan untuk berzina adalah sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam dan merupakan pidana yang hukumannya sangat berat.
Kedua, ‘pemaksaan’ pada al-ightisab bukanlah sebagaimana dalam rape. Ia bukan berakar pada konsep sexual autonomy (yang tidak dikenal dalam Islam). Justru, ‘pemaksaan’ di sini terkait dengan (a) pengecualian korban dari hudud, dan (b) tergantung caranya, cara dapat memperberat hukuman kepada pelaku di samping hukuman yang sudah ada.
Ketiga, zina menjadi unsur penting (di samping Al-Ikrah). Sedangkan hubungan seksual antara suami dan istri tidaklah dapat dikategorikan sebagai zina.
Dengan demikian, sampai di sini jelas bahwa Islam tidak mengenal marital rape. Term ‘rape’ atau perkosaan tidak masuk akal untuk terjadi dalam konteks hubungan suami istri, sebagaimana anehnya frasa “turun ke atas”.
Tapi apakah berarti Islam membolehkan menganiaya pasangan untuk memaksa berhubungan seks?
POIN 4: MEMILIKI HAK BUKAN BERARTI BOLEH MENGAMBILNYA DENGAN CARA BATHIL
Secara umum, manusia diperintahkan berbuat segala sesuatunya dengan cara yang sebaik-baiknya. Shaddad ibn Aws meriwayatkan Nabi Muhammad ﷺ bersabda:
إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ
“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.” (Sahih Muslim)
Selain mewajibkan ihsan pada segala sesuatu, hadits ini menyebut juga bahwa hewan dan pelaku kejahatan pun harus dibunuh dengan cara yang baik.[14] Apatah lagi antara suami dan istri yang seyogyanya saling mencintai dan mengasihi?
Firman Allah dalam Surah Al-Nisa ayat 19:
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
Maksud dari “bergaullah dengan mereka secara patut” ini mencakup semua hal, perkataan maupun perbuatan hingga pemenuhan hak dan kewajiban.[15] Tentunya ini juga termasuk dalam hubungan seksual yang mana Islam memiliki panduan supaya aktivitasnya bisa joss bagi kedua belah pihak.[16] Karena itu sudah pastilah haram hukumnya untuk melakukan apapun yang buruk, apatah lagi kepada suami atau istri sendiri.
Dalam Islam dikenal nusyuz atau perbuatan durhaka yaitu apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajiban menurut syariat atau bahkan menyakiti satu sama lain.[17] Tergantung tingkat keparahan situasinya, bisa saja ini dijadikan dasar untuk menggugat cerai atau bahkan pemidanaan.
Penulis belum berhasil menemukan literatur atau dalil yang khusus membicarakan tentang suami yang memaksa istrinya (atau istri memaksa suami) bersetubuh hingga menganiayanya. Akan tetapi perintah yang umum harus diterapkan secara umum kecuali terdapat dalil yang mengecualikannya.[18] Jelas ada perintah umum berbuat ihsan dan larangan untuk menganiaya, apalagi kepada suami atau istri sendiri, dan tidak nampak ada pengecualian dalam memaksakan hubungan seks.
Memang ada kalanya suami dibolehkan memukul istri ketika terjadi nusyuz, tetapi tentu saja ada ketentuan-ketentuannya. Ia hanya boleh dalam nusyuz, merupakan alternatif terakhir, tidak boleh mengenai bagian-bagian sensitif dan memukulnya tidak boleh menyakitkan.[19] Terkait syarat “tidak boleh menyakitkan”, suami dibenarkan memukul istri hanya jika dua sub-syarat utama terpenuhi sekaligus, pertama yaitu ada nusyuz pada istri dan kedua, pukulan tersebut tidak menyakitkan istri. Sedangkan kalau tidak terpenuhi satu syarat saja, misalnya memukul dengan cara yang menyakitkan meskipun disebabkan istri yang nusyuz, maka suami bisa dikenakan hukuman.[20]
Kalau (misalnya) seorang suami memaksa istri untuk bersetubuh dengan menganiaya, tidak mungkin ia memenuhi standar memukul yang dibolehkan di atas. Pertama, belum tentu ada nusyuz. Kedua, kalaupun ada nusyuz, tapi pastilah ia menyakitkan. Ketiga, pastilah menyakiti organ sensitif (yaitu kemaluan). Sehingga, tidak mungkin seorang suami memaksa istri (atau pun sebaliknya istri memaksa suami) melainkan ia pasti melanggar syariat sebagaimana dijelaskan di atas.
Karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, Islam melarang suami menganiaya istri (atau istri menganiaya suami). Dengan atau tanpa melibatkan tindakan seksual, penganiayaan tersebut adalah bersifat salah.
Akan tetapi, kesalahan di atas tidak ada hubungannya dengan halal atau haramnya hubungan seks tersebut. Islam memisahkan kedua isu itu. Halal atau haramnya hubungan seks tidak terpengaruh oleh halal-haram cara melakukannya. Maksudnya, hubungan seks antara suami istri tidak akan berubah menjadi haram (yaitu jadi zina) serta mertakarena dilakukan dengan cara yang haram.
Dengan demikian, kasus pemaksaan seks dengan kekerasan fisik/psikis antara pasangan menikah ini tidak dikenai hudud zina melainkan dihukum karena penganiayaannya. Di sisi lain, melakukan perbuatan tersebut bila bukan dengan pasangan sahnya akan kena hukuman dobel: karena zina-nya juga karena Al-Ikrah-nya.
Hal ini berbeda dengan konsep marital rape dan sexual autonomy, di mana pemaksaan dan ‘kehalalan seks’ ternyata berhubungan sebab akibat. Seksnya menjadi ‘haram’ (i.e. tanpa hak) walaupun korban dan pelaku berada dalam ikatan perkawinan. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam konsep sexual autonomy hak atas seks adalah mutlak milik individu dan bukan milik orang lain, terlepas status pernikahannya.
KESIMPULAN
Sebagaimana dijelaskan di atas, seringkali ada keliru mengira bahwa “Islam juga melarang marital rape” karena “Islam melarang suami/istri menganiaya pasangannya secara seksual.” Padahal, itu adalah kesalahan pemahaman. Pemahaman yang benar adalah bahwa “Islam juga melarang marital rape” ternyata tidak sama dengan “Islam melarang suami/istri menganiaya pasangannya secara seksual.”
Telah dijelaskan bahwa “Islam melarang suami/istri menganiaya pasangan secara seksual” tidak berarti afirmasi Islam terhadap konsep marital rape. Marital rape menjadi bertentangan dengan Islam karena ia memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan dari konsep sexual autonomy. Hal ini berbeda dengan Islam yang memandang bahwa urusan seksual dalam bingkai pernikahan bukanlah semata-mata hak mutlak individu dalam keadaan apapun, melainkan masing-masing pasangan juga memiliki hak atas satu sama lain.
Dalam Islam, paksaan untuk berhubungan seksual baik dari pihak suami atau istri berpotensi jatuh kepada penganiayaan dan bukan perkosaan, karena perkosaan hanya berlaku pada mereka yang tidak memiliki hak terhadap pasangannya. Sedangkan sepasang suami istri menyimpan hak satu sama lain, dalam diri istri tersimpan hak suami, begitupun sebaliknya. Namun perlu diingat, sekedar karena seseorang memiliki hak atas sesuatu (pada diri orang lain), tidaklah bermakna dia boleh mengambilnya dengan cara yang buruk, ini karena Islam begitu menjunjung tinggi ihsan bahkan dalam hal apapun.
*Dosen di Departmen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. dan peneliti The Center for Gender Studies.
[1] Dapat dilihat di tautan berikut ini: Fajri Matahati Muhammadin, “Apakah Islam Mengenal Konsep ‘Marital Rape’?,” UGM Staff Blog, 2019, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2019/10/13/apakah-islam-mengenal-konsep-marital-rape/.
[2] Fajri Matahati Muhammadin, “GENOSIDA: Istilah Secara Hukum vs ‘Penggunaan Populer,’” 2015, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2015/04/15/genosida-istilah-secara-hukum-vs-penggunaan-populer/. Lihat juga penjelasan Al-Attas tentang perbedaan makna agama dalam konsep Barat versus Islam (sekaligus penjelasan terminologis, kenapa ‘agama’ pun tidak zahir mudah difahami kecuali mengenal konsep dari Bahasa aslinya): Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), Perenggan 11-13.
[3] Jed Rubenfeld, “The Riddle of Rape-by-Deception and the Myth of Sexual Autonomy,” Yale LJ 122 (2012): 1376.
[4] Prosecutor vs Kunarac et al, Trial Chamber, Case No. IT-96-23, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, paragraph 453-456. Mahkamah ini adalah mahkamah pidana internasional ad-hoc, tapi penjelasannya pada poin ini merujuk pada praktek-praktek hukum pidana di dunia.
[5] Ibid, paragraph 457. Lihat juga tulisan Rubenfeld atau tulisan-tulisan lain tentang perkosaan apalagi yang terkait dengan HAM, semua menghubungkannya dengan sexual autonomy.
[6] Terjemahan bebas dari: Rubenfeld, “The Riddle of Rape-by-Deception and the Myth of Sexual Autonomy,” 1379.
[7] Perlu dicatat juga bahwa pemahaman ini juga bermakna bahwa tanpa adanya pernikahan, kehendak untuk melakukan hubungan seks pun tetap dibenarkan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, menurut konsep sexual autonomy, pernikahan tidak berdampak apapun.
[8] Sa‘d bin Nāṣir Al-Shathri, Sharḥ Al-Manẓumatu Al-Sa‘diyah Fî Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah, 2nd ed. (al-Riyāḍ: Dar Kanuz Ishbiliya, 1426), 81–87. Sebetulnya ada juga perbincangan mengenai raqabah, tapi itu memerlukan diskusi panjang tersendiri dan tidak relevan dalam topik ini.
[9] Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, Sahih Al-Bukhari, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 3237; Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, Sahih Muslim, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 2007), hadits no.3538.
[10] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ed. Muḥammad Nāṣiruddīn Al-Albānī (tahqiq and takhrij), vol. 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 407–8. Menurut Sayyid Sabiq di atas, mazhab Syafi’i adalah yang berbeda posisinya. Tapi ternyata ada juga kitab Mazhab Syafi’I yang menyebutkan hal senada. Lihat: Abu ’Abdillah Muḥammad al-Tihāmī Al-Fāsī, Qurrat Al-‘Uyūn Bi Sharḥ Naẓmi Ibn Yāmūn (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1425), 125–26.
[11] ʿAbd Allāh b. Aḥmad ibn Qudāmah Al-Maqdīsī, Al-Mughni, vol. 9 (Maktabah Al-Qahirah, 1388), 59; Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi Sahl Al-Sarkhasī, Al-Mabsūṭ Fī Al-Fiqh, vol. 24 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1409), 89. Ulama kontemporer semisal Wahbah Al-Zuhayli menggunakan juga istilah al-wath’u bi al-ikrah atau al-wath’u bi al-ightisab: Wahbah al-Zuḥaylī, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 2006), 294. Akan tetapi, inti konsepnya sama saja.
[12] Yaitu rajam bila ia sudah menikah, atau 100 cambuk dan pengasingan bila belum menikah.
[13] Muhammad Saalih Al-Munajjid, “حكم جريمة الاغتصاب ؟,” islamqa.info, accessed October 16, 2019, https://islamqa.info/ar/answers/72338/حكم-جريمة-الاغتصاب.
[14] Yaḥya ibn Sharaf Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim Sharḥ Al-Nawawī, vol. 13 (Beirut: Dār Ihya Al-Turath Al-‘Arabi, 1392), 107; ‘Alī ibn Muwaffaq ibn Al-ʿAṭṭār, Sharḥ Al-Arba‘īn Al-Nawawiyyah (Dār al-Bashā’ir al-Islamiyyah, 1433), 112.
[15] Jalāl al-Dīn Al-Maḥallī and Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, Tafsīr Al-Jalālayn, ed. Ghazi bin Muhammad ibn Talal (Amman: Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2007), 87.
[16] Lihat misalnya: Abu Umar Basyier, Sutra Ungu : Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam (Rumah Dzikir: Surakarta, 2005); Yasir Qadhi, Like a Garment: Intimacy in Islam (Yasir Qadhi, 2019), https://d1.islamhouse.com/data/en/ih_books/single/en_Like_A_Garment.pdf.
[17] Musthafa Al-Bugha and Musthafa Al-Khin, Al-Fiqh Al-Manhaji, vol. 4 (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), 106; Wahbah al-Zuḥaylī, Tafsīr Al-Munīr, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 2005), 57, 301.
[18] Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ushul Fiqih (Yogyakarta: Media Hidayah, 2008), 58–59; ‘Abd al-Karim Zaydan, Synopsis on the Elucidation of Legal Maxims in Islamic Law, trans. Md. Habibur Rahman and Azman Ismail (Kuala Lumpur: IBFIM, 2015), 25.
[19] Muhammad Saalih Al-Munajjid, “ضرب زوجته فغادرت البيت وذهبت إلى المحاكم الوضعية لتحكم لها بالطلاق,” islamqa.info, accessed October 16, 2019, https://islamqa.info/ar/answers/219574/ضرب-زوجته-فغادرت-البيت-وذهبت-الى-المحاكم-الوضعية-لتحكم-لها-بالطلاق.
[20] Untuk perinciannya dilihat di: “أقوال العلماء في القصاص من ضرب الزوج,” Islamweb.net, 1423, https://www.islamweb.net/ar/fatwa/25387/أقوال-العلماء-في-القصاص-من-ضرب-الزوج.